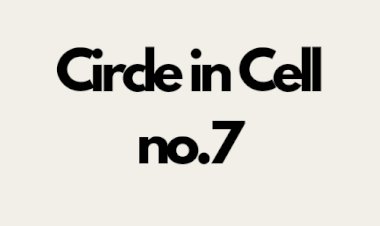Tuhan adalah Jin dalam Lampu Aladin
Tuhan bagi manusia di era digital ini adalah jin dalam lampu Alladin yang cukup digosok dengan dua tiga kali doa.

TUHAN ADALAH JIN DALAM LAMPU ALADIN
/1/
Seorang teman saya, pensyair muda Jakarta, mengeluh lagi. Sajak-sajaknya tak kunjung dimuat. Menurutnya, sajak yang dimuat di harian bergengsi nasional itu biasa saja, tidak lebih baik dari sajak-sajaknya. Semua upaya sudah dia lakukan: pendalaman konten, berinovasi dengan banyak hal, termasuk juga membuka jejaring dengan komunitas sastra, dan terus belajar dari banyak sumber. Tetapi, karyanya tak kunjung dimuat. Kenapa Tuhan begitu kikir untuk sekadar mengabulkan doa saya yang hanya sekerat itu? tanyanya retoris.
Dalam bentuk yang lain, pada orang yang lain, gugatan yang sama sering kali muncul. Kadang, mengambil bentuk penyakit yang tak kunjung sembuh. Kadang pula mewujud dalam jodoh yang tak juga tiba sementara batang usia semakin meninggi. Di titik lain, menjelma dalam bentuk hancurnya bisnis, rumah tangga, dan kemalangan lain.
Di mana Tuhan?
/2/
Perjalanan manusia mengenal Tuhan tentu bukan perjalanan pendek dan sederhana, sependek cerita Bawang Merah Bawang Putih, apatah lagi sesederhana legenda Malin Kundang. Fase ontologis di awal kehidupan manusia secara jelas menunjukkan lemahnya kuasa manusia terhadap alam. Itulah sebab, muncul animisme dinamisme. Segala hal yang lebih besar dan lebih menakjubkan dari manusia dianggap sebagai Tuhan dan (karena itu) diperlakukan dengan sangat agung. Upacara gugur gunung, rutinitas meletakkan sesajen di bawah pohon besar, ataupun melarung kepala kerbau ke laut adalah bentuk dari pengagungan tersebut. Permintaan turunnya hujan, keberhasilan panen, dan sekian permintaan lain diwujudkan dalam banyak persembahan.
Metamorfosis dari animisme dinamisme menuju kepercayaan terhadap Tuhan, tentu bukan hal yang mudah. Sekian banyak lelaki mulia telah hadir di muka bumi ini dengan menyebut dirinya sebagai utusan Tuhan, lengkap dengan bukti tak terbantahkan dan wahyu dari Tuhan langsung. Toh, hal itu tidak menjadi jaminan bahwa seluruh manusia lantas percaya dan tunduk pada Tuhan. Perlawanan atas keberadaan Tuhan seringkali muncul semata-mata atas dasar keengganan melepas keyakinan yang sudah membudaya ataupun atas dasar pertimbangan sosial politik. Penolakan bangsa Arab terhadap ajaran tauhid Islam didasarkan pada keengganan melepaskan diri dari berhala-berhala yang disembah ratusan tahun. Penolakan atas dasar sosial politik bisa kita lihat pada Firaun yang menganggap Tuhan sebagai pesaing kekuasaan mutlaknya.
Maka muncullah dua dikotomi besar ini: pemeluk teguh dan pengingkar keberadaan Tuhan; percaya-tidak percaya; beriman-atheis. Tentu, tidak ada yang bisa memaksa ketika seseorang memilih untuk meragukan bahkan tidak percaya pada Tuhan. Pun, firman Tuhan sejak awal sudah menyampaikan bahwa tidak ada paksaan untuk itu karena konsekuensi beriman dan tidak beriman sudah sangat jelas. Sangat boleh jadi, dikotomi ini merupakan dikotomi abadi yang ada di sepanjang zaman.
/3/
Bagaimana dengan abad digital ini?
Abad digital merupakan salah satu hasil dari revolusi industri. Saat ini, penelitian ilmiah dan banyaknya inovasi telah menghasilkan teknologi berlimpah yang memudahkan hidup manusia. Pesawat antariksa dan misi luar angkasa, satelit, telepon genggam, hingga berbagai aplikasi yang dapat diakses dengan mudah telah memunculkan revolusi di berbagai bidang. Informasi terbaru terkait penembakan di mesjid Australia, misalnya, bisa diakses siapapun dengan mudah, cepat, dan detil. Berbelanja tidak lagi harus datang, mencari, dan menunggu di kasir sehingga membuang banyak waktu dan tenaga. Sejumlah aplikasi pembelian daring, lengkap dengan sistem pembayaran daring, sudah tersedia. Media sosial telah memungkinkan kehidupan pribadi seseorang diakses siapapun. Aplikasi pokemon go bahkan berhasil merekam begitu banyak titik koordinat yang tidak dapat dijangkau satelit. Dengan itu, seorang yang diklaim sebagai teroris berhasil dibekuk dengan mudahnya. Teknologi telah mengubah hidup manusia secara revolusioner sehingga menjadi lebih mudah dan praktis.
Di titik yang sama, terjadi juga revolusi di bidang spiritual. Acara makan (bersama) tidak lagi diawali dengan doa (bersama) tetapi memfoto makanan yang disajikan lalu mengunggahnya di media sosial. Puasa tidak lagi untuk mensucikan jiwa tetapi untuk diet dan sekian uraian yang menekankan kebermanfaatan untuk kesehatan tubuh. Hingar-bingar media sosial hanya menyisakan segala hal yang bersifat menarik perhatian. Urusan esensi dan kepadatan kualitas spiritual dan ibadah menjadi urusan nomor buncit, demikian Haryatmoko, pakar filsafat UGM, menegaskan.
Tidak dapat dipungkiri, kecanggihan teknologi telah melahirkan kemudahan hidup dalam jumlah yang berlimpah. Ujung dari keberlimpahan itu adalah munculnya era yang disebut Jean Baudrillard, filsuf Prancis, sebagai era simulasi. Petit Robert menyebut era ini sebagai simulacrum, yakni era di mana segala hal yang tampak menyatakan diri sebagai realitas padahal hanya refleksi, bukan realitas itu sendiri.
Baudrillard merumuskan, salah satu ciri era simulasi ini adalah penghapusan acuan melalui kebangkitan artifisial. Keagungan dan kesakralan dalam berdoa, memberi pada yang papa, kekhusyuan dalam beribadah mengalami kemerosotan makna karena digantikan dengan hingar-bingar narsisme di media sosial. Terjadi pergeseran dalam memaknai ritual yang semula dianggap suci. Sebagaimana yang telah dikemukakan di atas, puasa yang tadinya diacu sebagai upaya untuk menyucikan jiwa telah bergeser pada acuan baru yang sangat terbatas: diet, kesehatan, dan kerampingan tubuh.
Tuhan tidak lagi menjadi tempat kembali dari semua urusan. Media sosial telah menjadi tempat mengadu, melaporkan, dan menuntaskan semua gundah hati, bahkan menyelesaikan sengketa dengan orang lain. Kecanggihan teknologi telah menghasilkan banyak hal instan: belanja, informasi, dan akhirnya komentar instan tanpa mengecek kebenarannya.
Pada gilirannya, relasi dengan Tuhan pun mengalami reduksi. Keserbainstanan hidup menjelma juga dalam keserbainstanan yang terkait dengan Tuhan. Tuhan menjelma jin dalam lampu Aladin yang cukup digosok dengan dua tiga kali doa. Tuhan harus sudah keluar dan berkata, apa permintanmu, hambaKu? Kemudian, dalam waktu yang instan, permintaan berbungkus doa itu sudah harus terkabul. Manusia kemudian marah dan kecewa ketika permintaan yang digosok dengan dua tiga kali doa itu tidak terwujud. Semua kemarahan dan kekecewaan itu kemudian tumpah dan meluap di media sosial atau pada peer group di sebuah tempat yang disebut banyak sosialita jetset sebagai "bukit perghibahan". Jika tidak, kemarahan itu bisa saja menjelma dalam gumam gugat sebagaimana teman saya si pensyair muda Jakarta itu: Kenapa Tuhan begitu kikir untuk sekadar mengabulkan doa saya yang hanya sekerat itu?
Tuhan jelas tak dianggap mempunyai otoritas untuk menerima atau menolak permintaan. Tuhan harus tunduk pada permintaan manusia abad digital. Tak ada lagi ingatan akan kasih Tuhan yang menunda pengabulan doa karena ingin mendengar rintih syahdu hambaNya dalam berdoa. Telah terhapus pemahaman bahwa tidak terkabulnya doa adalah bentuk penyelamatan Tuhan pada manusia. Telah hilang jejak ingatan bahwa Tuhan selalu punya rencana indah dari setiap situasi yang ada, seburuk apapun itu. Barangali sudah sempurna lenyapnya pemahaman atas firman Tuhan, “Boleh jadi kamu sangat menginginkan sesuatu padahal itu sangat buruk untukmu, sementara yang paling tak kau inginkan justru itu yang menyelamatkanmu.” Manusia cenderung lupa bahwa hanya Dialah yang tahu mana yang terbaik untuk manusia. Pun, lupa bahwa mengabulkan, menunda, bahkan menolak doa adalah murni hak prerogatif Tuhan.
Keserbainstanan tidak saja memosisikan Tuhan sebagai jin dalam lampu Aladin tetapi juga memosisikan manusia sebagai makhluk yang sangat percaya diri dengan semua yang dipikirkan, dirasakan, dan diputuskannya sendiri.
/4/
Maka, di mana Tuhan?
Dalam sebuah aksi demonstrasi mahasiswa di Semanggi, Jakarta, Mei 1998, desing peluru mendadak bertebaran di atas kepala mahasiswa demonstran. Ada Abel, Kris, Rico, dan Made (sebut saja begitu) yang di kampus begitu gagah berani memproklamasikan diri sebagai atheis dan dengan penuh kebencian menafikan semua hal terkait dengan Tuhan. Namun, desing peluru yang membabi buta itu meruntuhkan semua kesombongan dan pengingkaran atas eksistesi Tuhan. Teriakan Allahu Akbar, Yesus, Budha Sidharta, dan Sang Hyang Widhiyasa menggelegar hebat dari mulut mereka mengalahkan desing peluru yang terus mencari jantung dan mata demonstran yang lengah.
Maka, di manakah Tuhan? Dia terucap penuh sungguh ketika nyawa berada di ujung tanduk. Ini jelas sebuah ambivalensi yang unik. Pengingkaran bisa saja terjadi di mana dan kapan saja. Namun pengakuan tentang keberadaan Tuhan dan kebergantungan pada Tuhan pasti akan hadir dengan sendirinya ketika keadaan amat sangat terjepit dan luar biasa kritis.
Bisa saja manusia abad digital ini memosisikan Tuhan sebagai jin dalam lampu Aladin. Namun, yang tak pernah bisa dinafikan adalah keberadaan Tuhan dalam dirinya dan kebergantungan pada Tuhan, terutama dalam hal yang bersifat amat sangat kritis.
Samarinda, 17 Desember 2019
Dapatkan reward khusus dengan mendukung The Writers.
List Reward dapat dilihat di: https://trakteer.id/the-writers/showcase.

 inikifti
inikifti