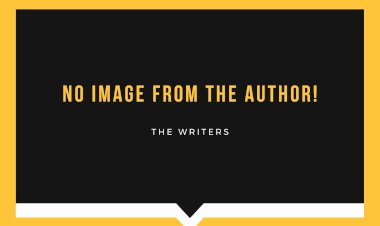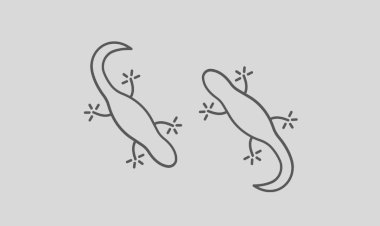Anak Bawang
Bagaimana rasanya menjadi anak bawang?

Di antara anak Mampang, aku memang paling bogel dan paling muda dari segi umur. Walaupun badan kurus, aku doyan menyamil terutama singkong rebus dan es mambo rasa coklat susu. Apalagi menyamil sambil duduk di atas bubungan garasi mobil, memandangi awan yang bergerak. Kadang-kadang gumpalan awan berlalu dengan cepat, secepat aku menghabisi satu es mambo, kadang-kadang lambat, selambat menunggu kakakku ke luar dari kamar kecil.
“Lihat! Itu ada beruang gendut yang sedang bersiul” teriakku sambil menunjuk ke awan yang sedang bergerak perlahan ke arah rumah pak Silitonga tetangga belakang rumah kami, yang punya banyak pohon mangga.
“Mana?” tanya kakakku, sambil mengenyot perlahan es mambo hijau rasa palanya.
“Di situ” seruku sambil menggunakan telunjuk, untuk memastikan beruang gendut itu bisa tertangkap mata kakakku.
“Mana?” tanyanya lagi penasaran kali ini sambal mengerenyitkan matanya.
Pada saat itu ternyata si awan beruang telah berubah bentuk. Mata beruang yang sebelumnya kecil seperti kelereng, kini telah menjadi bulat besar seperti donat, dan kepalanya terus membesar dan membulat, menyerupai dakocan, boneka balon tiup mainanku yang berwarna hitam, bermata belo dengan bulu mata lentik. Ah! Senangnya memandangi awan. Seperti memiliki layar film pribadi, dengan film yang berganti setiap hari.
Selain memandangi awan, kesukaanku adalah bermain dengan para tetangga yang tinggal di sepanjang jalan Mampang. Sebenarnya nama jalan kami adalah jalan Teuku Cik Ditiro, namun kami masih belum terbiasa, dan masih menyebutnya dengan nama lamanya jalan Mampang atau di zaman Belanda dikenal sebagai Mampangweg kata nenek dan kakekku. Sore itu, sebegitu bangun dari tidur siang, aku dan kakakku langsung mencari selop kami masing-masing dan berlari ke rumah Gina untuk bermain sore. Pekarangan rumah Gina dan rumah kami dibatasi oleh sebatang pohon belimbing dan tembok putih setinggi pinggang, sehingga kami jarang menggunakan pintu pagar depan untuk ke rumah Gina, kami lebih senang memanjat tembok.
“Hei! Kalian keenakan tidur sore ya?” sindir Gina dari teras depan rumahnya. Ia dan kakaknya Emil sedang sibuk menguntai gelang karet yang berserakan dilantai menjadi tali karet yang menyerupai ekor kucing panjang yang gemuk. Mereka dibantu para teman-teman tetangga yang lain. Sudah dua hari terakhir ini kami sibuk mengumpulkan karet gelang sebanyak mungkin. Kami mengecek semua dasar laci meja dan meneror seisi rumah untuk dimintai karet gelangnya. Dari beberapa rumah terkumpul lumayan banyak karet gelang dengan berbagai warna, dari merah bata, hijau daun hingga kuning madu. Untaian karet sepanjang tiga bentangan tangan itu kami jadikan tali loncatan. Ini salah satu permainan kegemaran kami semua, karena banyak ragam permainan yang bisa dinikmati dengan seuntai tali karet tersebut. Bahkan anak bogel seukurankupun bisa ikut bermain.
Selop karet kulepas, dan aku meniru anak-anak yang lebih besar berloncat dengan dua kaki berpijak di dalam irama putaran tali yang melenting mengikuti gerakan putaran tangan Is dan Emil. Kedua anak ini adalah yang paling jahil. Mereka berdiri saling berhadapan di kiri dan kanan seolah tiang kincir angin, dengan tangan kanan berputar dengan memegang ujung tali karet menyerupai baling-baling kincir angin. Aku serasa seperti meloncat-loncat di dalam terowongan balon yang ditiup melonjong.
“Ayo sekarang hanya boleh berpijak dengan satu kaki” usul Gina yang sudah mulai bosan dengan loncatan dua kaki. Gina agak bongsor badannya walau umurnya hanya beda setahun lebih tua dariku, kata mama karena dia berdarah bule, neneknya orang Jerman.
“Setelah semua mendapat giliran, kita beralih ke loncat 2-1-2 ya” lanjut Gina, dengan nada seperti ibu guruku, Ncik Inas. Ncik Inas adalah guru yang paling cantik se-TK Ade Irma Suryani. Bedanya Ncik Inas jika memberi aba-aba disertai gerincing rebana, sehingga kami selalu bergegas mengikuti irama gerincing itu. Loncat 2-1-2 memerlukan konsentrasi khusus, dimulai berloncat dengan satu kaki, lalu berganti menjadi dua dan kembali ke satu kaki. Untung saja tidak ada yang menyebut-nyebut mengenai es mambo, sehingga konsentrasikupun utuh, dan tidak menginjak tali karet walau sekalipun. Setelahnya semua anak harus menyebrang masuk meloncat dan keluar sementara tali terus berputar tanpa menyentuh tali karet.
“Panas. Panas. Panas” seru Is dan Emil sambil menutar tali karet, menakut-nakuti kami yang sedang mengantri menunggu giliran meloncat. Tali karet tersebut diumpamakan sebagai untaian lidah api yang panas. Perumpamaan ini membuatku kami semua semakin tegang.
“Dingin. Dingin. Dingin” balas setiap anak yang akan menyebrang, untuk menenangkan diri masing-masing ketika melewati untaian api yang siap menjilat tiap anak yang lewat. Anehnya, upaya mengelabui pikiran itu berhasil menyelamatkan kami menyeberang lorong putaran tali karet dengan selamat.
Variasi tersulit adalah berloncat berpasangan namun saling memunggungi, sebelum dilanjutkan ke aksi meloncat ketinggianan. Kali ini ada perubahan anggota regu. Pemilihan regu ditentukan dengan membentangkan jari tangan. Kami berdelapan membuat lingkaran besar, dan mulai mengayunkan tangan mengikuti irama
“Hompimpa alaium gambreng” di penekanan kata “breng” semua tangan berhenti dengan jari terbuka, sebagian dengan telapak tangan menengadah ke atas dan sebagian menghadap ke bawah. Kami hanya berhenti sampai ada jumlah yang sama antara telapak tangan yang menengadah dan yang tertelungkup. Setiap kali, aku mengharapkan agar arah tanganku searah dengan tangan Parti agar aku bisa seregu dengannya. Parti adalah anak yang tertinggi, namun agak pendiam karena kakinya penuh koreng, sehingga sering dipanggil si Koreng. Rumahnya di belakang Universitas Tujuh Belas Agustus atau kami semua menyebutnya dengan Untag. Orang tuanya menjaga kebersihan gedung universits bertingkat empat yang mirip kotak kardus putih itu. Akhirnya, dua regu terbentuk. Aku melirik ke semua pemilik telapak tangan dengan punggung di atas sama sepertiku.
“Ah!” teriakku dalam hati. Parti ternyata bergabung dengan regu yang bergeser ke bawah pohon belimbing, tidak di reguku. Aku agak kecewa, tapi menggantungkan harapan pada kepala regu kami Esti yang sekepalan di bawah Parti tingginya.
Masing-masing kepala regu kini mulai bersuit jari untuk menentukan regu yang akan mulai permainan. Disuitan jari pertama, Esti dan Emil yang didaulat sebagai kepala regu, keduanya memberikan jari jempolnya. Dua gajah beradu berarti seri, atau sama kuat. Disuitan jari kedua Esti memberikan jari kelingking yang melambangkan semut, sementara Emil tetap memberikan jari jempolnya yang melambangkan gajah. Berarti semut mengalahkan gajah dengan memasuki telinga gajah membuat gajah kelimpungan. Sehingga regu kami menang. Kalau saja Emil memberikan jari telunjuknya yang melambangkan orang, Regunya akan menang, karena berarti orang menginjak semut. Yang kalah memegang tali karet.
“Ssssssssssssss” Emil dan Is mengeluarkan suara desisan. Mereka berjongkok dan berdua mulai meliukan tali seperti gerakan ular. Satu persatu kami menyebrang meloncat tanpa menyentuh sang tali yang berliak liuk semakin cepat. Ini semua tentunya dimulai dari si bontot, yaitu aku.
“Aman!” seru reguku Ketika aku berhasil menghindari ular lantai tersebut. Kemudian meningkat tingginya sekuku di mana sang tali naik setara letak kuku jempol kaki, kemudian sejengkal.
Sampai ketinggian sedengkul aku masih bisa berloncat lincah. Ketika tali karet dipindahkan sepaha, aku mulai mengambil ancang-ancang meloncat dengan mundur dua langkah agar loncatan bisa sedikit lebih tinggi. Oh! kakiku menyentuh tali karet, tali yang tegang itu bergerak disambar betisku yang gempal, namun aku masih selamat sampai ke seberang. Berikutnya hatiku mulai kebat kebit, tali dinaikkan
“Setitit” seru Emil tetanggaku sambil menghentikan tinggi tali ke persis sejengkal di bawah pusarnya. Aku mundur selangkah lagi, mengharapkan dengan jarak mulai lebih jauh loncatan ku bisa lebih tinggi. Dan kali ini aku tidak berhasil melewati tinggi tali tersebut.
“Ayo, bela anak bawang” teriak Emil lagi. Gina yang lebih tinggi dariku dengan mudahnya melompat melewati tali karet dua kali. Sekali untuknya, dan sekali lagi untukku si anak bawang. Selanjutnya, mulai tali meningkat sepusar, seketek, sebahu, sekuping, aku terus harus dibela Gina tetanggaku yang rambutnya kembaran denganku berkepang dua. Waktu tali meningkat ke sekepala, giliran Gina harus dibela oleh Esti yang ceking, anak penjual pecel. Esti sangat gemulai namun juga gesit. Ketika tali karet dinaikkan ke sekepala pun, ia meloncat dengan mengaitkan satu kakinya ke atas tali tanpa kesulitan sedikitpun, lalu meloncat meliuk ke seberang tali. Kemudian ia menyelesaikan tinggi tali sejengkal di atas kepala. Di puncak permainan, Esti dan Parti harus melewati tali karet yang dinaikkan setinggi-tingginya jari tangan bisa menahan si tali lalu melewati tingkatan terakhir. Emil mengedipkan matanya ke Is yang memegang tali di seberangnya, dan keduanya perlahan menjinjit pada waktu Esti sedang melambung tinggi berusaha melewati tali karet.
“Kena” teriak Is dan Emil sambil menyerahkan tali karet ke Gina dan Esti.
“Curang” protesku yang melihat kaki yang menjinjit seketika. Namun Emil dan Is menolak tuduhan si anak bawang. Perselisihan mulut terjadi antara tim perempuan dan tim lelaki.
“Ayo! Sudah! Berdamai” usul Tambah dengan suaranya yang menggelegar. Ia yang tertua dari regu laki-laki. Tambah panggilannya si Batak, karena orangtuanya berasal dari Sumatera Utara. Ia berusaha mendamaikan adu mulut tersebut. Is dan Emil masih memberikan jempolnya yang berarti memilih untuk bermusuhan, walaupun Gina, Esti dan aku sudah memberikan jari kelingking yang berarti memilih untuk berdamai. Akhirnya setelah Tambah mengulurkan kelingkingnya dan mengaitkan ke jari kelingking regu perempuan, tanda perdamaian diterima. Is dan Emil mengikuti dari belakang dengan mengulurkan jari kelingking mereka dan mengaitkan ke jari kelingking regu perempuan.
“Merdeka!” teriak kami serempak, ketika Esti melakukan loncatan ulangan dan berhasil melewati tali karet di ketinggian puncak.
Mendekati pukul empat sore, satu persatu nama kami terdengar dipanggil dari rumah masing-masing. Dengan bersungut kami menyeret kaki pulang. Sebelum masuk pintu rumah, kutengok pohon jambu air di sebelah kiri pojok rumah. Buah-buah jambu air berwarna merah menyala, bergelayutan di dahan pohon ditiup angin sore. Aku membelok ke arah pohon jambu air dan memanjat batang terendah dan naik lagi ke dahan berikutnya ke dahan yang cukup kokoh. Kukaitkan kedua kaki dan tanganku di dahan dan menengadah ke atas. Dalam hal memanjat pohon, aku bukanlah anak bawang. Di sela-sela jambu air yang bergelayutan dengan berat, tampak langit yang mulai menggelap. Samar-samar di kejauhan awan yang menyerupai gulali raksasa berubah perlahan menjadi gepeng dan panjang menyerupai cakwe. Teringat cakwe di atas bubur ayam yang mengepul. Perutku mulai berbunyi. Anak bawang pun perlu makan.
Dapatkan reward khusus dengan mendukung The Writers.
List Reward dapat dilihat di: https://trakteer.id/the-writers/showcase.

 Ati Kisjanto
Ati Kisjanto