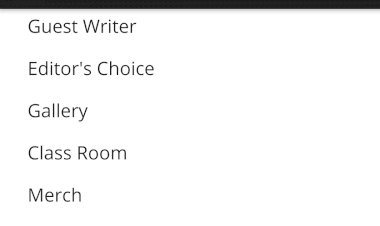TEMPOYAK, JALAN RINDU UNTUK PULANG
Buku Kuliner Nusantara - Anthology

Waktu aku kecil, saat pertama kali mencicipi tempoyak, lidahku terkejut. Asamnya menyeruak, tajam dan tak berkompromi, seperti musim hujan yang datang tiba-tiba di penghujung kemarau.
Namun, setelah suapan kedua dan ketiga, ada sesuatu yang mulai berubah. Rasa itu bukan hanya tentang keasaman atau bau durian yang menyengat. Ia perlahan membuka pintu-pintu kenangan purba, menuntun masuk ke dalam hutan-hutan tropis Sumatra, di mana rasa adalah cerita, dan makanan adalah warisan.
Aku masih ingat siang itu sepulang sekolah, selepas seragam lusuh merah putih diganti, ibuku menyodorkan sepiring nasi hangat dengan gulai tempoyak ikan patin. “Coba dulu,” katanya, “ini rasa yang hanya bisa kau mengerti dengan hati, bukan hanya lidah”. Lahapnya sekejap, perut padat terisi dan pinggan tak tersisa nasi, hatiku memuji, ibuku benar. Ini rasa yang mengoyak selera.
Aroma dari Masa Silam
Tempoyak adalah fermentasi daging durian, buahnya sendiri telah menjadi simbol ambiguitas rasa di Asia Tenggara. Ada yang mencintainya sepenuh hati, ada pula yang membencinya hingga ke sumsum tulang. Tapi ketika durian diolah menjadi tempoyak, rasanya menjelma lebih dari sekadar suka atau tidak suka. Ia menjadi pengalaman.
Tempoyak bukan sekadar makanan. Ia adalah rasa yang mengoyak, menantang lidah untuk tak hanya mencicip, tapi juga menerima, memahami, bahkan mencintai. Masamnya tak meminta maaf, aromanya tak berpura-pura manis. Ia hadir seperti masa lalu yang tak bisa dihapus, hanya bisa dikenang dan dihidangkan ulang.
Di dapur-dapur tradisional Palembang, Bengkulu, Jambi, hingga ke pelosok Lampung dan sebagian Sumatra Barat, tempoyak adalah bumbu rahasia, kadang bahkan menjadi inti hidangan. Fermentasi durian selama beberapa hari, dengan sedikit garam, mengubah rasa manis legit menjadi asam menyengat, menciptakan lapisan rasa yang tak bisa ditiru oleh cuka atau jeruk nipis apalagi oleh beragam rasa yang dikemas dalam botol plastik.
Tempoyak menjadi semacam warisan rumah. Setiap ibu, setiap nenek, punya cara sendiri menyimpan dan mengolahnya. Durian matang, dikerok dari bijinya, lalu diberi sedikit garam dan ditutup rapat, dibiarkan berhari-hari, bahkan berminggu, hingga keasaman dan keharuman fermentasi membentuk jati dirinya yang utuh.
Kala lemari pendingin belum ada, tempoyak disimpan dalam stoples kaca atau wadah tanah liat. Ada juga yang menyimpannya dalam kaleng bekas biskuit. Setiap kali dibuka, aroma khasnya menyapa seperti salam dari nenek moyang. Proses ini bukan sekadar teknik, tapi ‘ritual’.
Masakan, Sungai dan Patin
Tak ada pasangan yang lebih serasi untuk tempoyak selain ikan patin. Ikan air tawar ini berenang tenang di sungai-sungai besar Sumatra, terutama di Sungai Musi dan Batanghari. Dagingnya lembut, gemuk, dan nyaris tanpa duri. Ia menyerap bumbu dengan rakus, menjadikannya kanvas sempurna untuk tempoyak.
Gulai tempoyak patin bukan hanya menu makanan. Ia adalah kisah tentang sungai, tentang jala yang dilempar pagi-pagi, tentang anak-anak yang berenang di arus deras sambil tertawa, dan tentang ibu-ibu yang menumbuk bumbu di lesung kayu.
Gulai ini biasanya berisi santan, tempoyak, serai, lengkuas, daun kunyit, dan cabai rawit dalam jumlah yang bisa membakar langit-langit mulut. Tapi justru di situlah letak keajaibannya. Rasa asam dari tempoyak dan pedas dari cabai menciptakan gelombang rasa yang menari di mulut.
Di keluargaku, jika tak ada uang tuk membeli ikan patin, ibu mengakalinya. Sering kali aku atau adikku disuruhnya memetik buah petai di belakang rumah yang memang banyak tumbuh pohon petai. Petai menjadi campuran utama hidangan tempoyak sajian ibu. Makan gulai tempoyak seperti mendengarkan orkestra rasa, di mana setiap nada punya tempo dan harmoni. Benar-benar rasa yang mengoyak selera tuk segera melahapnya.
Dari Rimba ke Meja Makan
Asal-usul tempoyak tak pernah dicatat dalam buku sejarah resmi. Tapi para tetua dusun percaya, ia lahir dari keterpaksaan. Ketika musim durian tiba dan buah terlalu banyak untuk dikonsumsi sekaligus, masyarakat mencari cara untuk menyimpannya. Fermentasi menjadi jalan keluar. Siapa sangka, upaya menyelamatkan durian dari pembusukan justru melahirkan rasa baru yang melintasi generasi.
Di pedalaman Sumatra Selatan dan Bengkulu, tempoyak bahkan menjadi bagian dari identitas kuliner. Di desa-desa kecil, tempoyak disajikan dengan ikan sungai bakar, sambal tempoyak mentah dengan lalapan, atau campuran dalam pepes ikan, bahkan sekadar nasi panas dengan sedikit tempoyak dan irisan cabai rawit.
Namun jejak tempoyak tak berhenti di Palembang. Di Jambi, tempoyak mentah diaduk dengan ikan salai dan dibiarkan semalam sebelum dimasak. Di Lampung, lain lagi sambal tempoyak lebih pedas dan segar, sering menjadi teman makan singkong rebus atau ikan panggang.
Makanan ini tak pernah dibuat dengan terburu-buru. Ia lahir dari kesabaran. Dari waktu, dari kebersamaan. Tak ada satu pun cara tunggal untuk menikmati tempoyak. Justru di sanalah letak keindahannya: ia lentur, tapi tidak pernah kehilangan watak.
Aroma yang Membelah Dunia
Bau tempoyak itu mengingatkanku pada almarhumah ibu. Tiap kali hidung mencium aroma masakan tempoyak. Tak terasa air mata menetes. Tetesannya bahkan makin deras hingga membasahi kedua belah pipi. Aku teringat ibu. Dalam tangis, mulut spontan mengucap kalimat-kalimat dalam Surah Al-Fatihah, menitipkannya lewat angin berharap sampai ke liang lahat, tempat ibu kini berbaring. Aroma masakan tempoyak bagiku seperti aroma pulang.
Tempoyak memang bisa memecah belah ruangan. Tapi bagi mereka yang tumbuh dengannya, aroma itu bukan gangguan. Ia adalah sinyal cinta, jalan rindu atau simbol tradisi. Pengingat akan sesuatu yang lebih besar dari sekadar rasa.
Di tengah gempuran makanan cepat saji dan fusion cuisine, tempoyak tetap berdiri kokoh. Ia tak bisa dijinakkan oleh tren. Tak bisa dikemas dalam bentuk instan. Karena tempoyak bukan sekadar makanan, ia adalah kenangan yang bisa dirasakan di lidah.
Jejak Tempoyak di Sumatra
Di sepanjang Pulau Sumatra, tiap daerah punya caranya sendiri menyanyikan lagu tempoyak. Orang Palembang, hidangan gulai patin tempoyak sering hadir di acara keluarga, hajatan, atau menyambut tamu penting. Dimasak dalam belanga besar, baunya menyeruak ke seluruh rumah. Tempoyak di sini biasanya lebih pekat, tua, dan kaya rasa.
Dalam satu suapan gulai tempoyak patin, semua rasa bertumpuk: masam yang menggigit, gurih yang memeluk, pedas yang mengejutkan, dan aroma durian yang tiba-tiba jadi masuk akal. Ini bukan makanan yang jinak. Ini makanan yang punya identitas, yang tidak mencoba menyenangkan semua orang.
Di Bengkulu, tempoyak menjadi isi dalam pepes ikan nila atau lele. Dibungkus daun pisang dan dibakar perlahan, aromanya menjelma lebih halus, menyatu dengan asap dan daun yang terbakar pelan.
Di Jambi, tempoyak tak hanya digunakan sebagai masakan. Ia dijadikan sambal mentah, dicampur dengan ikan teri atau udang, lalu disantap dengan nasi dan lalapan. Segar dan menggigit.
Di Lampung, sambal tempoyak lebih cair dan pedas. Di beberapa kampung, ia disajikan dengan pindang atau dijadikan bumbu celupan untuk gorengan. Sensasi pedas-asam yang unik menjadikannya favorit banyak orang.
Di Minangkabau, meski jarang disebutkan, beberapa daerah di pesisir selatan memasukkan tempoyak dalam bumbu rendang ikan atau sambal lado mudo. Menciptakan dimensi rasa baru yang jarang dijumpai di dataran tinggi.
Mungkin tempoyak adalah cara orang Sumatra menulis sejarahnya sendiri di piring makan. Ia lahir dari berlebihnya durian, dari keterbatasan lemari pendingin, dari kecerdikan untuk menyimpan dan merawat. Tapi lebih dari itu, ia adalah bukti bahwa yang berbau kuat, yang berasa tajam, yang mengoyak, bisa bertahan bahkan dicintai.
Tempoyak di Era Modern
Di banyak dapur modern, tempoyak mungkin hanya muncul sebagai bumbu alternatif, sekilas lewat, atau malah tak dikenal sama sekali. Tapi di kampung-kampung, di warung pinggir jalan, dan di hati orang-orang yang pernah mengecapnya di masa kecil, tempoyak tetap hadir sebagai rasa yang tak tergantikan.
Kini, tempoyak mulai menemukan panggungnya di dunia kuliner modern. Beberapa chef nusantara mencoba mengolahnya menjadi mousse tempoyak, pasta tempoyak, hingga risotto tempoyak. Ada yang berhasil, ada pula yang gagal total. Karena tempoyak, pada hakikatnya bukan bahan yang bisa ditundukkan begitu saja. Ia harus dihormati.
Restoran-restoran fine dining yang mengusung tema nusantara perlahan mulai melirik tempoyak sebagai bahan otentik. Di Jakarta, Bandung, hingga Bali, muncul menu “gulai tempoyak modern”, yang mencoba menyandingkan rasa kuno dengan tampilan kontemporer. Tapi tetap saja, banyak yang setuju: tempoyak terbaik tetap ditemukan di dapur ibu-ibu di Sumatra.
Menjaga yang Asam
Di tengah upaya global melestarikan pangan lokal, tempoyak adalah salah satu contoh bagaimana rasa bisa menjadi identitas. Ia tak sekadar makanan, tapi bagian dari sistem pengetahuan tradisional: tentang musim, fermentasi, penyimpanan, hingga budaya makan bersama.
Petani durian kini mulai diajarkan kembali cara membuat tempoyak secara higienis. Komunitas kuliner mulai membagikan resep-resep tempoyak lintas generasi. Di festival-festival pangan lokal, tempoyak diberi ruang untuk tampil, tak lagi malu-malu di balik aroma yang menyengat.
Di sekolah-sekolah kuliner, sudah saatnya tempoyak diajarkan sebagai bagian dari warisan rasa. Karena siapa tahu, dari rasa yang mengoyak ini, kita bisa belajar tentang keberagaman, tentang penerimaan, dan tentang betapa kayanya negeri ini dalam satu sendok makan.
Rasa yang Tidak Bisa Diterjemahkan
Tak mudah menjelaskan tempoyak pada mereka yang belum pernah mencicipinya. Ia bukan sekadar asam, bukan hanya bau durian, dan bukan pula fermentasi biasa. Ia adalah gabungan antara tradisi, geografi, dan memori.
Sebagaimana kopi punya pahitnya sendiri dan wine punya waktu yang mengubah rasanya, tempoyak pun punya dinamika rasa yang menantang, mengejutkan, tapi pada akhirnya menenangkan. Ia merobek batas-batas rasa yang nyaman, mengajak kita menjelajah.
Ketika terakhir kali aku menyesap kuah gulai tempoyak di sebuah warung kecil menuju kota Bengkulu, aku tahu ini bukan makanan biasa. Ini adalah surat cinta dari tanah Sumatra. Dikirim lewat lidah, dibaca oleh hati.
Sebagaimana lagu lama yang hanya dimengerti oleh yang pernah patah hati, tempoyak adalah rasa yang dipahami mereka yang rela berteman dengan kenangan, dengan tanah, dan dengan lidah yang tumbuh bukan dari pelatihan koki, tapi dari panggilan akar.
Tempoyak seperti jalan rinduku untuk pulang ke kampung halaman Sumatra. Tempoyak, rasa yang mengoyak selera. Tapi dalam koyakannya, kita menemukan diri. ***
Dapatkan reward khusus dengan mendukung The Writers.
List Reward dapat dilihat di: https://trakteer.id/the-writers/showcase.

 Djoni Satria
Djoni Satria 








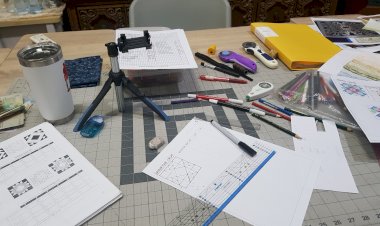




























![Setelah Bulan [Cerpenting]](https://cdn.pixabay.com/photo/2016/11/25/23/15/moon-1859616_1280.jpg)