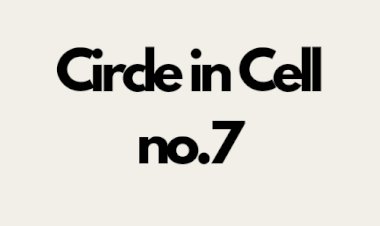Ngebir Bareng Ustaz Sebelum Sholat
Udara Bogor sangat dingin. Baru saja hujan begitu lebat. Waktu menunjukkan pukul 13.00. Dengan Kawasaki W175 Cafe, saya ngebut membelah jalan, menuju sebuah sekolah SD swasta di Jalan Pulo Armen. Ini adalah waktunya saya menjemput gadis kecil saya, yang masih duduk di kelas 3.
“De, kita ngebir dulu yuk, di Suryakencana? Dingin banget, nih.”
“Hayuk, Pah!” kata anak cantik saya, tanpa banyak tanya. Sepertinya anak saya sudah sangat memahami kebiasaan saya. Saya tekan starter motor, lalu beberapa detik kemudian, kami berdua pun sudah melaju kencang.
***
Siapakah yang pernah mempersatukan Ustaz dan Sang Pemabuk dalam satu ritual minum Bir? Adakah? Terasa aneh memang pertanyaan ini. Tapi, saya pernah! Begini ceritanya.
***
Tiga puluh tahun lalu, di masa kuliah dulu. Saya memiliki banyak sahabat di Kampus Depok, dengan berbagai karakter yang bahkan bertolak belakang. Ada yang kutu buku, kerjaannya baca melulu. Ada aktivis Rohis (Rohaniawan Islam), hobinya merekrut orang, khususnya para junior yang baru masuk kampus, untuk bergabung di pengajian rutinnya. Ada pemalas, yang nggak pernah masuk kelas, malah sukanya nongkrong di kantin kampus sambil main remi sampai bablas. Dan tak lupa ada satu lagi, ini yang unik, Sang Pemabuk, dengan tangan selalu menggenggam minuman beralkohol dari berbagai merek. Ada jenis vodka, whisky, brendi, atau yang paling ringan, bir! Banyak lagi perilaku dan hobi aneh teman-teman saya ini. Sepertinya, satu kepala memiliki satu kebiasaan dan ciri khas masing-masing yang berbeda. Nyebelinnya, semua tumplek menyukai tempat kos saya.
Inilah untungnya, atau malah repotnya ya, sebagai anak mahasiswa daerah super-ramah yang harus ngekos dan berkelana sendirian. Tempat kosnya berisiko dijadikan basecamp bagi teman-temannya dari berbagai angkatan, bahkan dari berbagai jurusan.
Sebagai tempat kecil yang ditongkrongi segerombol orang dengan watak berbeda, jelas, banyak hal terjadi. Kebersamaan, perdebatan, keisengan berlebihan, bahkan konflik fatal.
Sang Pemabuk, bernama Zen, adalah anak orang kaya asal Jambi, yang berambut ikal dan gondrong. Ia sangat slengean, seringkali bertingkah semaunya. Mungkin, 3/4 hidupnya dalam sehari diisi dengan efek alkohol yang bikin otaknya setengah sadar. Kuliah pun sering sambil beler. Tapi sesungguhnya, bagi saya, dan terhadap saya, hatinya sangat baik. Saya tahu, hanya keisengan yang berlebihannyalah yang kerap memicu perselisihan dengan teman-temannya.
Nah, teman yang paling tidak cocok dengan dia adalah Robi, aktivis Rohis garis keras yang memandang orang yang tidak sealiran dengannya sebagai orang kafir. Apalagi memandang Zen, bara api Robi selalu menyala-nyala, seakan menyambar alkohol yang senantiasa ada dalam genggaman Sang Pemabuk itu. Itu sebabnya, Robi dan Zen tak pernah datang bersamaan ke tempat saya.
Sampai, suatu ketika, datang hari naas Robi.
“Sep, ini air mineralnya Si Robi?” kata Zen, dengan suara seraknya, menunjuk sebotol air mineral di meja ruang tamu. “Ke mana sekarang dia? Tumben mau datang ke kosan lu pas ada gua,” lanjutnya.
“Itu lagi di toilet. Iya, katanya mau minjem buku Linguistik Komparatif, lagi ada tugas.”
Tiba-tiba, Zen mengeluarkan botol superkecil dari sakunya, seukuran tinggi 5 cm, lebar 1,5 cm. Isinya cairan bening. Saya nggak paham benda apa itu, yang jelas, itu pasti sejenis minuman beralkohol kadar tinggi. Dengan sigap, Zen memasukkan cairan itu ke botol air mineral Robi, sambil cekikikan.
Belum sempat saya mau mencegah Zen, tiba-tiba suara pintu toilet berbunyi, dan Robi keluar. “Panas banget ini cuaca, bikin haus aja,” katanya sambil menyambar botol air mineral tadi. Sebelum menenggaknya, matanya melirik sejenak ke arah Zen. Ujung bibir kanannya naik sedikit ke atas, pertanda ekspresi sinis kalau kita lihat di film-film India mah.
“Apa kabar lu? Tumben nongol,” katanya.
“Sehat, Ustaz! Alhamdulillah,” kata Zen sambil meraih tangan kiri Robi, lalu bergaya sungkem. Zen biasa memanggil Robi dengan sebutan Ustaz.
Glek.. glek.. glek… glek… Robi menenggak air mineralnya, seakan melenyapkan dendam kesumatnya pada rasa haus dan gerahnya cuaca. Atau entah mengekspresikan perasaannya pada Zen yang masih berposisi sungkem, seperti perasaan ingin melumat habis Mahluk tak Bermoral ini.
“Lha, kok tambah haus ya?” kata Robi.
Entah apa yang terjadi, satu setengah menit kemudian, Robi diam saja. Seperti merasakan sesuatu, tapi tak kuasa mengatakannya. Mata Robi tiba-tiba merah. Sejenak kemudian, ia menengokkan kepalanya ke arah Zen yang ada di sebelah kanan dia. Tapi tatapan matanya sayu. Sangat sayu. Zen kikuk ditatap terus menerus oleh Robi. Ia pindah posisi ke sebelah kiri Robi. Mata Robi mengikutinya. Tatapannya semakin sayu. Dan tiba-tiba dia bangkit sambil berteriak, “Zen…! Sampai mati pun lu nggak ane maafin ya! Baaajiiingan!!!!”
Robi ambruk duluan sebelum tinjunya berhasil menghajar Zen. Kekuatan alkohol di botol kecil Zen benar-benar dahsyat. Sekali lagi entah apa nama merek minuman ini. Atau mungkin sudah dicampur benda jahat lainnya.
Saya sendiri teringat, pernah menjajalnya, ketika Zen suatu saat menantang saya.
“Gak mungkin gua mempan hanya sama benda sekecil ini,” saya menyombong, maklum masih piyik. “Lu aja yang norak! Sok-sokan teler padahal biasa aja.”
Saat itu saya hendak mengambil wesel, kiriman uang bulanan dari ayah saya, di BRI Pasar Minggu.
“Coba kalo berani lo?” kata Zen.
Tanpa banyak cingcong, saya tenggak habis cairan di botol kecil itu. Saya cuma pengen jajal, karena saya pikir nggak bakal ngefek, sesendok juga kurang. Tapi aneh memang, cairan itu seperti tidak melewati kerongkongan saya. Cairan itu seperti minyak spirtus yang sudah langsung lenyap ketika baru sampai pangkal lidah saya.
“Halah, liat nih. Gua gak kenapa-kenapa, kan?” kata saya sambil meninggalkan Zen yang bengong. Dan memang, saya tidak merasakan apa-apa.
Beberapa menit kemudian, saya sudah berada di atas Metromini arah Pasar Minggu, ditemani Rendi, sahabat saya yang lain.
“Stop... stop... stop!” saya berteriak kencang, menghentikan laju bis, begitu saya melihat sebuah perempatan. Lalu kami berloncatan sebelum bis berhenti.
“Haduh Rendi, ternyata ini bukan perempatan Pasar Minggu! Salah berhenti gua!” Rendi bingung setengah dongkol. Lalu kami mencegat dan menaiki bis Kopaja, untuk melanjutkan perjalanan ke Pasar Minggu.
“Stop... stop... stop!” saya kembali menyeret Rendi lompat sebelum bis berhenti. Saya benar-benar merasa, saya sudah sampai di perempatan Pasar Minggu, arah di mana bank BRI berada. Dan ini terus terjadi beberapa kali.
Kepala saya tidak pusing, tapi sepertinya, orientasi saya hilang.
“Gila lu, Sep. Udah 6 kali lu seret-seret gua hanya untuk berhenti di tempat yang salah. Udah lah, kita balik aja! Besok lagi ambil uangnya!”
Rendi ngambek. Dan kami pun kembali ke kosan. Saya akhirnya memilih tidur pulas sampai pagi tiba.
Saya yakin, apa yang saya rasakan, terjadi pada Robi. Mungkin Robi tidak merasa pusing. Atau mungkin juga merasakannya, karena sepertinya efek benda haram ini berbeda-beda. Tapi yang jelas, Robi juga pasti merasakan sesuatu yang aneh, seperti kehilangan orientasi.
Sejak itu, Robi tak sudi bertegur sapa dengan Zen. Bagi Robi, Zen adalah sosok dajjal yang sebenar-benarnya. Ini terjadi sampai kami lulus. Bahkan sampai berpuluh tahun kemudian, saat mereka sudah mapan di dunia kerjanya masing-masing.
Saya sendiri tetap menjalin komunikasi dengan keduanya. Robi mendirikan Yayasan Pesantren Tahfiz khusus untuk orang-orang tidak mampu; sementara Zen bekerja di perusahaan minyak dan gas nasional.
Ketika Indonesia terbelah di masa pemilihan presiden tahun 2019 lalu, tentu tak ketinggalan, mereka berdua juga terlibat konflik. Mereka aktif di organisasi relawan alumni yang juga terbelah. Mereka saling hujat, saling maki, dengan mempertentangkan nasionalisme versus sentimen keagamaan. Bahkan nyaris saja mereka terlibat bentrok fisik.
Suatu kali saya mendengar kabar dari Zen, bahwa Robi sempat melontarkan ancaman, untuk mengirimkan laskar-laskarnya guna memberi dia pelajaran. Tentu ini tak membuat Zen gentar. Saya sangat kenal Zen, orang yang samasekali dididik keras oleh lingkungannya untuk tak pernah takut akan apapun.
Saya sendiri memilih untuk tidak memihak salah satu di antara mereka.
Setahun berselang setelah masa pemilihan presiden usai, saya dikejutkan oleh kabar dari Zen, bahwa Zen divonis terkena cancer hati stadium 4. Saya bagaikan tersambar petir, tak kuasa mendengar getar suaranya. Bagaimana pun, Zen adalah sahabat baik saya. Sahabat yang saya kenal gagah, bengal dan tangguh. Dari suaranya, saya membayangkan, ia sedang begitu tak berdaya.
“Sep, gua pengen ketemu Ustaz Robi. Sebelum gua meninggal, gua pengen banget minta maaf sama dia. Dan kalau ini bisa gua lakukan, gua rasanya lega. Tolong pertemukan gua ya, Sep.”
“Pasti, Zen! Gua jamin, gua pertemukan lu sama Robi.”
***
Tak sulit bagi saya untuk membujuk Robi mau bertemu dengan Zen. Walau awalnya menolak, Robi luluh ketika mendengar bahwa Zen saat ini menderita cancer dan sudah masuk stadium 4. Saya sangat percaya, walau tabiat, karakter, termasuk haluan politik mereka berdua berbeda, bagaimana pun, mereka punya ikatan kuat sebagai sahabat.
Saya sengaja pertemukan mereka di Bogor, Kota Hujan yang selalu menyajikan aura melankolis. Saya jemput Robi di stasiun Bogor, lalu saya jemput Zen yang konon sudah markir mobilnya di Botani Square. Rencananya, kami akan jalan dalam 1 mobil saja untuk nongkrong sambil makan siang bareng di sebuah Resto di Jalan Pajajaran.
Hujan tampak deras. Udara terasa amat dingin.
“Zen, ayo masuk!” teriak saya dari dalam mobil, begitu saya lihat sahabat saya ini sudah nunggu di Lobi Botani Square.
“Assalamu alaikum Ustaz, apa kabar?” sapa Zen, begitu duduk di jok belakang, sambil menyodorkan tangan kanannya ke arah Robi yang duduk di sebelah saya. Tangan kirinya memeluk bahu Robi.
“Waalaikum salam. Alhamdulillah ane sehat. Gimana kabar lu Zen?” Robi menyambut hangat, walau diawali sedikit grogi.
Mereka pun hanyut dalam haru. Mulut mereka tak banyak bicara, tapi saya yakin, hati mereka berceloteh dan bertegur sapa. Suasana pun hening, seakan Tuhan memberi ruang untuk mempersilakan perasaan-perasaan mereka, menembus masa lalu, ketika berbagai pengalaman pernah mereka lakukan bersama, baik yang menggembirakan maupun yang menyebalkan. Hujan baru saja berhenti, hanya menyisakan gerimis dan udara dingin, ditambah semburan AC yang malah semakin kontras menghadirkan hangatnya hati mereka.
“Woi, gua punya ide nih, lu pasti gak bisa nolak,” saya memecahkan suasana.
“Ide apa lo, Bro?” selak Zen dengan suaranya yang serak.
“Ini cuaca kan dingin banget. Gimana kalo kita ubah dulu rute kita. Sebelum makan siang, gua ajak lu ngebir bareng!”
“Gila lu, Sep!” Zen kaget.
“Astagfirullah aladzim!” Robi tercekat.
“Tenang, Robi. Sekarang kan pas pukul 11.15. Abis ngebir, ntar kita langsung solat berjamaah.”
“Ngaco lu, Sep. Emang ngapus dosa segampang itu? Nggak nggak nggak! Lu jangan malah membangkitkan luka lama ya!” teriak Robi.
Saya tidak perduli dengan protes mereka berdua. Saya banting setir mobil menuju Jalan Suryakencana. Lalu saya meminggirkan mobil tepat di dekat Gang Aud. Tanpa banyak bicara, saya menarik tangan mereka berdua, lalu mempersilakan mereka duduk di kursi plastik warna hijau, yang sudah tersedia di trotoar Suryakencana.
“Mang Ade! Bir tiga gelas!”
“Siap, Kang!” sahut seseorang yang saya panggil Mang Ade, di depan sebuah gerobak minuman, sigap.
“Gila lu ya, Sep! Gua datang ke sini buat minta maaf sama Ustaz Robi, bukan buat diajak minum bir! Maaf ya, Ustaz, ini bukan inisiatif gua.” Zen terlihat panik. Wajahnya mengarah ke saya dengan nada serius, lalu nengok ke Robi menunjukkan mimik cemas sekaligus memelas.
“Lu nggak salah, Zen. Ini si Asep yang ngaco!” selak Robi.
“Ini birnya, Kang. Selamat menikmati,” tiba-tiba Mang Ade datang dengan membawa nampan berisi 3 gelas besar bir. Satu disodorkan ke saya. Satu ke Zen, dan yang terakhir buat Robi.
Tampak, tangan Robi gemetar memegang kuping gelas bir. Wajahnya tegang, matanya terbelalak. Mulutnya ternganga.
Birnya terlihat jernih berwarna keemasan. Gelembung-gelembung sodanya bergerak ke atas, tampak begitu segar. Di bagian atasnya, lapisan buih tebal nyaris tumpah melewati sisi mulut gelas. Wow sangat indah.
“Ayo minum! Cheer!” kata saya sambil mangasongkan gelas, mengajak toast.
“Gila lu, Sep!”
“Ustaz Robi, Zen, tenang. Ini memang bir. Tapi namanya Bir Kotjok asli Bogor! Lu pade bebas minum sepuasnya karena ini satu-satunya bir yang halal. Sehat lagi!” terang saya panjang lebar.
“Mang Ade, beneran ini halal?” Robi ragu, sambil mengarahkan pandangan ke Mang Ade, si penjual Bir Kotjok ini.
“Betul, Pak. Ini bukan minuman beralkohol. Bir Kotjok ini terbuat dari jahe, kayu manis, gula aren, dan sedikit soda. Makanya rasanya seger dan hangat, Pak,” jelas Mang Ade.
Bir Kotjok adalah minuman legendaris khas Bogor. Bir Kotjok diracik oleh orang bernama Si Abah, sejak tahun 1965. Bahan-bahan serta cara meraciknya mirip sekali dengan Bir Pletok, minuman sejenis khas Betawi. Bir Kotjok ataupun Bir Pletok memang sengaja dibikin, bahkan sejak jaman Hindia Belanda, terinsprasi dari kebiasaan pesta para pejabat eropa yang selalu menghadirkan bir dalam keriangannya. Orang Betawi lalu bereksperimen untuk meracik minuman mirip bir tapi halal, tanpa alkohol. Maka terciptalah Bir Pletok, yang di Bogor kemudian bernama Bir Kotjok. Warna minuman ini keemasan, bergelembung, dan berbuih. Mirip bir, tapi lagi-lagi, tanpa alkohol dan halal.
“Cheer!” teriak saya sambil menyodorkan gelas.
Cring! Cring! Cring! Tiga gelas Bir Kotjok beradu. Lalu tanpa ragu, Ustaz Robi menenggaknya dengan semangat. “Bismillah…” ucapnya.
Saat saya dan Zen hanya menenggak 3 teguk, Robi menghabiskannya sekaligus segelas penuh. Begitu ia selesai menenggaknya, dia kaget sendiri.
“Lha, lo nggak habis Zen? Katanya lu peminum sejati?”
Zen bengong, menengok ke saya, lalu beralih ke Robi. Tawa kami pun pecah mengundang lirikan mata setiap orang yang lewat.
“Mang Ade! Satu gelas lagiiiiiiii!” teriak Robi dan Zen hampir bersamaan.
Tawa kami memantul di antara buih-buih bir. Melumatkan semua perasaan gondok dan benci yang barangkali pernah hinggap menyentuh hati kami. Anehnya, mungkin karena kami asyik ngebir bareng, kami jadi lupa dengan isu utama kami. Tak satupun kata minta maaf atau memaafkan meluncur dari mulut kami. Sepertinya, bekunya rasa marah sudah luntur digerus soda-soda bir. Dinginnya kebencian sudah dinetralisir hangatnya jahe dalam bir. Pahitnya dendam sudah dilebur aroma kayu manis dan gula aren pada bir. Bir Kotjok ini bukan sekadar obat dari rasa dahaga, tapi juga dari keroposnya jiwa.
“Allahu akbar Allaaaahu akbar…,” dari jauh, terdengar lantunan azan, tanda Zuhur tiba.
“Yuk, saatnya solat,” Zen berdiri.
“Alhamdulillah. Ini pengalaman seumur hidup ane nih. Bayangin, habis diajak ngebir bareng, lanjut solat bareng… Aura Zen sebagai peminum emang kuat, huahaha...”
Kami tertawa bareng. Tepatnya ngakak bareng.
Namun beberapa menit kemudian, kami sudah hanyut dalam hening. Robi di depan. Saya dan Zen di shaf belakang. Suasana Masjid Raya Bogor yang kami pilih, begitu syahdu dan tenang.
***
“Pah, Papa kenapa sih, sering banget ngajak aku ke sini?” tiba-tiba suara jernih putri saya membuyarkan lamunan. Tangannya memegang kuping gelas besar berisi air berwarna keemasan. Di dalam air terlihat gelembung-gelembung soda bergerak ke atas. Gelembung itu bermuara pada buih putih yang nyaris tumpah di mulut gelas. Leleran buihnya mengalir ke bawah, menyentuh barisan huruf yang melingkar bertuliskan “Minuman Top Since 1965. Bir Kotjok Bogor”.
“Suka aja, De. Apalagi kalau cuaca sedang dingin seperti ini. Seger tapi hangat rasanya,” sahut saya, sambil menenggak bir yang juga ada di tangan saya.
Sesungguhnya, saya ke sini untuk mengobati sebuncah rindu. Pikiran saya melayang pada sahabat saya Ustaz Robi, yang saat ini mungkin sedang sibuk bersama santri-santri Tahfiznya. Pikiran saya menerawang mengunjungi sahabat saya Zen, yang saat ini sudah istirahat damai di sisi Sang Pencipta.
***
Kota Hujan, 26 Juni 2025
Dapatkan reward khusus dengan mendukung The Writers.
List Reward dapat dilihat di: https://trakteer.id/the-writers/showcase.