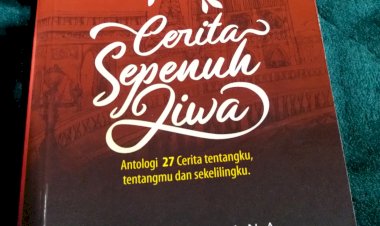[Cerbung] Perawan Sunti dari Bawono Kinayung #10
![[Cerbung] Perawan Sunti dari Bawono Kinayung #10](https://thewriters.id/uploads/images/image_750x_5e6db0a8abec0.jpg)
Sepuluh
Di Bawah Hangatnya
Cahaya Mentari
Sebesar apa pun rasa kehilangan itu, kehidupan yang masih tersisa haruslah tetap berjalan. Lagipula masih tersisa harapan bahwa Kresna akan kembali. Walaupun entah kapan. Sekilas Seta menatap Mahesa di seberang meja. Seorang ayah yang tegar dan kuat. Yang terkadang justru melemparnya kembali pada sepotong penyesalan.
Seandainya aku dulu semanis Kresna....
Dihelanya napas panjang. Mahesa mengangkat wajahnya. Ditatapnya Seta.
“Kenapa?” tanyanya halus.
Seta menggeleng. Kembali menekuni sarapannya.
“Kangen pada Kresna?”
Seketika Seta mengangkat wajahnya kembali. Pada satu titik waktu yang sama, tatapan mereka saling mengunci. Dan, keduanya sama-sama menemukan letupan kerinduan yang serupa. Seta mengerjapkan mata. Kembali menunduk.
“Ya,” gumamnya, “dan Ibu.”
Didengarnya sang ayah menghela napas panjang.
“Entahlah, dua malam berturut-turut ini aku memimpikan Ibu,” lanjut Seta, dengan suara nyaris tak terdengar.
Mahesa terdiam. Ia juga sering bermimpi tentang Wilujeng. Mimpi yang selalu sama selama bertahun-tahun, tapi tak pernah membuatnya bosan. Karena dalam mimpi itulah senyum dan sosok Wilujeng seutuhnya hadir untuk membantunya tetap bernapas. Demi Seta. Demi Kresna. Mimpi yang membuatnya bertekad untuk tak akan pernah menggantikan sosok Wilujeng dengan siapa pun dalam kehidupannya.
Mentari pagi mengintip malu-malu dari balik segumpal awan. Menghangatkan suasana di sekitar meja putih bundar di tengah taman belakang itu. Acara makan pagi mereka hampir berakhir. Hampir tiba waktunya bagi mereka berdua untuk berangkat ke kantor. Tepat saat itu, ponsel di saku kemeja Mahesa berbunyi. Laki-laki itu segera menjawab panggilan itu.
“Halo, selamat pagi,” sapanya dengan nada ramah walaupun nomor itu tak dikenalnya.
“Selamat pagi. Dengan Bapak Mahesa Prabangkara?”
“Iya, betul. Saya sendiri. Maaf, dengan Ibu siapa ini?”
“Saya Megasari dari Polsek Sumpiang, Pak. Ada yang ingin bicara dengan Bapak.”
Hening sejenak di seberang sana. Mahesa mengerutkan kening. Lalu....
“Yah....”
Mahesa tersentak mendengar suara lirih dan bergetar itu. Kresna???
“Kres?” hanya itu yang ia mampu bisikkan.
Mendengar Mahesa menggumamkan satu suku nama itu, Seta seketika terbelalak. Ditatapnya Mahesa tanpa berkedip.
“Iya, Yah.... Ini aku....”
“Ya, Tuhan.... Kresna.... Kresna!” Mahesa menatap Seta.
Pemuda itu segera meloncat ke dekat ayahnya. Tanpa permisi direbutnya ponsel dari tangan Mahesa. Mahesa pun meraih dan merengkuh bahu Seta.
“Kres! Lo di mana? Gue jemput sekarang!” seru Seta dengan kegembiraan meluap.
Tapi Mahesa segera mengambil alih ponsel itu dari tangan Seta.
“Kres, Seta dan Ayah jemput kamu sekarang. Kamu masih di Sumpiang?”
“Lagi jalan ke Palaguna, Yah. Jemput di Polsek Palaguna Kota saja.”
“Ya! Ya! Ayah ke sana sekarang.”
“Yah, ini Bu Polisi mau bicara lagi sama Ayah.”
“Ya! Ya!”
Hening sesaat.
“Pak Mahesa, kami dari Polsek Sumpiang beberapa jam lalu mendapat kabar dari Polsek Sembilangan bahwa putra Bapak bernama Mahakresna Prabangkara telah ditemukan dalam kondisi baik dan sehat di wilayah Polsek Sembilangan di wilayah kerja Kepolisian Kota Saruji. Putra Bapak sudah diantarkan ke kantor kami. Kami pun sudah berkoordinasi dengan Polsek Palaguna Kota. Dan sekarang kami dalam perjalanan ke Polsek Palaguna Kota. Bapak bisa menunggu di sana.”
Berkali-kali Mahesa mengucapkan terima kasih. Ketika pembicaraan itu berakhir, yang bisa dilakukannya adalah memeluk Seta erat-erat sambil tak henti-hentinya bersyukur pada Tuhan.
“Yah, boleh aku kabari geng?” ucap Seta ketika mereka beriringan melangkah ke garasi.
“Ya, kabarilah,” angguk Mahesa dengan antusias. “Kalau ada yang mau ikut jemput, suruh saja langsung ke Polsek Palaguna Kota.”
Seta tersenyum lebar sambil mulai sibuk dengan ponselnya.
* * *
“Aku mau ke ‘atas’ dengan Randu, Jeng,” ucap Paitun begitu mereka selesai sarapan. “Kamu titip apa?”
Wilujeng menatap Pinasti sebelum menjawab pertanyaan Paitun.
“Kamu butuh buku baru lagi, Nduk?” senyumnya.
Pinasti menggeleng. “Yang dibawakan Bibi Kriswo beberapa hari lalu belum semuanya selesai kubaca, Bu.”
Wilujeng mengalihkan tatapannya pada Paitun. “Nggak usah, Mak. Kebutuhan kami masih cukup.”
“Tak perlu masak hari ini. Nanti biar kusuruh Tirto ambil ikan dan buatkan kalian ikan bakar.”
“Baik, Mak,” Wilujeng mengangguk patuh. “Kalau begitu aku akan ajak Pinasti ke padang bunga atau padang rumput.”
Paitun mengangguk sambil tersenyum.
Sepeninggal Paitun, Wilujeng segera mengisi keranjang rotan dengan ubi panggang dan pisang kukus yang pagi-pagi tadi sudah ia siapkan. Pinasti pun mengambil beberapa buku yang belum dibacanya. Dimasukkannya pula buku-buku itu ke keranjang rotan.
“Mau ke padang rumput atau padang bunga, Pin?” tanya Wilujeng sembari menutup pintu pondok.
“Ke padang rumput saja, ya, Bu?”
Wilujeng pun mengangguk. Keduanya tak lupa mampir ke pondok Tirto untuk sekadar berpamitan.
“Nanti kuantarkan makan siang ke sana, Mbak,” ucap laki-laki tinggi besar itu.
Wilujeng mengucapkan terima kasih, kemudian berlalu bersama Pinasti.
* * *
Embun belum sepenuhnya menguap dari tepi rerumputan. Kerlip pantulan cahaya hangat mentari menyambut keduanya di sana. Segera saja Pinasti menjatuhkan diri di tempat kesukaannya di bawah naungan pohon. Ditatapnya kejauhan. Jalur di atas tebing-tebing Pegunungan Pedut mulai sibuk. Dunia ‘atas’ yang dikenalnya dari jauh.
Tiba-tiba saja, selintas pikiran menyeruak di dalam benaknya. Ditatapnya Wilujeng yang tengah mengeluarkan bekal mereka dari dalam keranjang.
“Bu, benarkah dunia ‘atas’ tidak seindah di sini?” celetuknya.
Seketika Wilujeng menoleh. Menatapnya dengan mata bulat yang berbinar indah. Perempuan itu tertawa ringan.
“Hah? Kata siapa?”
Sejenak Pinasti tercenung. Dikerutkannya kening. Rasa-rasanya ia pernah mendengar hal itu, tapi tak ingat siapa yang mengatakannya. Ia menggeleng.
“Aku lupa.” Perawan sunti itu meringis lucu.
Wilujeng tersenyum lebar sambil menggelengkan kepala. Ia kemudian duduk di sebelah Pinasti. Disorongkannya keranjang rotan pada Pinasti supaya gadis itu mudah memilih bahan bacaannya.
“Setiap dunia punya keindahannya sendiri-sendiri, Pin,” ucap Wilujeng, sembari mengupas sebuah pisang kukus. “Di ‘atas’ mungkin benar tak sedamai dan setenang Bawono Kinayung dan bawono lainnya, tapi tetap memiliki keindahannya sendiri.”
“Bu, apakah kita akan kembali ke ‘atas’ bersama-sama nantinya?”
Wilujeng tercenung sejenak. Lalu menggeleng seraya menghela napas panjang.
“Sepertinya tidak. Tapi semoga kita sama-sama baik-baik saja, Nduk. Ibu harap begitu.”
Pinasti tertunduk. Entah kenapa mendadak hatinya terasa sedih saat ini. Tadi saat ia bangun, ia merasa seperti ada bagian yang kosong dalam dirinya. Dalam hatinya. Entah apa. Ia sama sekali tak tahu. Dihelanya napas panjang. Ia mengangkat wajah dan menatap sekitarnya.
Padang rumput itu terlalu indah untuk diabaikan. Kemudian ia dan Wilujeng menikmati keindahan itu sembari bertukar cerita. Sesekali keduanya melanjutkan membaca buku-buku yang mereka bawa. Kemudian saling bercakap lagi. Begitu seterusnya. Sembari merasakan kehangatan cahaya mentari yang menyapa.
* * *
Mahesa sudah tak mampu lagi berkata-kata untuk menumpahkan rasa syukurnya. Ia hanya bisa memeluk erat anak laki-lakinya yang sempat beberapa hari tak diketahui nasibnya. Tak malu lagi orang-orang di sekitar melihat air matanya meleleh membasahi pipi. Demikian juga Seta. Baginya, Kresna bukan hanya sekadar saudara kembar, tapi juga sahabat dan penopangnya. Bahkan memiliki juga setengah jiwanya.
“Sumpah! Lo jangan pernah lagi tinggalin gue kayak kemarin!” bisik Seta, penuh tekanan.
Kresna hanya mengangguk-angguk dengan wajah terlihat masih sedikit linglung. Seta mengguncang sedikit bahu Kresna. Kemudian memeluknya lagi.
“Janji, jangan pernah tinggalin Ayah sama gue!” bisik Seta lagi.
Kresna kembali mengangguk. Pelan-pelan, suasana riang tapi penuh haru itu menularinya juga. Apalagi ketika para sahabatnya yang lain, minus Alex dan Rizal, memeluknya bergantian. Tapi sejenak Kresna tercenung.
Alex....
Ditatapnya Seta.
“Rizal sudah berangkat ke Sanggura?” tanyanya.
Seta mengangguk.
“Alex?”
Seketika suasana menghening.
* * *
Kresna termangu di depan jendela viewing gallery[1]. Alex terbaring di dalam sana. Koma. Ditemani berbagai selang dan alat yang Kresna tak paham apa saja fungsinya. Gadis itu terluka berat dengan luka bakar mencapai 70%. Kresna menghela napas panjang.
“Kalau Alex pulih, dia harus siap untuk dituntut,” bisik Seta, “karena ada korban lain juga.”
Kresna menggeleng sambil mengerutkan kening. Ada korban lain?
Seta seolah mengerti apa yang ada dalam pikiran saudara kembarnya. Diremasnya bahu Kresna pelan.
“Alex nabrak warung iga bakar di Samenik, di kaki Bukit Seribu Kembang Goyang. Dia lari ke vila keluarganya di bukit itu. Ayah, aku, dan teman-teman sempat mencarinya sampai ke Gondang, tapi dia sudah keburu kabur. Besoknya, kami dapat kabar Alex kecelakaan. Mobilnya nabrak warung dan kebakar. Ada empat orang yang ikut jadi korban. Satu keluarga yang lagi makan di dalam. Salah seorang anaknya nggak selamat, satu lagi masih koma, ayah-ibunya luka nggak terlalu parah. Saksi bilang Alex ngebut waktu masuk ke Samenik. Lalu mobilnya oleng gitu saja ke kiri. Nabrak warung, meledak, dan terbakar.”
Kresna makin kehabisan kata. Tapi sejenak kemudian ia seolah tersadar. Ia menoleh. Menatap Seta.
“Memangnya aku hilang berapa hari, Set?”
Seta menghitung sejenak. Ia balas menatap Kresna.
“Sembilan hari,” jawabnya.
Kresna menggeleng pelan. Masih tak habis mengerti bagaimana perjalanannya keluar dari jurang di sisi selatan Gunung Nawonggo, hingga ditemukan di sisi timur gunung yang sama. Yang diingatnya hanya peristiwa melayangnya ia ke dalam jurang, serasa masuk ke lorong gelap, kemudian terbangun saat ditemukan seorang pencari bahan obat bernama Saijan. Itu pula yang diungkapkannya pada para polisi yang memeriksanya. Jawaban yang dinilai sangat jujur karena memang ada hal-hal di luar nalar yang telah terjadi pada Kresna, tanpa pemuda itu menyadarinya.
Kresna menghela napas panjang. Mengerjapkan mata.
“Apakah Ayah akan menuntutnya, Set?”
Seta menggeleng. “Entahlah. Tapi seandainya kita tidak menuntut pun, kepolisian akan meneruskan kasusnya. Kasus percobaan pembunuhan bisa tetap diteruskan walaupun tidak ada aduan dari keluarga korban. Lagipula, memang sampai ada korban jiwa dalam rangkaian kasus ini.”
Kresna mengembuskan napas keras-keras. Ia kemudian mundur dari depan jendela. Duduk di kursi tunggu di depan seberang ruangan. Seta mengikutinya.
Ada lagi yang membuatnya tak habis pikir. Kenapa Alex tega melakukan itu padanya? Apa salahnya pada Alex? Dan, masih banyak lagi pertanyaan lain. Membuatnya pening. Lagi-lagi Seta memahami hal itu.
“Kres, kita pulang,” ucapnya sembari menepuk bahu Kresna. “Kamu butuh istirahat. Ayah sebetulnya ada meeting di kantor pagi ini, tapi ditunda. Kamu lebih penting.”
Kresna tak punya pilihan lain. Ia pun mengangguk dan berdiri. Keduanya keluar beriringan dari ruangan itu.
* * *
Lagi-lagi, ia merasa terapung dalam ruang kosong dan gelap yang serasa tak berujung dan sama sekali tanpa cahaya. Berkali-kali ia meneriakkan pertanyaan yang melingkar-lingkar dalam kepala.
Apa yang sudah terjadi?
Tapi tak satu huruf pun jawaban bisa diraihnya dari dalam kelam di sekitar. Lalu, ia mencoba mengingat-ingat. Sedikit demi sedikit. Secuil demi secuil. Mencoba merangkainya dengan segala kemampuan yang ia punya.
Sore itu, mereka berempat bermaksud merayakan ulang tahun ke-50 sang ayah. Setelah melalui perdebatan panjang beberapa hari sebelumnya, mereka akhirnya sepakat untuk naik ke Samenik. Ada warung iga bakar yang lezatnya sudah tersohor di sana.
Di bawah langit menjelang senja, mereka pun memulai perjalanan dari tengah kota Margiageng menuju ke Samenik. Taruno, sang ayah, bersenandung sambil mengemudikan mobil mungil mereka. Misty, sang ibu yang cantik, menimpalinya dengan nyanyian melalui suaranya yang indah. Di jok belakang, ia dan kakaknya menikmati semua itu dengan riang gembira.
Satu setengah jam kemudian, mereka berempat sudah sampai di Samenik. Warung iga bakar bakar yang mereka tuju masih menyisakan meja untuk berempat di sudut depan warung.
Celoteh mereka memenuhi sudut itu, ditimpali pula dengan aneka canda dan tawa. Kegembiraan itu makin lengkap ketika pesanan mereka datang. Empat porsi iga bakar super istimewa dilengkapi dengan lalapan dan sambal yang sungguh menggoda, ditambah dengan lauk lain yang tak kalah enaknya.
Setelah itu mereka berempat bergandengan tangan di sekeliling meja. Dengan suara lembutnya Misty memanjatkan doa syukur dan harapan. Tapi, ketika mereka akan mengakhiri doa itu, sebuah hantaman yang begitu keras dan menyakitkan melanda tubuhnya. Masih bisa didengarnya jeritan kakaknya sebelum kegelapan menyelimutinya dengan begitu sempurna.
Ia sedikit tersentak.
Mana Kakak? Mana Ayah? Mana Ibu? Hei! Di mana kalian semua?
“Alma.... Alma....”
Pada saat itu, samar-samar ia mendengar ada yang memanggilnya. Lebih terasa seperti gema. Tapi sekeras apa pun ia mencari sumber suara itu, kegelapan tetap menyelimutinya. Begitu juga ketika ia mencoba menjawab. Yang ada hanyalah hening.
Dan, kegelapan serta keheningan itu kembali menenggelamkannya.
* * *
Sebelum menyapa Ki Selo Giri agar batu besar itu membuka jalan, tiba-tiba saja Paitun menghentikan langkahnya. Perempuan itu mengerutkan keningnya sejenak. Randu ikut berhenti dan menatap Paitun.
“Ada apa, Mak?” tanyanya halus.
Tapi Paitun menggeleng. Mengisyaratkan agar Randu diam. Laki-laki itu pun hening di tempatnya berdiri.
“Hm...,” gumam Paitun beberapa saat kemudian. “Aku harus kembali ke Bawono Kinayung, Ndu. Kamu saja ke ‘atas’ sendirian. Jangan lupa, catat semua pesanan Saijan. Kalau sampai menjelang senja kamu belum datang, akan kukirim Janggo untuk menjemputmu.”
“Baik, Mak.” Randu mengangguk patuh.
Laki-laki itu kemudian meneruskan perjalanannya, sedangkan Paitun berbalik dan kembali ke Bawono Kinayung. Saat ia sudah berada di dekat pondok, dilihatnya Tirto sedang melangkah menjauhi pondok.
“To!” serunya. “Mau ke mana?”
Laki-laki itu berhenti dan berbalik. Diangkatnya keranjang rotan yang ditentengnya.
“Mau kirim makan siang untuk Mbak Jeng dan Pinasti, Mak,” jawab Tirto.
“Sudah!” Paitun mengibaskan tangannya. “Sini! Biar aku panggil saja mereka.”
Tirto pun mengangguk patuh, dan mengikuti langkah Paitun masuk ke area pondok perempuan itu.
“Emak tak jadi ke ‘atas’?” tanya Tirto.
Paitun menggeleng. “Ada yang lebih penting, To. Menyangkut Wilujeng dan Pinasti.” Paitun membuka pintu pondoknya. “Randu kusuruh meneruskan perjalanan sendirian. Kalau dia terlambat pulang, suruh Janggo menjemputnya nanti.”
“Baik, Mak.” Tirto kembali mengangguk. “Tapi, ngomong-ngomong, Mbak Jeng dan Pinasti kenapa, Mak?”
Paitun tak segera menjawab pertanyaan itu. Ia mengheningkan diri sejenak. Menyelaraskan gelombang pikirannya dengan pikiran Wilujeng atau Pinasti. Kali ini yang selaras lebih dulu adalah gelombang pikiran Wilujeng.
‘Jeng, sekarang juga bawa Pinasti pulang. Kutunggu di pondok.’
‘Lho, Emak tak jadi ke ‘atas?’
‘Tidak, Jeng. Nanti saja kujelaskan. Sekarang berkemaslah. Pulang.’
‘Baik, Mak.’
Setelah pembicaraannya dengan Wilujeng selesai, Paitun menatap Tirto.
“Ada perintah baru dari Gusti. Wilujeng dan Pinasti harus secepatnya kembali ke atas. Bersamaan. Kita harus menyiapkan mereka dalam waktu dua hari ini.”
“Oh....” Tirto manggut-manggut.
Keduanya kemudian berbincang sambil menunggu Wilujeng dan Pinasti datang.
* * *
(Bersambung hari Sabtu)
Ilustrasi : www.pixabay.com (dengan modifikasi)
Catatan:
[1] Viewing gallery = ruangan untuk menengok pasien yang dirawat di ruang ICU. Pasien dapat dilihat melalui jendela kaca.
Dapatkan reward khusus dengan mendukung The Writers.
List Reward dapat dilihat di: https://trakteer.id/the-writers/showcase.