La dan Sebutir Nasi
“Dalam waktu pagi, kita akan saling menyapa, Pak.”
Seperti biasa, setiap pagi menjelang, begitu datang, kau langsung memarkirkan sepeda tuamu di bawah pohon mangga. Capingmu kau kenakan, cangkul dan bekal pun kau bawa. Kedua kaki telanjangmu kau turunkan, bersatu dengan tanah dan air. Yang La lihat, cangkulmu kau angkat dan memulai membajak. La menghela napas. Otot-ototmu terlihat kencang bersama keringat yang mengucur riyuh di tubuhmu. Matahari memang masih malu untuk menampakkan seluruh wajahnya. Namun, napas gugup yang tak pernah berhenti. Rasa lelah yang dihadapi, kau lewati demi bisa menafkahi istri dan sang buah hati.
La, gadis yang telah jatuh cinta pada negeri ini. Karena keelokkan budaya dan keindahan alamnya. Pemandangan sawah selalu memberikan kesejukan bagi setiap orang yang melihatnya. La tak pernah mengerti, mengapa sebagian orang memilih bangun di waktu siang. Melihat jarum jam, kemudian tidur kembali tanpa mengingat apa yang harus dikerjakan di waktu pagi. Walaupun hanya sekadar mengucapkan hamdalah atau doa bangun tidur bahkan kata ‘ah’ saja tidak. Menghiraukan bunyi alarm, ayam berkokok, gema azan, suara lembut Bunda, lipatan seprai yang kusut, dan bantal yang sudah tak beraturan lagi.
Cukup lama. La berdiri. Melamun ketika menyaksikan Pak Petani membajak sawahnya. Dan ketika itu pula, denting abjad mengalun dan terdengar di telinganya.
“Neng, kenapa?”
Pak Petani naik ke permukaan tanah yang lebih tinggi. Berjalan menghampiri La, persis di pinggir jalan. Kedua kakinya penuh tanah dan lumpur, keringat, dan napas yang masih terengah-engah. Melepaskan capingnya. Mengibaskan ke bagian wajahnya. Rasa gerah telah menyelimuti dan bersatu dengan kain di dadanya yang terlihat agak basah.
Kami duduk di bawah pohon pisang. Rumput, tanah, suara air mengalir, dan burung-burung yang hilir mudik terbang kesana-kemari. Menemani La dan Pak Petani pagi itu. Berbincang mengenai diri, fenomena yang terjadi di negeri ini. Tentang tikus berdasi, psikopat, dan perihal lainnya.
“Kumiliki sawah berabad silam, air dari gunung curam, cangkul bermata tajam, bajak siap menghujam, benih siap ditanam, dan butir padi siap diketam.” Dia berbisik pelan kepada La. Aku ini milik siapa?
***
Lantunan suara merdu di atas rumah Allah yang menggema membangunkan La dari lelapnya tidur. La memutuskan untuk segera melangkahkan kedua kaki mungilnya menuju tempat yang akan ia rasakan betapa segarnya air wudu membasahi sebagian tubuhnya. Fajar pun mulai tersenyum dengan sinarnya ketika La telah selesai menunaikan kewajibannya sebagai seorang muslimah.
“Yang kalian tanam di desa, kami di kota turut serta makan,” gumam La sambil menatap sayu melihat tayangan berita yang menjelanak semerbak dari kotak televisi di depannya. Masih kental larutan ingatan yang kau celupkan dalam bejana otaknya beberapa waktu lalu.
Semangat membara dari petani padi yang setiap hari mengurus, merawat sawahnya dari mulai mengolah tanah, menanam benih, lalu ditanam benih itu dan kemudian diketam. Lebih dari itu, usaha petani padi dalam menghasilkan beras dan kemudian menjadi nasi yang setiap hari kita makan, benar-benar membutuhkan proses yang panjang. Namun, sebagian dari kita tidak menghiraukan. Yang kita tahu hanya nasi yang sudah berada di atas piring. Ketika kita merasa kenyang atau malas untuk memakannya. Kemudian nasi itu dibiarkan saja bahkan kita membuangnya secara cuma-cuma.
Padi tidak tumbuh dalam satu hari. Jangan buang nasimu lagi. Karena di setiap suap demi suap nasi yang kita makan terdapat doa mereka. Jika kamu tahu bagaimana proses sebutir nasi bisa sampai di atas piringmu, mungkin kamu akan mengambil sisa nasimu kemarin di tempat sampah dan menghabiskannya saat itu juga.
Matahari tersenyum simpul di hadapan daun-daun hijau dan pohon-pohon di sekitarnya. Aroma tanah basah mengusik lubang hidungnya. Pagi. Masih sama seperti kemarin-kemarin.
***
Hamparan daun-daun hijau begitu luas. Tertetesi butiran-butiran embun dari atas. Melekat erat di dahan dan menghias nampak berkilauan bagai mutiara yang berbias. Beginilah suasana alam saat pagi di sawah. Memanjakan mata dengan pemandangan yang indah. Menatap terpaku seolah tak pernah lelah selalu segar terbasuh sejuknya udara pesawahan.
La menyempitkan matanya. Tangannya diletakan tepat di atas mata. Sejajar dengan alisnya yang tebal. Matahari sangat akrab pagi itu. Bercengkrama bersama wajah La. Sedangkan Pak Petani sedang asyik bersama benih-benih di genggaman daging dan tulang yang sudah tak muda lagi. Ditanamlah benih-benih itu dengan apiknya, air yang keluar dari pori-porinya menjadi bukti bahwa kerja keras petani tidak mudah. Ia tahu bahwa hidup ini bukan melulu soal mengeluh. Tuhan maha baik dan kehidupan tetap berjalan. Sampailah pada waktu istrihatnya. Benih-benih itu telah ditanamnya. Tangannya mengambil sebotol air mineral yang telah ia bawa. Diminumlah air mineral itu dengan tegukkan yang khas. Sementara angin sedang asyik bercumbu dengan bau keringat di tubuhnya. Wajahnya memerah, kusam, dan basah. Walaupun capingnya telah ia pakai, namun tetap saja saat itu cuacanya benar-benar panas.
Ia mengusap keringat di wajahnya dengan pelan. Matanya menatap ke bawah, melihat kaki yang telah terlumuri lumpur bersama rasa gatal yang tiba-tiba datang. Sunyi dan sepi. Suara Ariel Noah yang merdu bahkan lirihnya musik nasyid Nissa Sabyan pun tak terdengar di telinga. Hanya suara burung yang asyik berkicau bersama induknya, suara katak yang seolah merengek meminta makan, suara jangkrik yang selalu ingin dicari keberadaannya, bahkan bisikkan semut yang lagi-lagi meminta perhatian.
Kembali lagi, tangannya mengambil sepotong ubi rebus. Dengan lahap ia memakannya. Matanya kembali menatap ke bawah. Lumpur di kakinya telah sedikit mengering. Ia lupa harus membersihkan lumpur-lumpur itu. Sedangkan masa telah ramai berdemo di perutnya. Setidaknya ia telah mengisi energi untuk bisa bertahan sampai matahari lurus sejajar dengan kepalanya.
Kemudian, ia mengangkat tubuhnya dan berjalan menuju anak sungai. Terlihat air mengalir bersama darah di nadinya. Otot-ototnya terlihat menonjol ketika ia mulai membasuhkan air ke punggung kakinya. Ia basuh sedikit demi sedikit. Suara gemercik air sangat bersahabat dengannya, dihiasi denting rindu pada keluarga yang sesekali melintas di pikiran. Rasanya ingin sekali waktu cepat berlalu dan segera bersua di tengah-tengah harta yang tidak ternilai harganya.
***
Kakinya telah bersih dari lumpur-lumpur itu. Ia tersenyum melihatnya. Belum ia membalikkan tubuhnya, tiba-tiba suara gadis memanggilnya.
“Bapak!” teriak La.
La cepat-cepat menghampiri Pak Petani itu. Kaki mungilnya seolah-olah akrab dengan tanah serta rumput yang ia pijak. Setiap hari, La memang melewati pesawahan karena ia sendiri tinggal di dekat lingkungan pesawahan dan ia juga seorang aktifis lingkungan yang kapan saja ia bisa menemui hal-hal semacam ini. Dengan ransel di punggung dan bingkisan hitam di tangan. La mencoba menyeimbangkan langkahnya dengan tanah sedikit basah yang dilaluinya.
“Neng yang kemarin, ya?” tanya Pak Petani.
“Ya, Pak.” Jawab La dengan ramah.
“Mau kemana dan dari mana, Neng?” Tanya Pak Petani.
La tak menjawab. Ia memilih tersenyum sembari membantu Pak Petani berjalan melewati anak sungai. Sepertinya Pak Petani pun tak menjadi masalah soal jawaban dari pertanyaannya. La mengibaskan kain di kepalanya setelah bersentuhan dengan batang pohon mangga yang merupakan tempat tidur para semut dan serangga lain. Dari lubuk hatinya penuh harap, La ingin berbincang-bincang lebih lama bersama Pak Petani soal dunia pertanian dan lingkungan di desa tersebut.
Seperti biasa di kemarin pagi, mereka duduk di bawah pohon mangga. Namun, pagi ini berbeda. Mereka tak banyak berbincang-bincang. Entah itu tentang dunia pertanian, tikus berdasi, semut yang berjalan di atas air, bahkan rumput yang bergoyang pada waktu malam. Tak satu pun mengenai hal itu. Pagi ini, mereka berbincang mengenai La sendiri.
Pak Petani mengalihkan pandangannya ke arah matahari yang sudah mulai meninggi. Kepalanya penuh dengan suara lembut istri, teriakan anak bungsunya, bahkan suara wajan dalam tungku yang mengepul setiap pagi di dapur kecilnya. Dalam hatinya berkata “ saya harus segera pulang”. Keadaan anak bungsunya yang sedang sakit membuat pikirannya terbagi dua.
La pun tetap setia duduk di sebelah Pak Petani. Walaupun ia bertanya-tanya tentang apa yang sedang dipikirkan oleh Pak Petani ketika cukup lama menatap lingkaran besar bersinar di atas sana. La sesekali menegur Pak Petani dan bertanya tentang hal-hal kecil untuk mengalihkan pandangannya. Walaupun akhirnya Pak Petani memutuskan untuk mengakhiri perbincangan hari itu.
***
Sejak itu, La tidak lagi mencoba berbincang-bincang lagi dengan Pak Petani. Walau mereka dekat sekali. Lekat. Selekat aroma parfum yang membuat La bak habis menelan buah kepayang ketika berbincang tentang lingkungan.
Kini La hanya bisa melihat Pak petani dari kejauhan. Sekadar menyapa namun tak dapat berlama-lama. Hari-hari La terasa berbeda tanpa kisah dari Pak Petani. Ia sering mengurung diri di kamar. Dengan buku-buku Surealisme dan dunia lingkungannya. Mendengarkan teriakan adik kecilnya berlari-lari bersama dunia bermain di ruang tengah rumah barunya. Musik klasik yang sering diputar oleh Ibunya. Suara gemercik air yang mengalir di belakang rumah. Sesekali melamun. Menatap layar ponsel. Membaca berita-berita hoax ataupun kisah romantis dari sang pujangga Jalaludin Rumi. Namun, La sedikit beruntung. Ia bisa berbincang langsung dengan seorang Petani di sebuah desa yang baru ia tinggali beberapa bulan ini. Bahkan lebih dari itu ia dapat membangun suasana nyaman dan akrab. Karena bagi La, semua yang ia lakukan selama ini tak ada yang sia-sia.
Terlihat beberapa waktu yang lalu, Pak Petani telah menanam benih padinya. Ia juga telah melakukan proses perairan dan pemupukkan. Kini padi sudah tumbuh dan hijau meluas. Angin pun rindu akan tarian indah di waktu pagi, siang, sore, bahkan malam. Menari sebebas-bebasnya seperti burung yang terbang sesuka hati. Suara katak yang hampir tak mau berhenti sedangkan semut merasa terganggu sehingga ia rindu berjalan di kulit manusia.
***
Sejauh kisah bergulir, La percaya tak ada satu pun benang kusut yang tak ia urai di hadapan Pak Petani. Kisah Pak Petani mengalir deras kala La meraba detak jantung dan pikiran Pak Petani yang mengentak-entak. Kadang kala gejolak amarah bukan karena kecewa, namun bisa jadi karena terbiasa mengalah. Pak Petani tak pernah benar-benar ingin mengeluh. Walau peluh mereka di bayar murah.
Ku lihat hamparan luas itu. Padi pun mulai menguning. Waktu-waktu seperti inilah yang ditunggu-tunggu petani. Menunggu waktu panen dan melihat padi mereka mulai menguning sudah membuat mereka tersenyum.
Begitu pula dengan Pak Petani, ia tersenyum. Kebahagiaannya terlihat jelas di mata La saat itu. Sementara itu, binar mata La tak mampu menyembunyikan kegembiraan. Pagi itu, La memutuskan menghampiri Pak Petani. Kakinya berusaha untuk sampai di permukaan ladang. Sedangkan Pak Petani sedang melihat dan meraba padi-padi yang sudah menguning. Berjalan menyelusuri ladang. Bertemankan angin, panas, dan keringat, bahkan lelah yang setiap saat selalu muncul untuk mencoba merayu.
“Selamat pagi, Pak.” Sapa La.
Pak Petani tergelak dan terhenti dari aktivitasnya. Kepalanya menengok ke belakang persis ke hadapan La dan memandang penuh tanya. Dengan tangan yang masih memeriksa padi-padinya. Tak lama La sampai, tepat di samping Pak Petani.
“Eh, Neng lagi.” Gumam Pak Petani.
“Ya, Pak.” Jawab La tersenyum.
“Bagaimana kabar, Bapak? Cukup lama kita tidak bertemu. Tak terasa padinya sudah menguning ya, Pak?” Tanya La.
Pak Petani menjawab pertanyaan La dengan penuh senyum dan tawa. Seolah ia benar-benar bahagia seperti melihat padinya telah menguning dan siap dipanen. Mereka bertemu dengan tak sengaja dan berujung menjadi persaudaraan. Mereka membangun keakraban dengan saling menghormati. Setelah cukup lama, akhirnya mereka berbincang-bincang lagi.
Seingat La, dulu waktu pertama kali bertemu, Pak Petani jarang tertawa lepas. Ia hanya tertawa sekadarnya saja tapi pas pada porsinya. Tetap terlihat tulus, namun bagi La kurang lepas. Begitulah yang ada di dalam pikirannya. Tapi, La tak terlalu memperhatikan hal itu. Yang La tahu, Pak Petani adalah orang yang ramah dan suka tersenyum. La tak suka ketika melihat Pak Petani sedang di tengah ladang ketika cuaca tak lagi teduh yang membuat kain di dadanya basah, rasa gatal yang datang menyelimuti sebagian tubuhnya bahkan otot-otot di tubuhnya terlihat. Hal itu membuat La merasa iba. La merasa seusia Pak Petani sudah seharusnya berdiam dan beristirahat di rumah.
Sayangnya, sampai sekarang Pak Petani tetap melakukan pekerjaanya itu. Dalam tidur, La selalu memikirkan hal tersebut. Namun Labeeba sadar, ini adalah kehidupan. Setiap orang berhak memilih jalan hidupnya atau bahkan Tuhan sudah memilihkan jalan hidup orang masing-masing. Pak Petani hanya contoh kecil dari perihal kehidupan.
Setahu La, Pak Petani bukan hanya sebagai sosok bercaping yang membawa cangkul di tangannya. Namun, ia adalah sosok lelaki tua yang memiliki semangat luar biasa dalam menjalani hidup. Motivator bagi siapa saja yang bisa mengambil pelajaran dari sosok Pak Petani.
Petani memang selalu digambarkan sebagai sosok bercaping yang membawa cangkul di tangannya. Dalam kedudukan sosial petani pun sering kali ditempatkan di posisi yang rendah. Hari ini jika anak-anak ditanyai apa cita-cita mereka, hampir tidak ada yang ingin jadi petani. Kenapa? Bukankah mereka membanting tulang setiap hari demi sebulir nasi yang mengisi perut kita? Lalu apa yang sudah kita berikan kepada mereka? Sudahkah mengucapkan terima kasih? Atau hanya sekadar ucapan selamat pagi ketika menyapanya?
***
Sehari setelah Pak Petani memanen padinya. La manyatakan bahwa ia akan pindah dari desa itu.
Pak Petani tentu sedih mengetahuinya, namun ia bahagia karena dapat mengenal sosok La yang ceria.
Dapatkan reward khusus dengan mendukung The Writers.
List Reward dapat dilihat di: https://trakteer.id/the-writers/showcase.












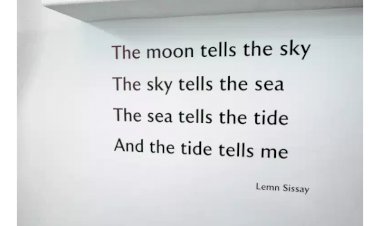

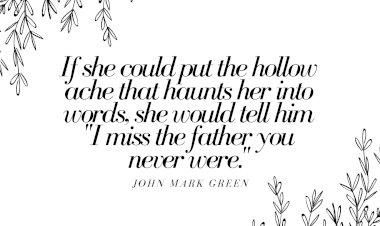



















![[Cerbung] Perawan Sunti dari Bawono Kinayung #1-4](https://thewriters.id/uploads/images/image_380x226_5e6db0a9bea1f.jpg)






