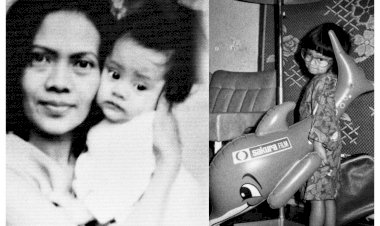JANGAN PERNAH MENYAKITI PEREMPUAN

JANGAN PERNAH MENYAKITI PEREMPUAN
Oleh : Dinarasokya Larasati
"Ceraikan aku."
"Lei ..."
Leia menampik tanganku yang terulur mencoba mengelus rambutnya. Kepalanya ia surukkan jauh-jauh ke balik bantal. Bahunya berguncang-guncang. Ah ia pasti menangis. Kugertakkan gigi sambil menengadah, menahan mata yang juga mulai basah.
Aku tahu hati Leia sakit, namun hatiku juga tak kurang sama sakitnya. Rambut lebatnya menutup sebagian muka pias. Aroma bedak bayi menguar dari tubuh melengkung merasakan nyeri, membuatku tak tahan untuk memeluk.
Kali ini Leia tak menolak.
"Ceraikan aku, Mas," bisiknya penuh rasa pedih, "kita selesai. Aku tak akan pernah bisa memaafkanmu."
Kulepas pelukan dengan hati-hati lalu berjalan keluar kamar. Amarahku menggelegak. Dalam hal ini, Leia yang salah. Aku bahkan tak menghukumnya. Yang kulakukan justru berusaha menyelamatkannya agar tak berubah jadi monster. Kenapa ia justru bersikap seperti korban?
Kutuang air putih dan meminumnya banyak-banyak, mencoba berpikir jernih dengan tenang.
Katanya tadi aku sudah menyakitinya. Menyakiti yang bagaimana aku juga tak paham. Tak secuil pun bagian tubuhnya pernah kusentuh dengan kasar. Tak sepatah pun aku pernah berucap tak sopan. Pernikahan kami yang sudah dua windu ini berjalan tenang dan adem. Segala keperluan dan keinginannya juga selalu kupenuhi. Apalagi yang kurang?
Amarahku berkobar lagi. Bagaimanapun, aku selalu ingat pesan ibu sebelum meninggal : jangan pernah menyakiti perempuan. Baiklah, kalau memang Leia merasa pernikahan ini sudah menyakitinya, aku akan mengalah. Akan kuceraikan dia.
*********
Gayung dari batok kelapa bergagang bambu itu mengayun secepat pedang jawara menebas musuhnya. Aku tak sempat menghindar. Suara berkelotakan ketika beradu dengan batok kepalaku sedetik menenggelamkan umpatan ibu.
"Dasar anak setan! Minggat seperti bangkotanmu sana!"
Dua kalimat itu samar masih terdengar ketika kunang-kunang di mataku berangsur padam. Gelap.
Saat sadar aku sudah di puskesmas. Kepalaku terbebat perban. Begitu pun beberapa luka di tubuh. Termasuk koreng bekas tusukan paku yang membuat kakiku bengkak hingga susah berjalan. Di lantai sebelah ranjang nampak ibu sedang bersimpuh di atas sajadah, khusuk mendaras tasbih.
"Bu," panggilku takut-takut. Tenggorokanku terasa kering mencekit.
Ketika ibu mendongak, senyumnya nampak lega, hatiku ikut lega. Ibu sudah tak marah.
"Haus, Bu. Mau minum."
Ibu mengangsurkan segelas air yang tadinya berada di nakas samping ranjang, mengawasiku minum dengan rakus sembari mengelus lembut tanganku yang diinfus.
"Gimana rasanya, Le? Badanmu sudah baikan?"
Itu bukan pertanyaan. Sebelas tahun usiaku, tujuh tahun terakhir membiasakan diri dengan ibu yang sewaktu-waktu bisa berubah menjadi monster, membuatku peka pada kalimat bersayap seperti itu.
"Ridwan ndak papa, Bu. Kita pulang saja."
"Yowes, biar ibu matur ke Pak Dokter. Tadi ibu sudah cerita kalau kamu jatuh dari puncak bukit tempatmu mengangon kambing."
Aku mengangguk. Kalimat ibu itu artinya menyuruhku berbohong. Aku tak boleh bercerita kalau ibu mengamuk karena aku telat mengisi gentong air di rumah. Luka-luka lebam bekas sabetan sapu, koreng tusukan paku yang membengkak membuatku demam hingga tak mampu menyelesaikan tugas harian tepat waktu, harus kuakui sebagai luka jatuh persis cerita ibu.
Dokter itu menatapku sangsi. Tapi aku berkeras pada cerita yang sama.
"Semalam hujan, Pak Dokter. Saya kehilangan kendali karena kambing saya mendadak lari waktu kami sedang menuruni lereng bukit yang licin. Saya terseret, jatuh menggelinding dan saat sadar sudah di sini."
Di sebelahku ibu duduk menunduk. Sebelah tangannya mengusap-usap punggungku. Alih-alih rasa sayang, setiap usapan kurasakan sebagai tikaman. Diam-diam aku bergidik.
Dokter itu masih menatapku dengan pandangan aneh. Namun ia mengangguk lalu menuliskan sesuatu di buku resep.
"Ya sudah, kau boleh pulang. Lain kali hati-hati." Ia meneruskan ucapannya pada ibu dengan nada mendadak tajam, "jaga putranya baik-baik ya, Bu. Bulan ini sudah dua kali ia masuk puskesmas dengan badan penuh luka. Jangan sampai ada perkiraan tidak baik tentang hal ini."
Ibu mendongak menampakkan ekspresi hendak protes, namun sepertinya ia berubah pikiran karena kemudian hanya mengangguk takzim lalu menyuruhku menyalami dokter itu.
Ayah pergi saat umurku empat tahun. Satu-satunya memori yang sempat terekam dalam benak kecilku adalah ayah sedang menjambak rambut ibu sambil menyepaki perutnya. Setelah itu ia menghilang dalam kegelapan subuh, meninggalkan ibu yang pingsan dalam kubangan darah yang mengalir dari sela-sela pahanya.
Dari cerita para tetangga ketika aku mulai besar, ayah kalap ketika ibu ketahuan selingkuh dan hamil. Pekerjaan ayah adalah salesman elektronik. Ia biasa berkeliling pulau Jawa, menawarkan produknya. Tak jarang dalam sebulan hanya satu dua hari bisa mampir rumah. Rupanya hal itu membuat ibu kesepian.
Yang kuingat kemudian hanyalah sejak kepergian ayah, ibu berubah. Rumah jadi sangat sepi karena tak ada lagi om yang datang menyapaku ramah dan membawakan mainan sebelum menghilang bersama ibu ke kamar. Tak ada lagi ibu yang asyik bersolek sambil menyanyi lalu sesekali mencium dan memelukku gemas. Yang tertinggal adalah ibu yang suka menangis terguguk saat bersimpuh mendaras doa, namun lima menit kemudian bisa mengamuk liar merapal umpatan hanya karena hal sepele saja.
"Ada kemungkinan ibumu penderita bipolar. Atau juga depresi tak tertangani pasca keguguran. Baby blues syndrom tak hanya dialami oleh ibu melahirkan. Sayang jaman itu tenaga medis dan konselor masih sangat terbatas." Demikian analisa dokter Malik, dokter puskesmas yang telah lama curiga pada luka di tubuhku setiap aku di bawa periksa.
Dokter itu pula yang kemudian mengadopsiku ketika pada ulang tahun ke dua belas ibu memberi hadiah tak terlupa. Kaki yang terjulur menendang muka saat aku membuka pintu sepulang sekolah. Bukan tendangan penuh amarah seperti biasanya, tapi semata gerakan kaki yang berayun dari tubuh yang sudah kaku tergantung. Ibu bunuh diri, meninggalkan secarik pesan : jangan pernah sakiti perempuan.
Maka tumbuhlah aku dengan jiwa terbelah. Lega sudah bebas dari ibu yang setengah gila, namun sekaligus merindukannya. Ada ruang kosong yang ajek terasa nyeri meski dokter Malik dan keluarganya memperlakukan aku dengan sangat baik. Termasuk merestuiku menikahi putri bungsunya, Leia.
Harusnya hidupku sudah sempurna. Bisnis propertyku berkembang bagus. Leia juga istri yang sempurna. Padanya kutemukan lagi ibuku yang suka menyanyi dengan wajah berseri seperti sebelum ayah pergi. Satu-satunya hal yang membuat kami bisa berselisih tajam adalah, Leia ingin punya bayi, dan aku tidak. Aku takut Leia berubah jadi ibuku yang monster.
Berkali-kali Leia meyakinkan bahwa situasinya dengan ibuku dulu berbeda, bahwa baby blues bisa ditangani agar tak menjadi parah. Tapi tetap saja, aku takut. Maka alangkah murka ketika aku tahu istriku sengaja melepas alat kontrasepsinya dan membiarkan dirinya hamil.
Hampir saja aku hilang kendali. Ada keinginan kuat untuk menjambak rambut panjangnya, menyeret sepanjang dinding rumah lalu menendangi perutnya agar janin sialan itu keluar. Sama seperti yang dilakukan oleh ayah dulu. Namun aku ingat pesan ibu, jangan pernah menyakiti perempuan. Maka kemudian yang kulakukan adalah memeluknya, mengucap selamat. Lalu bertahap menyelipkan misoprostol* di antara vitamin yang harus ia minum.
********
Seperti pesanku, ia sudah menyetel temaram lampu kamar motel. Senyumnya nampak malu-malu, terlihat lugu. Kulihat profilnya di situs kencan online tadi, umurnya masih 21 tahun. Separuh umurku. Masih sangat segar. Kusorongkan amplop lalu menariknya ke pelukan, menjilati telinganya dengan liar sementara ia baru membuka amplopnya.
Engahan nafas pemuda itu berubah jadi jeritan teredam lakban.
"Aku! Tak pernah! Mau! Menyakiti! Perempuan!" dengusku sementara tinjuku berderak-derak menghantam semua bagian tubuhnya yang bisa kujangkau.
Tanganku sudah terasa nyeri ketika kusadari pemuda itu terkulai diam. Kulepas ikatan tangan dan kakinya. Mencopot lakban di mulutnya lalu menutup tubuh telanjangnya dengan selimut setelah mengusap setiap incinya dengan tisu beralkohol.
Memastikan tak ada jejak tertinggal, aku turun lewat tangga yang langsung terhubung ke garasi di lantai bawah kamar. Tentu saja tak ada mobilku di sana. Sudah kutinggal di parkiran mal dekat situ. Berjalan meningalkan motel dengan topi menutup kening dan kacamata gelap melindungi separuh muka, aku yakin tak ada seorang pun mengenali dan bisa melacakku bila pelacur cilik tadi melapor polisi.
Aku butuh melampiaskan amarah. Namun sebagai anak baik, tentu saja aku harus patuh pada pesan ibu : jangan pernah menyakiti perempuan.
Sambi, 29 Mei 2020
Catatan kaki
Misoprostol : obat tukak lambung dosis tinggi yang sering disalahgunakan untuk menggugurkan kandungan.
Dapatkan reward khusus dengan mendukung The Writers.
List Reward dapat dilihat di: https://trakteer.id/the-writers/showcase.

 Dinarasokya Larasati
Dinarasokya Larasati