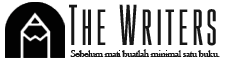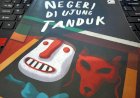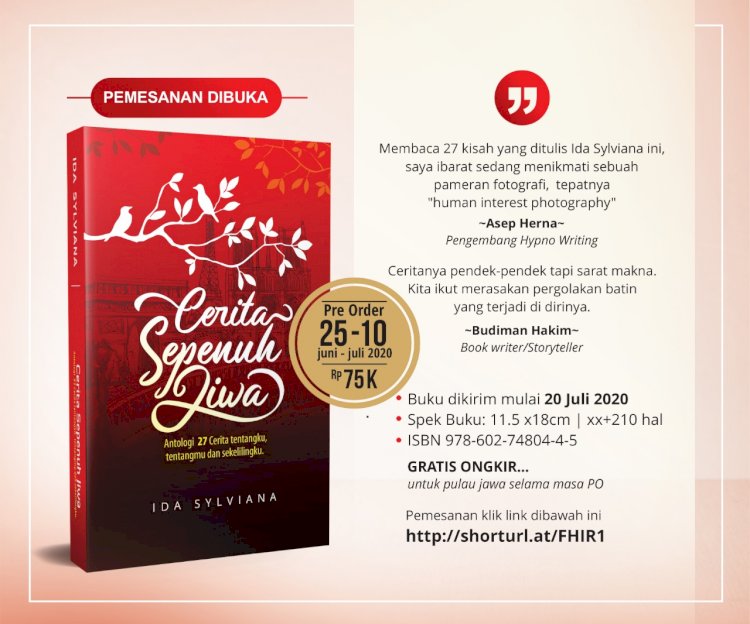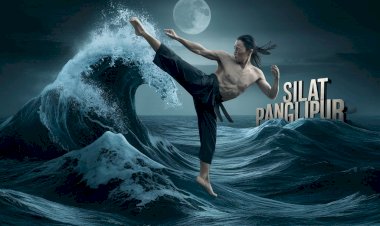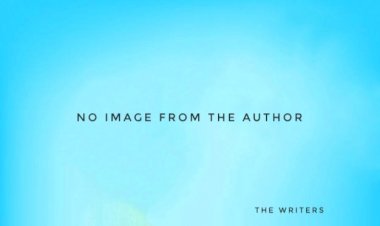Resonansi Komunikasi : Mengakhiri Rivalitas Cebong Versus Kampret
Rivalitas Cebong Versus Kampret adalah fenomena dehumanisasi. Merendahkan harkat dan martabat manusia dengan memberikan label layaknya hewan. Mengancam kualitas demokrasi dan etika berkomunikasi. Sebuah resonansi komunikasi diperlukan sebagai upaya mengakhiri perayaan caci maki ini.

Rivalitas ini bukan seperti Real Madrid dan Barcelona dalam tajuk El-Clasico. Bukan pula layaknya persaingan bisnis legendaris dalam dunia soda antara Pepsi dan Coca-Cola. Akan tetapi, rivalitas ini tentang rasa benci dan caci maki. Meski terkadang terlihat sangat jenaka kala perdebatan mereka selalu berakhir tanpa isi dan jauh dari substansi. Arena perseteruan mereka terjadi di alam maya dan nyata. Tak jarang merusak keakraban antara sesama anak bangsa sampai menghancurkan keharmonisan sebuah keluarga. Kehangatan antar sesama pun terasa hambar karena saling mengenal tapi tak lagi saling menyapa. Atas nama perbedaan pilihan segala bentuk gagasan dan sudut pandang menjadi tak ada artinya. Siapa yang paling keras menggebrak meja, paling kencang urat lehernya, paling lantang makiannya, maka masing-masing meyakini sebuah kebenaran sedang berada dalam genggamannya. Seolah nalar yang sehat telah dikalahkan oleh emosi yang pada akhirnya hanya melahirkan perang lontar sumpah serapah. Rivalitas cebong dan kampret adalah potret masalah komunikasi antar anak bangsa yang sangat memprihatinkan dan parah.
Istilah “cebong” dan “kampret” merupakan residu dari kontestasi pemilihan presiden tahun 2019 yang mempertemukan kembali calon presiden yang sama pada edisi sebelumnya. Singkatnya, cebong atau anak katak merupakan sebutan bagi pendukung setia Jokowi. Sedangkan kampret atau anak kelalawar menjadi sebutan untuk pendukung militan Prabowo. Bergabungnya Prabowo Subianto ke dalam pemerintahan sebagai Menteri Pertahanan dan Sandiaga Uno yang baru-baru ini juga diangkat sebagai Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif seharusnya menjadi momentum perdamaian. Alih-alih berdamai, sinisme dari dua kubu yang nihil gagasan ini masih riuh diberbagai arena media sosial. Buktinya, muncul lagi istilah baru yang disebut “kadrun” atau kadal gurun. Pada akhirnya perseteruan ini seolah-olah terpolarisasi lebih luas menjadi kelompok pro pemerintah dan anti pemerintah. Istilah-istilah bernada merendahkan ini sejatinya mengancam kualitas demokrasi kita karena ajang adu ide dan gagasan berganti menjadi ajang saling memaki yang bisa membahayakan kehidupan bersama.
Fanatisme buta ini menjadi masalah yang amat serius dalam etika komunikasi kita saat ini. Jika kita mengapresiasi kinerja pemerintah bersiaplah dinobatkan sebagai cebong. Begitu pun sebaliknya, jika kita memberikan kritik yang konstruktif sekali pun kepada kinerja pemerintah terimalah disebut kampret atau kadrun. Media sosial sebagai lokus dari komunikasi telah terkontaminasi oleh residu rivalitas yang tak ada habisnya. Fenomena ini disebut labelling dalam teori sosial. Salah satu teori yang relevan untuk menjelaskan hal ini diutarakan oleh Howard. S. Becker (1963) yang menyatakan bahwa pelabelan yang dialamatkan kepada seseorang seolah-olah orang tersebut dinyatakan sebagai devians atau berprilaku menyimpang (Akhmadi & Nur’aini, 2005). Sehingga, pelabelan terhadap seseorang akan mempengaruhi prilakunya meskipun bertentangan dengan keinginannya sendiri. Dampaknya, citra dirinya yang asli sirna karena digantikan oleh citra baru yang diberikan orang lain. Maka, seseorang yang dijuluki cebong hanya karena dia membela pemerintah dan seseorang yang dijuluki kampret atau kadrun hanya karena dia memberikan kritik terhadap kinerja pemerintah akan mempengaruhi citra dirinya meskipun bisa jadi awalnya dia menolak julukan itu terhadap dirinya. Akhirnya, berondongan penjulukan yang terus menerus itu secara tidak sadar akan membuat seseorang terbawa arus untuk ikut memberikan label kepada orang lain dengan segala kosa kata makiannya.
Belajarlah dari peristiwa pahit di masa lampau. Tragedi Holocaust misalnya, bermula saat Hitler bersama rezim Nazi menganggap bahwa ras Arya Jerman merupakan “ras unggul” dibandingkan dengan kaum lain seperti Yahudi, Roma (Gipsi), penyandang disabilitas, orang polandia, rakyat sipil Soviet, dan orang kulit hitam. Mereka memberi julukan “tikus” untuk menggambarkan betapa rendahnya kaum-kaum inferior itu. Puncaknya, menurut sumber Ensiklopedia Holocaust sekitar 6 juta orang yahudi dan ratusan ribu korban jiwa dari kaum lainnya melayang akibat persekusi dan pembantaian dalam tragedi tersebut. Tak kalah memilukan dari Holocaust di Jerman, genosida meledak di Rwanda antara Suku Hutu yang merupakan mayoritas dan Suku Tutsi yang menjadi minoritas. Konflik antara kedua etnis ini dipicu sentimen politik dimana hampir seluruh lini pemerintahan dikuasai oleh Suku Tutsi yang notabene minoritas. Propaganda kebencian pun disiarkan oleh pihak Hutu lewat radio dan surat kabar dengan narasi untuk membasmi “Inyenzi” yang dalam bahasa setempat artinya “kecoa” sebagai sebutan untuk Tutsi. Berdasarkan sumber Survivor Funds, genosida yang terjadi selama 100 hari pada tahun 1994 itu pun berhasil menewaskan lebih dari 800.000 orang Rwanda. Hal yang menarik yang bisa kita petik dari kedua tragedi itu adalah adanya dehumanisasi atau prilaku penghilangan harkat dan martabat manusia. Merendahkan manusia dengan narasi layaknya hewan rendahan dan menjijikan. Maka, perayaan caci maki yang merendahkan martabat manusia layaknya cebong dan kampret atau kadrun harus segera diakhiri.
Komunikasi dan bahasa adalah satu kesatuan. Komunikasi menuntut hadirnya bahasa dan bahasa hadir sebagai ekspresi berkomunikasi. Ibarat sebuah pisau, komunikasi bergandengan dengan bahasa bisa digunakan untuk menghidangkan pesan-pesan perdamaian. sebaliknya juga bisa digunakan untuk memotong-motong persatuan. Sepanjang sejarah republik ini berdiri berbagai konflik dan pergolakan yang pernah terjadi dapat diselesaikan dengan komunikasi. Sudah semestinya segala keterbelahan yang berlarut-larut ini pun diselesaikan dengan jalan komunikasi. Tak akan mudah itu niscaya. Tapi, relakah kita semua menyaksikan wajah peradaban bangsa yang luhur semakin mundur hanya karena alam bernegara telah dikotori oleh sikap merendahkan antar sesama. Bak bergetarnya sebuah benda karena adanya benda lain yang bergetar sehingga menghasilkan frekuensi yang sama, maka semua pihak perlu meresonansikan pesan-pesan damai kepada masyarakat. Pemerintah, elit-elit partai politik, tokoh-tokoh agama, media massa, hingga pegiat media sosial bergerak bersama untuk meredam narasi cebong, kampret, kadrun, dan segala olok-lolok bernada merendahkan guna mengembalikan percakapan publik yang lebih substantif.
Seluruh elemen bangsa harus bergerak bersama-sama dalam sebuah resonansi komunikasi yang membawa pesan-pesan perdamaian. Pemerintah bisa memulai dengan menertibkan dan meningkatkan pengawasan terhadap akun-akun di media sosial yang masih menggunakan diksi-diksi yang merendahkan layaknya cebong, kampret, dan kadrun tanpa mengurangi perlindungan akan kebebasan berpendapat. Selain itu, pemerintah harus terus mengupayakan meningkatkan literasi masyarakat agar melek berita sehingga dapat memilah berita hoax dan kredibel. Pemerintah harus melakukan upaya-upaya tersebut tanpa pandang bulu karena komunikasi terbaik antara pemerintah dan rakyatnya adalah melalui bahasa keadilan. Biarkan masyarakat berdebat dan beradu gagasan atas berbagai isu di ruang mana pun mereka bertemu. Hal itu jauh lebih baik daripada saling memberi label yang merendahkan sebagai manusia.
Pada waktu yang sama, tokoh-tokoh agama perlu kembali mengingatkan kepada setiap umat beragama agar menghargai sesama manusia sebagai sebuah perintah Tuhan Yang Maha Esa. Elit-elit partai juga harus memberikan contoh kepada masyarakat tentang kedewasaan dalam mengelola segala perbedaan. Perlihatkan kepada masyarakat bagaimana etika berkomunikasi yang seharusnya dilakukan serta bangun kecerdasan publik lewat lontar argumentasi. Para pegiat media sosial dari sisi manapun mereka berpihak sudah saatnya membuang jauh-jauh menyebut cebong, kampret, dan kadrun dalam narasi apa pun. Kubur dalam-dalam segala bentuk permusuhan dan ujaran kebencian. Silahkan beradu gagasan tentang segala hal tanpa harus merendahkan orang yang mengapresiasi pemerintah dengan sebutan cebong atau menghinakan orang yang memberikan kritik dengan sebutan kampret dan kadrun. Media massa pun harus menjaga kualitas pemberitaan tetap berada dalam prinsip-prinsip keberimbangan dengan memperhatikan kode etik jurnalistik. Semua bergerak dalam resonansi komunikasi yang sama.
Pandanglah masalah ini bukan lagi dari kacamata Jokowi atau Prabowo, 01 atau 02, Pro pemerintah atau anti pemerintah. Lihatlah masalah ini dari sudut pandang demi mengembalikan harkat martabat manusia dan peradaban luhur sebagai sebuah bangsa. Bicaralah atas nama bahwa kita semua adalah manusia yang menjunjung tinggi nilai-nilai perikemanusian yang adil dan beradab. Jangan sampai virus-virus dehumanisasi ini terus dipupuk. Sekali lagi, belajarlah dari sejarah agar kita paham betapa tak terhingganya harga dari sebuah persatuan.
Sumber Bacaan :
Ahmad Junaidi, Eko Hari Susanto, Rilis Loisa. 2018. Media dan Komunikasi Politik : Potret Demokrasi di Indonesia dalam Perspektif Komunikasi. Yogyakarta : Mbridge Press.
Dadi Akhmadi dan Aliyah Nur’aini H. 2005. Teori Penjulukan. Jurnal Komunikasi MEDIATOR : Universitas Islam Bandung.
M. Tazri. 2019. Cebong dan Kampret dalam Perspektif Komunikasi Politik Indonesia. Jurnal PERSPEKTIF Komunikasi : Universitas Muhammadiyah Jakarta.
Dapatkan reward khusus dengan mendukung The Writers.
List Reward dapat dilihat di: https://trakteer.id/the-writers/showcase.