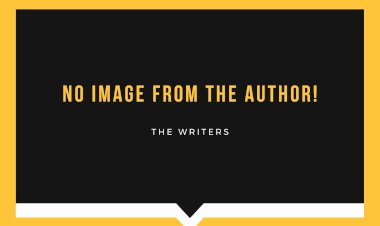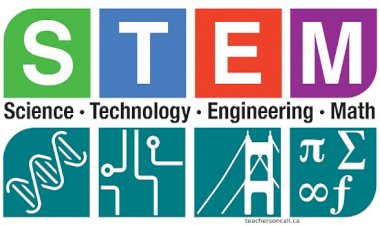Kobaran Api
Kobaran api, bisa jadi adalah perlambang pembersihan jiwa. Entah dimana aku baca kalimat itu. Begitu melekat dalam ingatan, hingga sebuah kejadian mengizinkanku merasakan sensasinya.

Kami berkumpul di teras rumah. Semua. Mungkin bersepuluh atau berdua belas. Sahabat-sahabat kami penduduk asli Tanah Tradisi juga. Mereka mengenakan pakaian sehari-hari tradisi mereka yang bersahaja. Kemeja kain katun berpewarna alam jahit tangan. Semacam sarung tenun pendek selutut, menjadi 'celana' bagi mereka. Ikat kepala pun berbahan kain katun tanpa bahan sintetis. Semuanya menggunakan bahan alam.
Ada David. Ada Christian.
Semua mengerumuni Mia, Si Gadis Tomboy, yang sudah lama sekali nggak singgah ke rumah keluarga kami. Mia, duduk bersila, mengulurkan tangan kirinya. Telapak tangan kiri Mia dibentangkannya lebar-lebar. Semua orang, kuulangi lagi, semua orang tanpa kecuali memandang ke arah telapak tangan kiri Mia, termasuk aku. Al nggak ada. Raras juga nggak ada. Mereka berdua sedang ada acara di luar kota.
Mereka semua yang di teras rumah bilang, mereka bisa melihat 'sesuatu' di telapak tangan kiri Mia. Mereka bilang, mereka seperti melihat tayangan video. Semua! Kecuali aku.
Duh, sedihnya menjadi aku yang berbeda dari mereka.
Meski begitu, kupaksa juga mataku kuarahkan ke telapak kiri Mia.
Sedetik.
Dua detik.
Lima detik.
Tak ada apa-apa.
Maka aku pun segera mengalihkan pandangku. Diam. Selintas aku melihat wajah-wajah mereka mengekspresikan kengerian.
Aku beranjak. Bangkit, turun dari teras rumah panggung kayu itu.
Saat itu lah aku mulai mengeja sebuah 'rasa' yang tiba-tiba menyeruak dari dasar ulu hatiku. Tangisku meledak. Bukan sekedar isak tangis, tetapi sesenggukan yang dahsyat. Terguguk-guguk tangisku pecah berkali-kali. Hampir setengah meraung-raung, seperti seekor induk Orangutan yang anaknya terlepas dari penjagaan dan pelukannya, lalu tertangkap pemburu liar, bahkan mati di tangan pemburu biadab itu. Induk Orangutan yang malang yang menjadi saksi atas nyawa anaknya yang meregang. Begitulah perumpamaanku.
Aku merasakan Al dikungkung api yang menyala-nyala. Besar. Sedemikian besar hingga melampaui tinggi badannya. Berkobar-kobar api itu.
Merah.
Biru.
Orange.
Biru.
Kuning.
Biru.
Merah.
Oh, betapa sedih hatiku 'menyaksikan' Al sendirian meronta dan melawan dengan segala macam jurus yang dikuasainya memerangi Sang Api.
Tidak. Tidak. Tidak.
Itu semua tidak 'kulihat' di telapak tangan Mia. Itu semua timbul dari 'rasa' yang ada di dalam hatiku. Dari tengah-tengah dadaku. Duh! Aku jadi bingung. Ini semua tentang 'rasa' yang bisa 'melihat'. Tergambar, namun tidak berupa tayangan video di layar.
Oh, Tuhan. Aku bingung dan tak paham.
Semua orang di teras mulai mengalihkan pandangnya kepadaku. Mungkin mereka memaklumi tangisku yang di benak mereka pecah karena betapa berbedanya aku dari mereka. Aku tak peduli. Ketika Pulung, saudara Tanah Tradisi beranjak ke arahku, Christian menahannya. Dengan bahasa tubuhnya, Christian mengatakan untuk membiarkan saya sendiri saja.
Ya, aku memang butuh untuk bersendiri.
Kuseka air mataku yang makin deras saja mengalir. Aku memilih berjalan cepat-cepat menjauh dari kerumunan orang-orang di teras. Akhirnya kuputuskan untuk berlari, menuruni tebing di sisi Selatan rumah panggung kayu dengan hati-hati, berlari terus aku berlari. Tak peduli alas kaki entah dimana. Jalanan menurun di dekat rumpun bambu kuning kuturuni secepat cicak melahap nyamuk dengan lidahnya. Kulewati kebun terong dan pepaya. Kuhiraukan kolam besar berisi teratai yang masih menyisakan beberapa kuntum bunga berwarna merah muda.
Aku terus berlari. Kucapai sebuah saung bambu beratap rumbia. Ilalang tinggi penuh sekeliling. Seakan menjadi tempat persembunyian yang sempurna.
Di situ aku menangis sejadi-jadinya.
Al, adakah kakak terbaik yang kumiliki. Betapapun kadang becandanya kelewatan. Betapapun sering ia mencekokiku dengan begitu banyak hal absurd kehidupan. Betapapin jika sedang marah, bibirnya yang tipis semakin tipis dan ..... tajam. Pedas, terdengar di telinga. Bila sedang marah, ia tak meninggalkan jeda - bahkan ruang - bagi yang dimarahinya untuk bersuara. Justru ia yang perlu jeda dan ruang untuk dirinya sendiri menjauh dari hiruk pikuk sekitarnya. Namun merasakan Al berada di dalam kobaran api yang dua tiga kali besarnya dari tubuh Al, dan melihatnya kewalahan melawan? Oh, tidak! Tidak tega aku.
Tangisku perlahan mereda, berubah menjadi sesenggukan. Mungkin karena kurasakan perlawanan Al dalam kobaran api itu sangat gigih dan persistent, hingga ada celah besar kemenangan di pihaknya, meskipun Al sangat kewalahan. Dan aku pun kewalahan mengendalikan air mata, kegeraman, rasa sedih, dan seluruh doa yang bisa kurapal bagai mantra untuknya.
***
Lalu tiba-tiba aku terbangun. Suara adzan Subuh berkumandang menendang-nendang gendang telingaku. Keringat membanjiri tubuhku hingga kuyup.
Aku masih sesenggukan. Kupandangi sekelilingku, bukan saung bambu dalam rimbun ilalang, melainkan kamar tidurku.
Dapatkan reward khusus dengan mendukung The Writers.
List Reward dapat dilihat di: https://trakteer.id/the-writers/showcase.