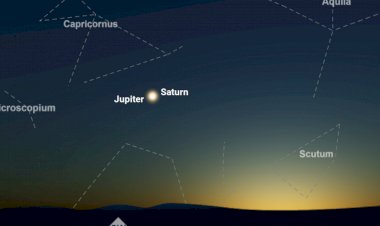Bukan lelaki idaman

BUKAN LELAKI IDAMAN
Vee Cemal
He wasn’t good with words, and didn’t put his love on display loudly, but it was there.
Quiet, steady and true. It showed in the things which he did and didn’t do.
Aku tidak pernah membayangkan bahwa aku akan menikah karena dijodohkan oleh orang tuaku. Selama ini aku mengira orang tuaku berpikiran moderen karena sudah membolehkan anak perempuannya mendapatkan pendidikan tinggi. Mereka bahkan membolehkanku pergi ke luar negeri tanpa pengawalan mereka atau saudara-saudaraku. Namun aku tidak menduga bahwa mereka sudah menyiapkan suami, dan sudah lama merencanakan pernikahanku.
Suamiku adalah anak kawan lama ayah. Mereka berteman sejak lama dan menginginkan tali silaturahmi mereka langgeng. Lalu mereka berniat bahwa bila anak-anak mereka berlawanan jenis, maka mereka akan menikahkannya. Ibuku tidak keberatan karena baginya bibit, bobot dan bebet sangatlah penting untuk memilih pasangan. Sementara aku belum pernah mengenalkan seseorang pun sebagai pacar kepada keluarga. Kedua kakak perempuanku semua sudah menikah dengan laki-laki pilihan mereka. Maka pilihan jatuhlah kepadaku.
Awalnya aku ingin lari meninggalkan rumah karena tidak menginginkan pernikahan itu. Aku bahkan sudah meminta izin seorang teman untuk sementara tinggal di apartemennya sambil mencari rumah kos yang cocok. Teganya ayah dan ibu menikahkanku dengan orang yang tidak aku kenal? Tapi rencana itu ketahuan oleh kakakku karena temanku secara tidak sengaja menanyakan kepastian soal apartemen kepada kakak.
“Ayah dan ibu tidak mungkin mencarikan jodoh yang tidak baik untukmu, Aisyah. Mereka pasti sudah mempertimbangkan masak-masak seperti apa yang akan menjadi suamimu. Firdaus seorang insiyur dengan pekerjaan dan masa depan yang baik. Dan dia datang dari keluarga yang sudah dikenal baik oleh ayah dan ibu. Buat kak Anisah, ini lebih baik daripada kamu mencari pasangan yang belum tentu mendapat restu dari ayah dan ibu. Mungkin ini juga jalan yang diberikan Allah untuk kamu membalas pengorbanan ayah dan ibu. Ingat waktu kamu pergi ke Inggris untuk summer course. Sekalipun berat buat mereka melepas anak gadisnya ke negara asing, tapi karena kamu memaksa demi memperdalam bahasa Inggris kamu, mereka memberikan izin. Mereka mengalah demi kebaikan kamu. Jadi sekarang cobalah memahami keinginan mereka untuk mendapatkan menantu yang baik,” kakakku, Anisah, memberikan pendapatnya.
“Lalu bagaimana dengan cinta kak? Bagaimana aku bisa mencintai seseorang yang tidak aku kenal? Bagaimana aku bisa menjadi istri buat laki-laki yang asing buatku?,” aku bertahan pada pendirianku.
“Belajarlah mengenal dia. Pernikahan bukanlah akhir dari pembelajaran mengenai pasangan kita. Suami-istri yang sudah bertahun-tahun hidup bersama pun masih terus belajar mengenai pasangannya. Belajar untuk menerima kelebihan dan kekurangan pasangan kita, dan jangan paksakan dia menjadi orang yang kamu mau. Setelah kamu mengenal pasanganmu, cinta akan datang dengan sendirinya.”
Apa mungkin? Bagaimana bisa? Aku meragukan perkataan kak Anisah.
Seakan membaca pikiranku, Kak Anisah memelukku dan mengusap air mataku. “Ridho lah pada jodohmu. Mungkin Allah sudah menentukannya seperti ini. Insya Allah suamimu adalah lelaki terbaik.”
***
Pada akhirnya aku mengalah kepada keinginan orang tuaku. Aku tidak ingin ribut dengan mereka. Mengikuti apa kak Anisah bilang, aku menyerahkan jodohku kepada Allah. Aku akan mencoba menjadi istri yang menjalankan tugas rumah tangga, namun aku tidak yakin bisa bermesraan dengan suamiku. Buatku, hubungan suami-istri bisa dilakukan bila ada cinta di antara keduanya. Jadi, terserah saja dia mau bertindak apa karena aku tidak akan memulainya.
Resepsi pernikahan aku dan Firdaus, ramai didatangi para kerabat dan teman keluarga kami. Apalagi aku adalah anak bungsu di keluargaku, dan Firdaus adalah anak laki-laki pertama yang menikah di keluarganya. Beberapa temanku datang dan berbisik kalo aku beruntung punya suami yang ganteng. Memang aku akui wajah dan perawakan Firdaus cukup menarik. Namun tetap saja, ia adalah orang asing bagiku.
Malam pertama kami tidaklah seperti yang diceritakan banyak orang. Setiba di rumah orang tuaku usai resepsi, aku buru-buru masuk ke kamarku yang menjadi kamar pengantin, membersihkan wajah dari make up dan mengganti baju. Aku tidak mau berbicara dengan Firdaus apalagi bercumbu dengannya. Bagiku, janji kepada ayah sudah kupenuhi. Cepat-cepat aku naik ke tempat tidur, menutup rapat diriku dengan selimut lalu mengambil posisi membelakangi Firdaus.
Setengah jam kemudian aku mendengar ia masuk ke kamar. Ia mengambil baju pengantin yang aku biarkan di kursi meja rias, lalu menggantungnya di gantungan baju. Setelah itu ia ke kamar mandi, dan tak lama aku mencium bau sabun. Mungkin dia mandi, aku tak tahu. Koper bajunya sudah dikirim ke rumahku sehari sebelumnya. Perlahan dia merebahkan dirinya di sampingku.
Aku mencoba untuk tetap terjaga agar aku tidak merubah posisi tidurku. Namun penat di badan membuat kantukku tak tertahan, dan aku pun tertidur pulas. Sampai keesokan harinya, ada yang mengguncang bahuku secara perlahan.
“Aisyah, bangun. Sudah subuh, dek. Kita shalat berjama’ah.”
Biasanya aku bangun dengan bantuan alarm. Namun rupanya tadi malam aku lupa menyalakan alarm. Aku lihat Firdaus sudah menggelar sajadah. Buru-buru aku bangun dan mengambil air wudhu. Sementara itu, Firdaus membaca zikir. Usai mengenakan mugena, aku berdehem menyatakan aku siap untuk shalat. Ia menengok ke belakang, lalu berdiri mengumandangkan qamat.
Usai shalat, aku bergegas ke dapur. Kulihat ibu sudah sibuk menyiapkan sarapan seperti biasa. Ibu tersenyum melihatku, lalu menyorongkan roti dan selai.
“Ayo, buatkan sarapan buat suamimu.”
***
Satu minggu harusnya menjadi waktu bulan madu kami. Namun aku masih tidak mau berdekatan dengan Firdaus. Aku biarkan dia lebih banyak mengobrol dengan ayah, atau membaca buku. Ia pun tidak memaksaku untuk berbicara dengannya. Orang tuaku tidak menaruh curiga karena aku rajin menyiapkan sarapan, makan siang dan makan malam buatnya. Aku juga menjawab setiap pertanyaannya pada saat makan.
Sekali kami ke rumah orang tuanya untuk bersilaturahmi. Mereka menyambut kami dengan ceria. Firdaus juga terlihat bahagia bisa berkumpul dengan keluarganya. Kami nampak seperti pengantin baru layaknya, tapi aku tetap menjaga jarak dari suamiku.
Namun sore itu, Firdaus datang menghampiri.
“Aisyah, bisa bicara sebentar?”
“Ya, ada apa?” jawabku sambil menutup laptopku.
“Minggu depan aku sudah harus balik bekerja. Dan rumah orang tuamu ini terlalu jauh dari kantorku. Aku juga tidak mau memberatkan orang tuamu. Aku punya apartemen yang dekat dengan kantor. Bagaimana kalo kita pindah ke sana?”
Berpisah dengan orang tua? Hanya berdua saja dengannya? Aku mulai merasa panik. Aku tidak mungkin menolak ajakannya karena aku harus berada bersamanya. Tapi bagaimana aku menjalani keseharianku berdua saja dengannya? Bagaimana aku menghindar berbicara dengannya? Kalo aku menolak, maka orang tuaku akan bertanya macam-macam. Mana ada pengantin baru yang pisah rumah karena istri lebih senang di rumah orangtuanya?
“Ya bang. Nanti aku rapihkan pakaian.”
“Tidak usah bawa terlalu banyak. Nanti khan kita bisa ke sini lagi. Sekalian menengok ayah dan ibu.”
Firdaus seakan membaca keraguanku.
***
Apartemen suamiku tergolong besar. Ada satu kamar tempat tidur utama, dan satu kamar yang dijadikan kamar kerja. Lalu ada ruang tamu, ruang makan dan dapur, dan ruang mencuci baju. Lokasinya memang tidak jauh dari kantornya sehingga dia pulang-pergi hanya dengan mengendarai sepeda.
“Sekalian olah raga. Abang tidak bisa menyisihkan waktu untuk itu. Lagipula Abang gak harus mengeluarkan uang untuk bensin kan? Paling bensinnya satu piring nasi uduk, oseng tempe dan telur balado,” katanya mencoba untuk mengajakku berbicara.
Dia menyebut dirinya dengan abang karena kedua adiknya memanggil demikian. Aku tidak ambil pusing dengan sebutan, dan mengikuti saja kebiasaan itu.
“Jadi abang mau aku buatkan nasi uduk untuk dibawa ke kantor?”
Aku berusaha mengingat-ingat resep nasi uduk. Atau nanti aku bisa belajar dari youtube. Menyiapkan makanan buatnya sekarang sudah menjadi kebiasaan. Lagipula aku perlu kesibukan untuk tidak berada di dekatnya, dan memasak bisa menjadi alasan.
“Ah tidak usah, dik. Di kantor ada kantin yang jual nasi uduk. Lumayan rasanya. Nanti kalo abang tidak beli, penjualnya kekurangan pelanggan.”
Sedikit demi sedikit aku mulai paham selera makan suamiku. Dia tidak pernah memilih makanan, bahkan dia lebih menyukai masakan rumah yang sederhana. Dia selalu memuji makanan yang dihidangkan walaupun buatku makanan itu tidak enak. Satu waktu aku mencoba memasak gulai ayam, dan aku memasukkan terlalu banyak lada. Rasanya menjadi pahit dan pedasnya membakar kerongkongan. Tapi Firdaus tetap memakannya.
“Makannya harus dengan timun. Jadi rasa pedasnya tidak terasa,” katanya melihat aku yang menatapnya bingung karena ia makan timun sangat banyak.
Di apartemen ini tidak terlalu banyak barang. Apartemen tipikal untuk bujangan. Di lemari baju, pakaian Firdaus tersusun rapi. Tapi dimana-mana ada buku. Mungkin waktu luangnya lebih banyak dihabiskan dengan membaca buku. Di ruang kerja, ada sudut dengan sajadah. Dia memang tidak pernah lupa shalat, dan selalu mengingatkanku untuk shalat berjama’ah dengannya.
“Kamu boleh mengatur apartemen ini sesukamu. Belilah barang yang kamu butuhkan, nanti aku berikan uangnya.”
Aku mulai membuat catatan di kepala. Lalu aku mulai membayangkan dekor seperti apa untuk apartemen ini. Untuk seterusnya Firdaus menepati janjinya dengan memberikanku uang. Ia bahkan selalu menanyakan apakah uang yang diberikannya cukup atau tidak. Namun aku tidak terus menerus meminta uang kepadanya karena aku juga memiliki penghasilan. Pekerjaanku sebagai penerjemah lepas memberi pemasukan yang cukup.
***
Lima hari sudah aku berdua saja di apartemen ini. Rutinitas yang kami jalani selalu sama. Bangun, shalat berjamaah, lalu aku membuatkan sarapan sementara Firdaus bersiap pergi ke kantor. Setelah itu aku membersihkan rumah, mencuci atau menyetrika pakaian, dan menyelesaikan naskah terjemahan. Sore hari aku menyiapkan makan malam sambil menunggu Firdaus. Saat makan malam, ia akan bercerita tentang kesibukannya di kantor dan menanyakan perkembangan pekerjaanku. Setelah makan malam, Firdaus melanjutkan pekerjaannya dan aku membereskan dapur. Waktu tidur, aku akan masuk kamar terlebih dahulu, membungkus diriku dengan selimut dan tidur dengan posisi membelakangi suamiku.
Selama itu, Firdaus tidak pernah berusaha untuk bercumbu denganku. Ia bahkan tidak keberatan aku duduk jauh darinya saat menonton TV. Tapi ia selalu mengingatkan untuk shalat berjamaah dan menawarkan bantuan untuk pekerjaan rumah.
Seharusnya aku merasa lega dengan rutinias ini. Namun hati kecilku terusik. Sampai kapan ia bisa tahan dengan perlakuanku? Sampai kapan pula aku memperlakukan suamiku seperti ini? Ia sangat sabar dan perhatian, soleh dan serius menjalani pernikahan kami. Mana ada laki-laki yang tahan tidak berhubungan dengan istrinya selama itu, apalagi kami adalah pengantin baru?
Akhirnya aku beranikan diri bertanya kepadanya.
“Bang, kenapa abang mau dijodohkan denganku? Abang pintar, punya karir yang bagus. Kenapa abang tidak cari istri sendiri?”
“Bohong kalo abang bilang abang tidak pernah pacaran. Tapi selama ini perempuan yang menjadi pacar abang tidak mendapatkan restu orang tua. Bagaimana abang bisa menikahi perempuan yang tidak disetujui mereka? Orang tua abang sudah banyak berkorban untuk pendidikan abang. Sekarang abang sudah bekerja dan bisa menawarkan banyak materi untuk mereka. Tapi bukan itu yang mereka mau. Mereka menginginkan abang menikah dengan perempuan yang nantinya bisa menjadi istri dan ibu yang baik. Akhirnya abang serahkan pilihan itu kepada mereka, dan mereka memilihmu.”
“Abang tidak merasa dijebak? Bagaimana abang bisa menjalani pernikahan dengan orang yang tidak abang kenal?,” tanyaku lagi.
Firdaus menatapku tajam.
“Apakah Aisyah orang jahat? Apakah Aisyah tidak pintar?”
Aku menggeleng.
“Lalu kenapa abang harus merasa dijebak? Abang yakin orang tua abang mencarikan perempuan yang sholehah, baik dan pintar. Perempuan yang bisa menjadi pendamping dan ibu yang baik untuk anak-anak abang nantinya. Sekarang lihat istri abang. Dia cantik, sarjana, pintar mengurus rumah dan memasak. Siapa yang tidak akan jatuh cinta dengan perempuan seperti itu?”
Pujian Firdaus membuatku tersipu. Lalu, apa iya dia jatuh cinta kepadaku? Apa karena itukah dia selalu sabar menghadapiku? Tapi cinta kah aku kepadanya?
Perlahan Firdaus meraih tanganku.
“Aisyah, abang mungkin bukan lelaki idamanmu. Tapi kamu adalah perempuan idamanku. Sejak dulu abang mencari perempuan sepertimu. Kamu mungkin merasa belum cukup mengenal abang, seperti abang juga masih belajar mengenalmu. Kita berdua sama-sama belajar. Tapi yakinlah kalo abang ingin pernikahan kita langgeng karena Allah sudah menjadi saksi atas sumpah pernikahan kita. Insya Allah abang bisa menepati janji dan membahagiakan kamu”
Aku tidak bisa berkata-kata mendengar ucapannya. Sebelumnya aku berpikiran negatif mengenai alasan Firdaus mau dijodohkan. Tapi perlakuan dan ucapannya menggerus semua pikiran negatif itu dan aku berbalik mengaguminya. Apakah ia akan menepati janjinya, aku tidak bisa menerkanya. Yang aku tahu sekarang ia punya niat baik untuk menikah, dan ia memilihku untuk menjadi istrinya.
Firdaus terus memegang tanganku. Ia melanjutkan bicaranya tentang rencana masa depan kami. Aku mendengarkan dengan khidmat karena aku belum pernah memikirkannya. Namun ia meminta pendapatku, dan kami pun akhirnya berdiskusi tentang banyak hal. Semakin lama kami berbicara, semakin aku respek kepadanya. Suamiku bisa menjadi teman diskusi dan pendengar yang baik. Ia memiliki wawasan yang luas dan sangat terbuka menceritakan perasaan dan pikirannya.
Tidak terasa kami duduk makin berdekatan, dan aku bisa merasakan kehangatan tubuhnya. Ia masih tetap memegang tanganku, dan sesekali ia menciumnya. Awalnya aku terkejut, dan ingin menarik tanganku. Tapi Firdaus tidak melepaskannya dan terus berbicara. Kedua kali dan seterusnya, aku tidak lagi merasa canggung dengan ciumannya. ‘Sungguh suami yang sopan,’ batinku berkata, ‘ia merayuku dengan cara yang halus.’
Jam sudah menunjukkan angka sebelas. Biasanya aku sudah berada di tempat tidur. Tapi malam ini aku yakin dengan keputusanku.
“Sudah malam, bang. Ayo kita tidur.”
SELESAI
Untuk seorang sahabat.
Ceritamu menjadi inspirasi tulisan ini.
Dapatkan reward khusus dengan mendukung The Writers.
List Reward dapat dilihat di: https://trakteer.id/the-writers/showcase.