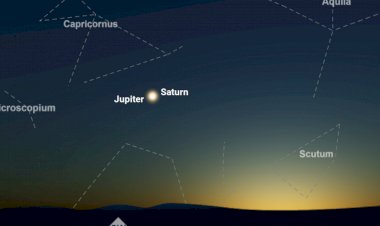Warta Membawa Petaka (III)

Pintu ruangan Ati diketuk dengan lembut.
“Ya,” sahutnya sambil memnadang jam dinding yang menunjukkan jam 09.00. Dari balik pintu muncul wajah Karina, rambutnya yang dipotong pendek di atas kuping dengan style sportif terlihat sedikit berantakan, senyumnya terurai, membuat wajahnya yang selalu ramah menjadi tambah ramah.
Penampilannya yang selalu sportif tampak segar dengan blus katun model jaket dan celana jeans warna gelap. Mungkin senyum Rina atau penampilannya yang muda, enerjik seoalah menghangatkan ruangan Ati yang terasa kaku dan dingin.
“Selamat pagi Mbak Ati,” sapa Rina dengan ramah.
“Pagi Rina, gimana perjalanan dari rumah? Lancar?” sambut Ati menyambut kehangatan Karina. Karina pun menceritakan dengan singkat pengalaman perdananya naik KRL dalam masa pandemi. Ati mendengarkan sambil mengirimkan pesan whatsapp kepada Wisnu agar segera bergabung. Wisnu masuk ruangan tepat setelah Karina selesai bicara.
“Sudah datang semua ya. Jadi bisa kita mulai nih Pak Wisnu,” kata Ati.
Wisnu menganggukkan kepalanya. Ati memulai pembicaraan dengan nada suara lembut, ramah, seperti biasa, namun ini tidak menenangkan Rina. Hatinya was-was, ada apa? Ini bukan saat regular assessment, apa salahku. Beberapa menit berlalu, Rina masih belum paham mengapa ia dipanggil. Kalimat-kalimat Ati yang halus hanya terdengar sepotong-sepotong olehnya.
“Rina handal … kolega senang , lingkungan hidup, pimpinan menegur…” Perhatian Karina terbelah, ia mencoba mengingat-ngingat, liputan yang mana yang kira-kira tidak berkenan.
Ditegur, lingkungan hidup? Masak? Tanyanya dalam hati. Tulisan lingkungan hidupku kan dapat penghargaan, dari organisasi dunia di bawah naungan PBB, yaitu United Nations Environmental Programme, disingkat UNEP. Waktu itu semua memujiku, termasuk Mas Wisnu, Mbak Ati, bahkan Pemred, katanya dalam hati.
Ingatannya kembali kepada tulisannya dengan judul Banjir badang di Rumah Gadang. Liputan ini mengulas banjir badang di Sumatra Barat, mengupas secara mendalam kekacauan tata-kelola pengelolaan lahan: perijinan yang selalu diberikan untuk pembukaan perkebunan berskala besar, kasus-kasus korupsi yang menyertainya, masyarakat yang terus menderita serta analisis yang tajam mengenai dampaknya pada perubahan iklim. Penghargaan dari UNEP itu juga yang mendorong lahirnya komunitas Earth Lover di Titian yang dimotori Karina.
“… penghargaan dari UNEP… tapi,..” terdengar suara Ati.
Rina tersentak, jantungnya berdebar keras, dengan konsentrasi penuh ia mendengarkan Ati.
“Pimpinan berpendapat tulisan Rina tidak lagi objektif. Jadi membahayakaan perusahaan,” lanjut Ati.
Rina menggeser duduknya. Punggungnya membungkuk, agar bisa lebih jelas mendengarkan kalimat-kalimat Ati, bibirnya mulai terbuka.
“Dengarkan dulu ya Rina. Mulai besok Rina tidak lagi bertanggung jawab untuk isu lingkungan hidup dan perubahan iklim. Tugas Rina selanjutnya adalah seputar kepolisian, khususnya kriminal.” Rina serasa dilempar bom, tangannya terasa dingin, lidahnya kelu.
“Silahkan Pak Wisnu, monggo dilanjutkan, “ kata Ati sambil menguatkan hatinya.
“Saya tahu bahwa keputusan ini sungguh berat bagi kamu Karina,” suara Wisnu yang biasanya terdengar sejuk, sekarang terasa sumbang di telinga Rina.
“Tapi anggaplah ini sebagai sebuah pelajaran. Tidak selamanya dalam hidup ini kita bisa mendapatkan apa yang kita inginkan,” lanjut Wisnu sambil menatap wajah Rina yang terlihat pucat, bibirnya bergetar, pasti dia sudah gak sabar untuk menyela, pikir Wisnu.
“Saya selesaikan dulu ya Karina. Habis ini waktumu bicara,” sambung Wisnu dengan datar.
Rina merasa Wisnu menghabiskan waktu yang terlalu lama hanya untuk mengulang apa yang sudah disampaikan Ati: bahwa ia, Karina, berbakat, pandai, teliti, tajam, dapat penghargaan, tapi tidak objektif.
Apanya yang tidak objektif? Bahwa perusahaan raksasa itu selalu menyengsarakan rakyat? Bahwa kita tidak bisa lagi menunggu untuk beralih ke energi baru terbarukan , menghentikan laju deforestasi karena sebentar lagi bumi akan hancur karena bencana perubahan iklim? Hatinya geram, jiwanya berontak. Bukankah tugas utama jurnalis adalah menyampaikan kebenaran? Membela kaum yang lemah?
“Jadi apa sebenarnya kekeliruan saya Mas Wisnu dan Mbak Ati,” tanya Rina, ketika akhirnya ia dipersilahkan bicara.
“Saya tidak paham, mengapa tulisan saya dianggap tidak objektif. Saya mengutip berbagai sumber, bukan hanya masyarakat. Pihak perusahaan selalu saya hubungi, saya kutip,” suara Rina terdengar bergetar campuran antara marah dan sedih.
“Betul, tulisanmu lengkap. Tetapi framing yang kamu pilih Rina, adalah bahwa Pemerintah, bisnis, selalu salah. Dan itu berkali-kali, ini berdampak pada reputasi perusahaan,” jawab Wisnu.
Bagi Rina respon ini begitu kabur, apa artinya “berdampak pada perusahaan?”
Rina terus mencecar, tanpa bisa ditenangkan oleh Ati yang berhati lembut. Sampai akhirnya Wisnu menyerah dan dengan mengambil nafas panjang berkata:
“Bagaimanapun majalah kita ini adalah sebuah industri. Harus bisa berkolaborasi dengan semua pihak. Kamu juga tahu kan bahwa Titian hidup dari iklan. Iklan itu cuan, dan cuan tidak punya ideologi,”
“Bagian pemasaran menyampaikan bahwa beberapa perusahaan menarik iklannya karena tulisan kamu, dan juga karena…’’ Wisnu berhenti sebentar, memandang wajah Rina, editor muda kesayangannya itu, “Komunitas Earth Lover.”
Rina tersentak.
“Apa hubungannya Mas? Itu kan komunitas kami, karyawan, sebagai warga negara, tidak mewakili perusahaan? Karena kami sering demo, mendukung teman-teman aktivis lingkungan?,” tanya Rina bertubi-tubi.
Rina kembali terkejut ketika Wisnu dan Ati mengiyakan pertanyaannya.
“Kami dan pimpinan sudah berkali-kali menyampaikan bahwa Earth Lover tidak mewakili Titian. Tetapi karena penggerak dan anggotanya semua bekerja di Titian, mereka menganggap PT Media Nusantara Inti partisan,” jelas Ati
Badan Rina lemas, Earth Lover adalah bayinya. Kegiatan bersama komunitas, memilah sampah, bergabung dengan berbagai komunitas lainnya, termasuk Lembaga Swadaya Masyarakat lingkungana hidup untuk edukasi publik, ikut unjuk rasa, yang selam ini ia anggap sebagai hak asasinya yang hakiki, ternyata dianggap merugikan perusahaan.
Air mata Rina tidak terbendung lagi, ia memandang Ati dan Wisnu bergantian:
“ Tidak ada pilihan lagi buat saya Mas, Mbak? Harus pindah ke kriminal? Atau….?”
Ati memegang tangan Rina.
“Jangan berpikir ‘atau’ ya… terima saja dulu tugas ini,” ujar Ati lembut.
Rina ingin berteriak bahwa ia tidak mau, tidak sudi, bahwa ia lebih baik keluar dari Titian, bahwa ia akan membawa kasusnya ke Lembaga Baantuan Hukum. Tetapi wajah ibunya yang masih harus bekerja, menerima pesanan kue untuk membiayai rumah tangga, wajah adiknya yang akan lulus 1 semester lagi menahannya. Gajih Rina dari Titian sangat diperlukan. Ayah Karina entah kemana. Ia menghilang saat Karina berumur 12 tahun.
Dengan berat hati Ri berdiri, menganggukkaan kepala, menyalami Ati dan Wisnu. Ia minta ijin untuk kerja ½ hari. Ia perlu menenangkan diri. Rina bergegas menuju mejanya, ia perlu keluar sebentar, sendiri, menghirup kopi di kantin sebelah.
“Aku temenin ya mbak, sambil kita ngerancang acara kita dengan anak-anak Hijau Lestari,” kata Ina, reporter muda dengan nada manja.
Rina menggelengkan kepala. Segala tawaran dan pertanyaan, tidak ia hiraukan. Dengan wajah kusam dan mulut bungkam, Rina bergegas ke luar ruangan. Ia masih tidak mengerti mengapa ia dihukum. Rina bergabung dengan Titian karena ia percaya media massa adalah pilar penting dalam demokrasi. Media massa menjadi saluran aspirasi masyarakat. Tetapi ternyata ia keliru.
“Majalah kita adalah sebuah industri…,” seperti ucapan Wisnu tadi. Rupanya fakta pahit ini yang harus ia terima
Dapatkan reward khusus dengan mendukung The Writers.
List Reward dapat dilihat di: https://trakteer.id/the-writers/showcase.