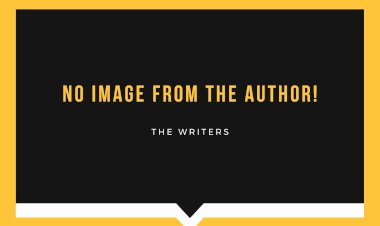TERLUNTA-LUNTA DI AMERIKA

“Hah? Kamu hamil? Nggak mungkin!!!” pekik Ernest dengan suara sangat panik.
Ernest adalah pacar saya sejak masih SMA. Saat itu saya dan dia sedang menuntut ilmu di Amerika. Kami berdua kuliah di sebuah College yang letaknya di selatan New York. Saya belajar Travel and Tourism, sedangkan Ernest belajar Business and Financial Administration.
Karena biaya hidup di Amerika terlalu mahal, kami sepakat untuk sharing apartemen 1 kamar agar biaya penginapan bisa patungan. Tadinya saya agak ragu-ragu tapi karena dia pacar saya dan karena sudah lama berpacaran, akhirnya desakan finansial membuat kami memutuskan untuk tinggal bersama.
Dan akhirnya yang saya takutkan pun terjadi. Saya hamil. Dan seperti yang telah saya perkirakan, Ernest sama sekali tidak siap untuk menghadapi kenyataan ini.
“Kamu yakin kalau kamu hamil, Yo?” tanya Ernest dengan suara parau.
“Iya, saya yakin. Sudah saya uji 3X pakai test pack, semuanya positif.”
Sejenak kami terdiam. Ernest menutup mukanya yang semakin memucat dengan kedua belah tangan.
“Huhuhuhu…..” Tiba-tiba dia menangis meraung-raung seperti anak kecil. Untuk menenangkan hatinya, saya hampiri dan peluk dia seerat mungkin. Akhirnya reda juga tangisnya. Dengan suara sesunggukan dia berusaha memulai percakapan kembali.
“Kok kamu bisa hamil, Yo?” Kepanikan yang teramat sangat membuatnya melemparkan pertanyaan bodoh.
“Menurut kamu kenapa?” tanya saya dengan suara lembut.
“Maksud saya, apa betul itu benih dari saya?” tanyanya lagi bertambah tolol.
“Kamu menuduh saya ML dengan orang lain?” Saya balik bertanya sambil mendorong tubuhnya dan menatap tajam kedua matanya.
Dia semakin panik, “Saya nggak tau. Yang saya tau, saya selalu keluarinnya di luar setiap kali kita ML,” teriaknya lalu menangis lagi.
“Lalu bagaimana? Maksud kamu tadi mau bilang apa?”
“Kamu jangan paksa saya bersikap harus bagaimana. Saya nggak tau harus bersikap apa! Jangan paksa saya!”
“Saya nggak maksa kamu apa-apa kok…”
“Saya nggak siap jadi suami, Yo. Kamu jangan menyudutkan saya.”
“Saya nggak bermaksud menyudutkan kamu…”
“Saya nggak siap jadi seorang Ayah…!!! Saya nggak siaaaap!!!”
Habis berkata begitu, Ernest berlari ke luar dan membanting pintu keras bukan main.
Saya cuma bisa menghela napas panjang. Kasihan Ernest, dia ternyata jauh lebih tidak siap daripada saya sendiri. Harus dipahami bahwa saat itu saya baru berusia 19 tahun, sedangkan Ernest 20 tahun. Siapa cowo yang siap menikah di umur segitu? Apalagi Ernest adalah satu-satunya anak lelaki di keluarganya. Dia juga anak tunggal. Kedua orangtuanya pasti mempunyai pengharapan besar pada masa depan puteranya ini.
Ernest tidak pulang ke apartemen selama tiga hari. Di kampus dia juga bolos, entah pergi ke mana. Saya telepon, HPnya tidak aktif. Saya text semuanya tidak terkirim. Ketika saya mulai terpikir untuk menelpon orangtuanya yang tinggal di Indonesia, tiba-tiba saya menerima text dari dia. Isinya, ‘Yoyo, nanti malam saya pulang. Kamu jangan ke mana-mana. Saya sudah punya solusi untuk menyelesaikan masalah kita.”
Menjelang jam 9 malam, Ernest pulang. Saya sudah menunggu di meja makan dan menghidangkan Thai food kesukaannya. Dia memeluk dan mencium saya lalu duduk di meja makan. “Apa kabar, Yo?”
“Saya baik-baik aja. Kamu?”
“Saya juga baik,” sahutnya sambil melirik ke arah perut saya.
Sejenak keheningan menyela.
“Begini Yo, saya kemarin ketemu sama Victor, temen saya yang dulu kuliah di Denver. Sekarang dia sudah tinggal di New York."
“Oh Victor. Iya saya inget sama dia.”
“Dia bersedia membantu kita untuk meminjami uang untuk aborsi kandungan kamu,” ucap Ernest.
Saya mendengarkan omongannya tanpa memberi reaksi apa-apa.
“Dan yang lebih bagus lagi, dia juga punya channel dokter kandungan yang mau melakukan aborsi ini. Bagus kan, Yo?”
“Oh, begitu?”
“Iya. Akhirnya masalah kita bisa terselesaikan.”
Belum lagi saya menyahut, Ernest memeluk saya. Walaupun badannya agak kurus, Ernest tingginya 176 cm. Jadi kalau dipeluk, kepala saya cuma sampai di lehernya.
“Kita bisa belajar dengan tenang seperti biasanya, Yo. Lain kali kita harus hati-hati kalo ML lagi,” katanya lagi.
Keheningan kembali menyela. Ernest terlihat lebih tenang, rupanya solusi tersebut merupakan jalan terbaik untuknya.
Setelah menghela napas panjang berkali-kali, saya berkata,”Ernest…”
“Ya, Yoyoku?” sahut Ernest sambil menggenggam tangan saya.
“Saya nggak mau aborsi. Saya mau memelihara anak ini.”
“Hah???!!! Maksud kamu bagaimana, Yo?” Persis seperti sebelumnya Ernest panik bukan main.
“Iya, saya mau melahirkan anak ini,” jawab saya tegas.
“Tapi saya nggak siap jadi suami, Yo!! Saya nggak siap jadi Ayah!!!” Suara Ernest kembali meninggi.
“Saya tau. Saya nggak menuntut kamu untuk menikahi saya. Kamu nggak usah kuatir.”
“Saya harus bagaimana, Yo? Apa kata Papa dan Mama saya kalau kamu nggak mau aborsi?”
"Kamu tenang dan dengerin saya dulu..."
"Kamu Cina, saya pribumi. Kamu Budha, saya Kristen. Kita banyak masalah, Yo."
"Kamu tenang dulu, bisa nggak?"
"Saya bisa dibunuh sama Papa dan Mama nanti."
“Papa sama Mama kamu nggak perlu tau kalo saya hamil,” jawab saya berusaha membuatnya tenang.
“Aduh, tolong saya, Yo. Saya harus gimana?”
“Kamu nggak harus gimana-gimana. Saya akan piara anak ini sendiri.”
“Tapi Yo… kalau anak ini lahir, orang juga akan tau kalau saya bapaknya?”
“Saya nggak akan bilang siapa-siapa kok.”
“Tapi saya nggak mungkin membiarkan kamu sendirian, Yo. Saya jadi jahat banget kedengarannya. Huhuhu….” Tangis Ernest kembali meledak. Saya peluk dia seerat mungkin. Ernest balas memeluk saya.
“Buat saya, kamu bukan orang jahat. Saya akan selalu sayang sama kamu,” bisik saya sambil mengecup ubun-ubunnya.
Makanan Thailand favorit kami, yang biasanya selalu kurang karena kami berdua selalu lahap memakannya, kini sama sekali tidak tersentuh. Saya dan Ernest tidak punya nafsu makan lagi. Kami berdua menghabiskan malam dengan berbaring di ranjang saling memunggungi dengan pikiran kusut di kepala masing-masing.
'Ya Tuhanku, berilah ketabahan untuk Ernestku ini. Berilah dia tambahan kekuatan. Saya sangat mencintai Ernest, Tuhanku. Tolonglah dia…' Saya terus berdoa dalam hati.
Karena sulit sekali untuk tidur, saya mencoba membaca untuk memancing kantuk. Buku yang saya pilih berjudul Fifty Shades of Grey, karangan E.L. James. Novel ini bercerita tentang Anastasia, seorang gadis innocent yang terjerat dalam kisah asmara dengan Christian Grey, seorang milyuner muda dan tampan. Ana tidak menyadari ternyata Christian mempunyai sisi kelam yang menyeramkan.
Novel ini sangat laris sehingga sudah dfilmkan dengan judul sama. Dibintangi oleh Dakota Johnson dan Jamie Dornan. Saya sudah nonton filmnya tapi rasanya film itu kalah bagus dari novelnya sendiri. Mungkin imajinasi saya lebih seru daripada kreator film tersebut.
Tepat pukul 12 malam, saya terbangun, lalu menyalakan hio. Sebagai umat Budha saya ingin minta ampun dan minta petunjuk atas cobaan yang sedang menyelimuti kami berdua. Sebenarnya saya jarang menyalakan hio karena tetangga sebelah beberapa kali terganggu oleh baunya. Bahkan pernah seseorang mengadu pada landlord yang tinggal di apartemen paling bawah. Saya sempat disemprot oleh landlord sembari mengancam akan mengusir keluar apartemen kalau kami menyalakan hio lagi.
Tapi kali ini adalah doa yang sangat krusial. Saya merasa perlu berdoa menyalakan hio di keheningan tengah malam yang sunyi. Semoga semua orang sudah tertidur lelap.
Sambil memegang hio yang menyala, saya berdiri di atas lutut, kemudian pai kui (menyembah) sebanyak 3X dan mulai berdoa,
”Aku berlindung kepada Namo Budhaya, Namo Dharmaya, Namo Sanghaya.”
Seraya memejamkan mata, saya lanjutkan, “Aku berlindung kepada Amitabha Budha/Namo Amitabha Budhaya/Namo Oh Mee Toh Fo.”
“Wahai Budha, aku bertekad untuk tidak melakukan perbuatan jahat dan bodoh lagi, karena sekecil apapun perbuatan jahat dan bodoh yang baru, pasti juga akan melahirkan penderitaanku yang baru.
Oh Budha, aku selalu mengharap, agar orang-orang yang berada dalam hidupku, terutama Ernest, semoga bisa hidup lebih beruntung dan bahagia. Semoga semuanya bisa hidup lebih tentram dan damai. Semoga semuanya dapat bersama-sama memasuki jalan yang benar, memasuki pintu kesucian Dharma, melenyapkan penderitaan dan sampai terlahir di Tanah Suci Surga Sukhavati.”
Esok paginya, kami sudah duduk kembali di meja makan sambil menikmati kopi dan croissant yang sudah dihangatkan dalam oven. Mata Ernest terlihat merah dan sembab, mungkin dia tidak bisa tidur nyenyak semalaman itu.
“Jadi rencana kamu bagaimana, Yo?” tanyanya membuka percakapan.
“Seperti yang saya katakan kemarin, saya nggak akan menyusahkan kamu.”
“Persisnya bagaimana, Yo?”
“Saya akan melahirkan anak ini. Jadi saya nggak mungkin tinggal sama kamu. Saya harus pergi dari sini.”
Ernest terdiam. Saya menghirup kopi sebelum terlanjur dingin.
“Kamu mau pulang ke Indonesia?” tanya dia lagi.
“Saya belum tau…”
“Kalau kamu pulang ke Indonesia, nanti orangtua kamu juga akan tau dong kalau itu anak saya?” katanya ketakutan.
Saya tersenyum mendengar kekuatirannya. Saya genggam tangannya yang ada di atas meja untuk membesarkan hatinya.
“Jangan kuatir. Saya akan pergi ke suatu tempat. Tapi yang pasti bukan ke Indonesia.”
“Jadi kamu mau ke mana, Yo?” Suara Ernest teramat lirih semakin mengikis hati saya.
“Nanti kalau saya sudah tau mau ke mana, saya akan kasih tau kamu.”
“Yo..”
“Ya, sayang…?”
“Saya bukannya nggak mau mengakui anak ini adalah anak saya….”
“Iya, saya ngerti. Kamu belajar aja yang rajin. Kamu harus menyelesaikan kuliah kamu,” kata saya sambil memeluk dan mencium pipi anak manis itu.
“Terus kamu mau ke mana, Yo? Tolong kasih tau saya…”
“Bagaimana saya mau kasih tau? Saya kan belum tau mau ke mana…”
“Yo…”
“Iya, sayang?”
“Kalau saya sudah mapan, sudah punya kerjaan, sudah punya uang sendiri, saya akan cari kamu…”
“Iya, saya percaya.”
“Saya akan mengatakan sendiri pada anak itu, bahwa saya ayahnya.”
“Iya, sayangku.”
“Saya nggak mau, kamu menganggap saya nggak bertanggung jawab dan nggak peduli sama anak kita.”
Tangan kami saling menggenggam erat. Dan Ernest menangis lagi. Saya tau dia merasa sangat bersalah karena tidak mampu menghadapi masalah ini bersama saya. Ah..kasihan sekali dia. Saya pun bangkit dan memeluk dia sepuasnya.
“Jangan nangis sayangku. Kamu harus kuat. Saya melakukan ini karena nggak mau jadi penghalang cita-cita kamu. Okay?”
Kepalanya yang menempel di buah dada saya terasa sedang mengangguk mengiyakan.
“Dan saya akan kecewa sekali kalau kuliah kamu nggak selesai. Jangan membuat kepergian saya sia-sia. Janji?”
Terasa kepalanya mengangguk lagi di balik sedu-sedannya.
Bulan depannya, sepulang kuliah, Ernest hanya menemukan apartemen kosong. Saya pergi diam-diam tanpa meninggalkan surat atau pesan apapun. Saya tau dia sedih. Saya tau dia sangat kebingungan. Saya tau dia belum kuat untuk mendapatkan cobaan sebesar ini. Tapi seiring dengan waktu, saya yakin pelan-pelan dia akan melupakan saya.
Dalam situasi seperti ini, orang lain tentu banyak yang menyalahkan Ernest sebagai orang yang tidak bertanggungjawab. Pasti ada yang bilang bahwa dia cowo pengecut yang mau enaknya sendiri. Orang lain boleh berpendapat apa saja yang jelek-jelek tentang Ernest. Tapi saya tidak!
Memang saya hamil, tapi apakah itu kesalahan Ernest semata? Bukan! Itu adalah kesalahan saya juga. Bukankah saya juga mau melakukannya. Ketika kami melakukannya bersama, maka tidak ada yang berperan sebagai pemangsa, dan tidak ada yang berfungsi sebagai korban. Apalagi tidak pernah ada komitmen bahwa kalau hamil dia harus menikahi saya? Pernikahan tidak akan berhasil apabila dilakukan atas keterpaksaan.
Buat saya persoalan ini cuma masalah pilihan. Ernest memilih aborsi sebagai penyelesaian masalah. Sedangkan saya memilih untuk melahirkan dan memelihara jabang bayi ini. Pilihan saya berbeda dengan pilihan Ernest, karena itu tidak adil kalau saya memaksa dia untuk bersama menjalani pilihan saya tersebut.
Saya mencintai Ernest dan saya ingin dia berbahagia.Karena itulah saya memutuskan untuk menghadapi masalah ini sendiri. Saya paling tidak suka mengetahui ada orang menderita dan ternyata saya adalah bagian dari penyebab penderitaannya itu. Ada pepatah Cina yang mengatakan ‘Kalau kamu tidak bisa membahagiakan orang lain, minimal jangan pernah menyusahkan orang lain.’
Bersambung ke Episode 2
Dapatkan reward khusus dengan mendukung The Writers.
List Reward dapat dilihat di: https://trakteer.id/the-writers/showcase.