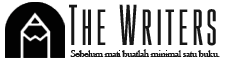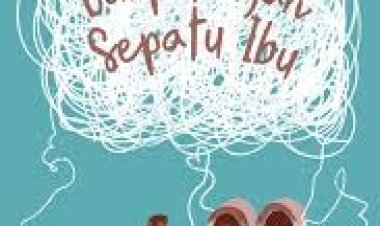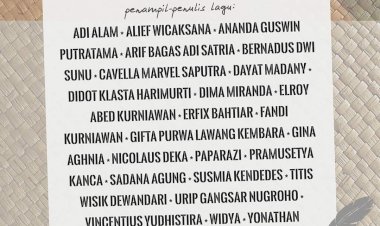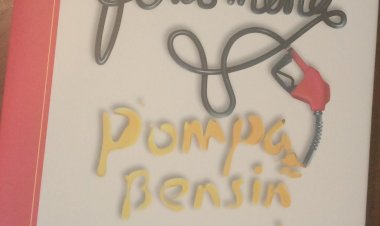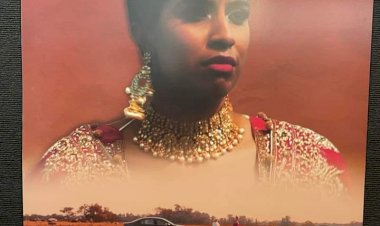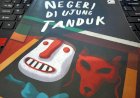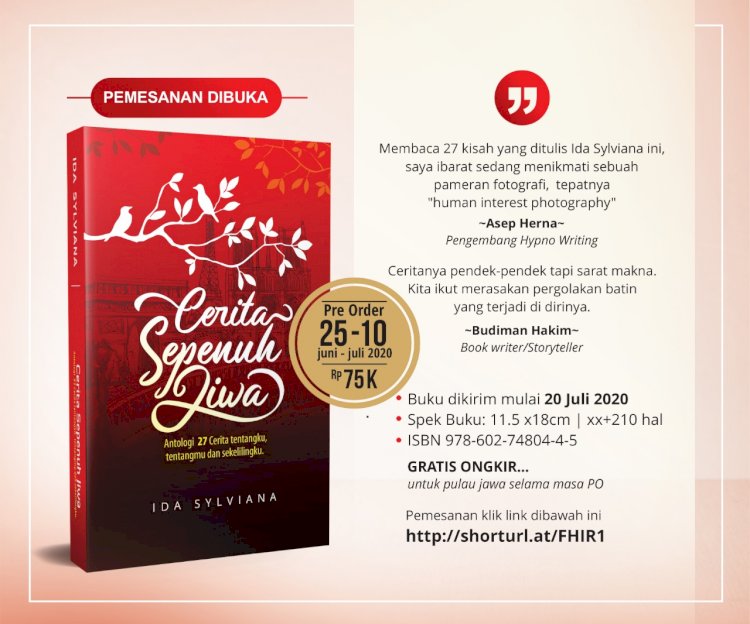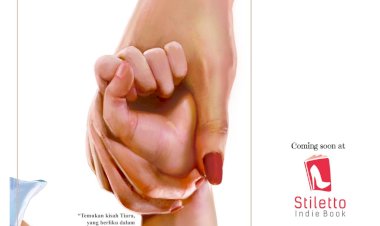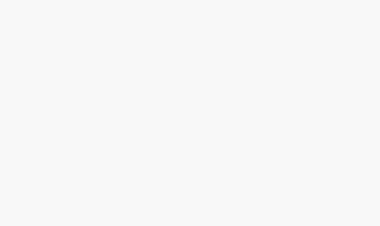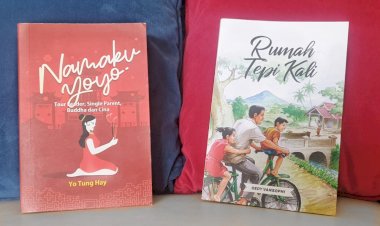"Sudah baca buku ini?" temanku Luwi menyodorkan sebentuk buku padaku, yang kusambut dengan sumringah.
Buku itu kecil saja, berukuran 18×13,3 cm. Di pojok kanan atas sampulnya tercetak harganya, Rp. 9,25. Itu harga lama tentunya. Harga kekiniannya, yang harus dibayar seseorang untuk memperoleh buku itu, terbilang tak murah. Sebab, buku ini sudah masuk ke dalam kategori buku antik. Buku untuk koleksi, bukan sekedar buku untuk dibaca senang-senang belaka. Warnanya kecoklatan, kuyakini karena dimakan usia. Kemungkinan besar warnanya semula adalah putih.
Buku mungil tersebut adalah buku karya sastrawan besar Indonesia Sitor Situmorang (1924-2014), yang juga dikenal sebagai seorang wartawan. Merupakan sebentuk buku kumpulan cerpen, berjudul Pertempuran dan Saldju di Paris - Enam Cerita Pendek. Diterbitkan oleh PT Pustaka Rakjat, Djakarta (sekarang: Jakarta), 1956. Setebal 100 halaman. Tercatat dari sumber lain bahwa, buku ini pernah mendapat penghargaan Hadiah Sastra Nasional BMKN 1955/1956 –BMKN adalah singkatan dari Badan Musyawarah Kebudayaan Nasional.
Berhubung diterbitkan pada 1956, tak heran apabila buku ini masih memakai ejaan lama. Sebagai contoh, kata 'yang' tertulis sebagai 'jang, dan 'cerita' sebagai 'tjerita'. J yang ditulis Y serta C ditulis TJ adalah ejaan yang baru berlaku di negara kita pada 1972. Disebut sebagai Ejaan yang Disempurnakan (EYD), pemakaiannya diresmikan pada 16 Agustus 1972.
Ejaan yang dipakai oleh buku ini sendiri dikenal sebagai Ejaan Soewandi, diperkenalkan pada 1947. Pada ejaan ini, huruf U sudah tidak lagi ditulis sebagai OE seperti dalam Bahasa Belanda.
Untuk generasi kelahiran sesudah 1972, membaca ejaan dalam buku ini pasti akan bingung. Saya yang pernah mengalami hidup dalam Ejaan Soewandi pun kadang tersendat kagok. Tapi, bagi saya, mendapat kesempatan untuk membaca buku langka ini merupakan sebuah pengalaman yang sangat tak terlupakan.
Saya belum pernah membaca maupun mendengar pembahasan mengenai buku ini, ataupun tentang cerita-cerita di dalamnya. Kemungkinan, karena saya belum atau tidak mencarinya secara lebih mendalam. Maka, saya menduga saja bahwa, semua cerita dalam buku ini merupakan pengejawantahan dari pengalaman-pengalaman pribadi si penulis sendiri, dan tentang legenda atau mitos yang pernah didengarnya di kampung halamannya.
Cerpen pertama dalam buku ini berjudul Pertempuran. Saat membacanya, dengan mudah kita dapat mengetahui bahwa kisah ini mengambil latar belakang masa ketika NKRI baru saja merdeka. Dari nama-nama sejumlah tokoh, kejadian awal cerita tampaknya berlangsung di sebuah tempat di daerah Tapanuli, Sumatra Utara. Menjelang akhir cerita, adegan pindah ke ibu kota, tepatnya di daerah Senen, Jakarta Pusat.
Membaca bagian terakhir yang berlokasi di seputaran Senin, cukup mengingatkanku akan cerita-cerita Mochtar Lubis dalam buku-bukunya, yang banyak memaparkan situasi Jakarta pada masa awal kemerdekaan. Mungkin, sebabnya karena dua sastrawan besar ini, baik Sitor Situmorang maupun Mochtar Lubis, berasal dari masa yang lebih kurang sama –selain sama-sama merupakan wartawan, serta sama-sama berdarah Batak.
Selain itu, bagian ini telah menambah pemahamanku akan daerah Senen sehingga menjadi sedikit lebih tebal. Senen adalah suatu daerah di pusat Jakarta, yang pada satu masa bagai dikuasai oleh kelompok etnis tertentu. Di mana untuk bertahan hidup mereka memakai prinsip “yang kuat yang menang”, dan cenderung memakai kekerasan untuk berhasil.
Satu hal lagi tentang daerah Senen, aku pernah mendapat kabar bahwa daerah tersebut pernah menjadi tempat berkumpulnya seniman, wartawan, dan sastrawan. Konon, Harmoko yang penah menjadi Menteri Penerangan di era orde baru, di masa mudanya adalah salah satu dari seniman yang rajin nongkrong di situ –kalau tak salah beliau dulu adalah seniman gambar karikatur. Mungkin saja Sitor Situmorang pun demikian adanya.
Cerita kedua dalam buku ini berhudul Harimau Tua. Ini kisah tentang seorang laki-laki berumur, yang nyaris di seluruh hidupnya membawa dendam untuk memusnahkan mahluk hidup lainnya –dalam hal ini binatang. Suatu cara baginya untuk bertahan hidup di alam liar yang keras dan buas. Tapi juga, menurut pendapat saya, cerita klasik tentang manusia yang menganggap binatang memang saingan yang layak dimusnahkan.
Kisah dalam cerita ini dituturkan oleh sosok lain, yang khusus datang ke tempat itu. Namun, sampai cerita selesai, tak ketahuan apa tujuan ia datang ke sana.
Salju di Paris dan Fontenay aux Roses adalah dua cerita tentang romantika kehidupan seorang laki-laki Indonesia di Prancis. Dengan sentuhan kisah romansa bersama lawan jenis yang dikenalnya di sana. Bahwa dia adalah seorang laki-laki Indonesia, lagi-lagi hanya dugaanku belaka. Dugaan saya yang lebih jauh adalah, lelaki itu adalah si penulis sendiri, Sitor Situmorang sendiri, yang sejak masa mudanya sudah hidup di Prancis. Dengan demikian, mudah bagi saya untuk menduga bahwa cerita-cerita ini adalah pengalaman pribadinya.
Cerita kelima berjudul Djin, yang kalau dalam ejaan sekarang adalah Jin. Kisahnya bersangkutan dengan legenda mistis di sebuah daerah, yang kemungkinan besar adalah daerah asal si penulis. Latar belakang masa atau waktu sepertinya adalah ketika Indonesia masih berada di jaman pendudukan Belanda. Karena, ada sekilas disebutkan nama ibu kota negara saat itu adalah Batavia.
Terakhir, ceritanya berjudul Ibu Pergi Kesorga –penulisan sekarang: Ibu Pergi ke Sorga. Sebagaimana yang tersirat dari judulnya, ini adalah suatu drama keluarga. Latar belakang waktunya setelah kemerdekaan, dengan ibu kota negara yang sudah bernama Djakarta (Jakarta).
Nama Sitor Situmorang buat saya adalah nama yang besar, seorang sastrawan terkemuka. Meskipun demikian, saya sebelumnya belum pernah mengenal karya-karyanya. Membaca cerita-cerita dalam buku ini, merupakan pengalaman pertama saya bersentuhan dengan karya-karya beliau.
Awal membacanya, seperti yang sudah sempat saya singgung di atas, agak tersendat. Bukan saja karena ejaannya adalah ejaan lama, melainkan juga karena gaya bahasanya yang juga gaya lama. Beberapa kali saya sempat salah menangkap tulisan kata ‘saja’, sampai-sampai tak mengerti dengan maksud yang hendak disampaikan oleh sang penulis. Sampai saya sadar bahwa seharusnya saya membacanya sebagai ‘saya’. Separuh buku berjalan, akhirnya saya pun menjadi terbiasa dan lebih lancar membacanya.
Adalah sebuah berkah bahwa saya bisa mendapat kesempatan membaca karya dalam buku langka ini. Untuk itu, terima kasihku pada semesta. Salam damai untuk Bapak Sitor Situmorang. Requiescat in pace. =^.^=