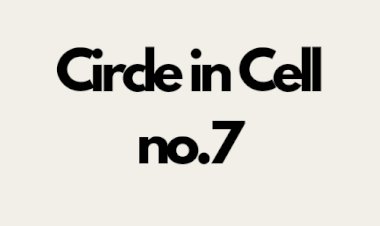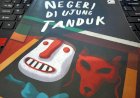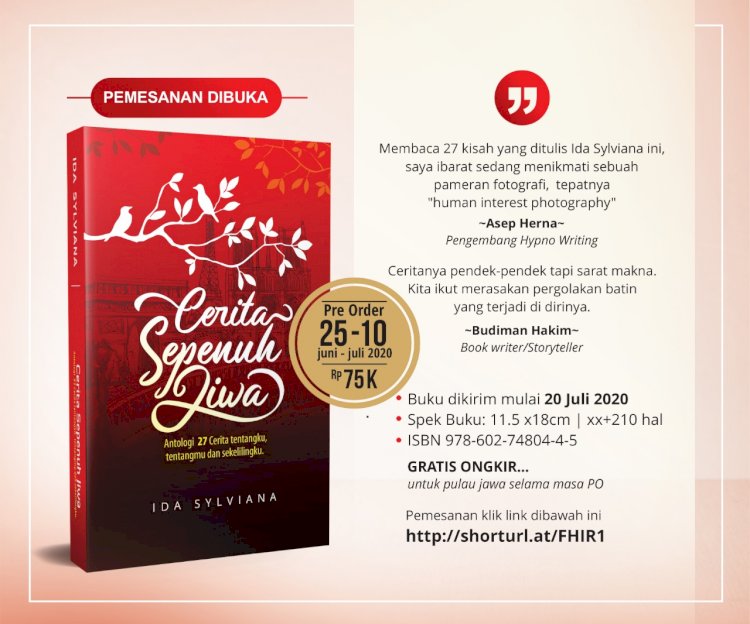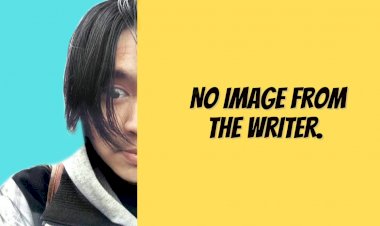Menangani Konflik Komunikasi Virtual dengan Psikologi Komunikasi untuk Generasi Z
Pandemi COVID-19 membuat aktivitas lebih banyak dilakukan lewat media sosial, tetapi begitu banyak pula konflik yang terjadi dalam aktivitas komunikasi virtual di media sosial. Konflik-konflik ini dapat ditangani dengan penerapan psikologi komunikasi yang tepat loh. Bagaimana ulasannya? Yuk, simak artikel di bawah ini. Selamat Membaca!
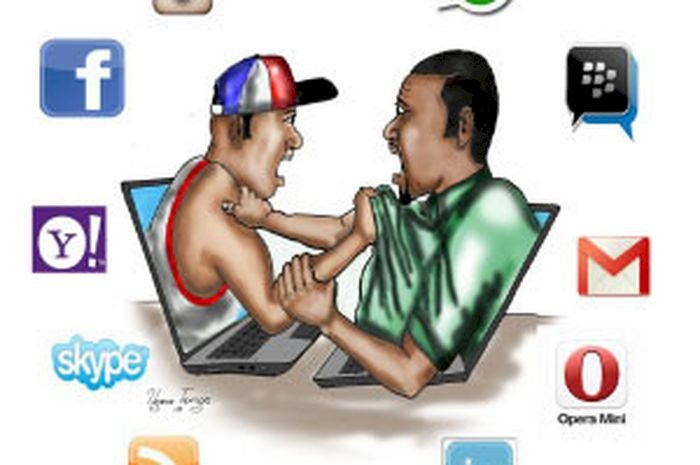
 |
| Sumber: gmedia.net.id |
Pandemi COVID-19 di Indonesia sudah berjalan 10 bulan lamanya, selama masa pandemi ini secara tidak langsung mengubah perilaku masyarakat dalam berkomunikasi. Pemerintah hingga saat ini telah menerapkan perpanjangan masa Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) untuk jangka waktu yang belum diketahui. Salah satu perilaku yang nampak adalah meningkatnya konsumsi penggunaan media sosial. Dilansir dari katadata.co.id pengguna media sosial khususnya Instagram dan WhatsApp menunjukkan peningkatan yang sangat drastis. Facebook menunjukkan data bahwa pengguna WhatsApp naik 50-51% dan juga terjadi pada Instagram dimana kenaikan pengguna mencapai 40%, total aktivitas kirim pesan pada kedua platform digital tersebut juga menunjukkan angka kenaikan lebih dari 50%. Selain itu, postingan pengguna di Instagram story meningkat 15% setiap harinya, jumlah pengguna yang melihat story pengguna lainnya juga ikut meningkat sebesar 21%. Faktor yang melatarbelakanginya adalah semenjak diberlakukannya aturan social distancing dan Work From Home yang memaksa masyarakat lebih banyak beraktivitas dari rumah termasuk untuk berinteraksi dengan orang-orang terdekat, maka tidak mengherankan untuk memenuhi kebutuhan hubungan sosial inilah membuat media sosial dipilih sebagai cara yang termudah dan paling cepat untuk tetap keep in touch. Namun, kegiatan untuk beraktivitas di luar yang terbatas inilah lambat laun juga menyebabkan kontrol diri seseorang menjadi kurang terkendali, peran orang terdekat (significant others) kurang berperan dalam memberikan pembekalan literasi media terkait penggunaan media sosial yang bijak serta kurangnya pengetahuan sebagai dampak yang diperoleh secara psikologi bagi pelaku ataupun pengguna akun media sosial.
Akibat intensitas penggunaan media sosial yang tinggi yang mana pengguna mayoritasnya adalah generasi z, maka konflik komunikasi virtual yang terjadi di media sosial tak terhindarkan. Mengapa demikian? Karena karakteristik generasi Z dalam menerima, mengelola dan mengintepretasikan informasi dari eksternal terhadap dirinya memiliki kecenderungan cuek terhadap apa yang dilontarkan (tidak berpikir matang untuk dampak kedepannya), ingin mendapat pengakuan dalam suatu situasi komunikasi, ingin selalu terhubung dengan media sosial agar dianggap selalu up to date, dan senang melakukan komunikasi terbuka (debat). Kecenderungan inilah yang membuat konflik komunikasi virtual di media sosial sangat mudah untuk terjadi.
 |
| Sumber: idntimes.com |
Konflik komunikasi virtual yang terjadi di media sosial jika dilihat dari pendekatan psikologisnya merupakan bagian dari ciri-ciri generasi remaja itu sendiri yaitu labil, berorientasi pada diri sendiri, tidak logis dalam membuat keputusan, pemberontak, dan emosional. Kondisi kepribadian tersebut sedikit banyak mempengaruhi mereka dalam melakukan komunikasi virtual di media sosial. Selain itu, penyebab lain munculnya fenomena tersebut adalah karena terpancing oleh hal-hal berbau ujaran kebencian (hate speech), informasi hoax, dan hal-hal sejenis lainnya yang membuat mereka menjadi terbiasa untuk mengkritik, berkomentar bebas berdasarkan kebenaran pribadi, dan berlomba dianggap menjadi yang paling pintar di media sosial.
Proses komunikasi virtual yang cenderung menggunakan ujaran kebencian (hate speech) dan ke arah bad comment inilah sekaligus mencerminkan adanya sesuatu yang salah dalam proses pengungkapan diri (self-disclosure) dan kontrol diri (self-control) yang dilakukan. Pengungkapan diri (self-disclosure) menurut Wrightsman (1987) merupakan proses menghadirkan diri yang diwujudkan dalam kegiatan membagi perasaan dan informasi bersama orang lain. Sedangkan, kontrol diri (self-control) adalah salah satu faktor dari dalam diri manusia yang sangat penting untuk digunakan dalam mengendalikan perilaku agar tidak merugikan diri sendiri dan orang lain
Tahukah kalian bahwa kebiasaan diri dalam memberikan respon yang terkait dengan beragam ungkapan kebencian atau sarkas ketika memberikan komentar di kolom comment kepada pemilik akun dapat berdampak secara psikologi loh. Pertama, dapat menimbulkan low self-esteem. Mengapa demikian? Berbagai komentar negatif yang muncul secara terus menerus dalam waktu yang lama akan menjadi “bom waktu” yang siap meledak dan membuat rasa percaya diri menurun bagi pengguna akun tersebut. Kedua, meningkatnya kecemasan diri (self-anxiety) sehingga akan berakhir dengan depresi, dimana seseorang yang sudah terlalu banyak menerima serangan hate speech dapat memengaruhi emosi dirinya seperti merasa gelisah, sedih, dan overthinking. Apabila, kondisi diri ini meningkat hingga depresi maka seseorang akan kehilangan akal sehatnya dan akan menempuh jalan pintas sebagai solusi yang dipilihnya.
 |
| Sumber: saint.trunojoyo.ac.id |
Kemudian, bagaimana dari sudut pandang pelaku yang melakukan hate speech? Pertama, saat ini sudah terdapat UU ITE yang mengatur tentang komunikasi di dunia maya yang diatur dalam pasal 27 ayat 3, orang yang melanggar pasal tersebut akan dipenjara dengan masa kurungan 4 tahun dan/atau denda sebesar Rp750.000 sesuai yang diatur dalam pasal 45 ayat 3 UU 19 tahun 2016. Selain pasal 27 ayat 3, terdapat pula pasal 28 ayat 2 UU ITE dimana orang yang melakukan pelanggaran terhadap pasal tersebut dapat dikenakan sanksi berupa hukuman penjara selama 6 tahun dan/atau denda sebesar Rp1.000.000.000 sesuai yang diatur dalam pasal 45A ayat 2 UU 19 tahun 2016. Akibat dari pelanggaran ini bukan hanya sebatas berakhir di penjara atau membayar denda, tetapi pelaku yang sudah pernah tercatat dalam catatan kepolisian secara tidak langsung kehidupan masa depannya juga akan ikut terkena imbasnya, seperti akan sulit mendapatkan pekerjaan yang layak karena statusnya pernah berurusan dengan hukum pidana, dikucilkan dari lingkungan sosial, sulit mendapatkan kepercayaan dari orang terdekat dan masyarakat. Kedua, konsekuensi diri akibat kebiasaan buruk tersebut adalah sifat adiktif yang mana akan menganggap perilaku yang dilakukan oleh dirinya merupakan sesuatu yang wajar saja. Ketiga, membentuk self-image (citra diri) yang buruk pada dirinya. Inilah yang terpenting dalam proses pembentukan diri kita. Apabila kita ingin digambarkan sebagai kepribadian yang menyenangkan akan tetapi tidak selaras dengan perilaku dalam berkomunikasi dan bersikap, maka gambaran diri yang ingin kita bentuk dan dinilai oleh orang lain tidak akan terwujud. Oleh karena itu, saat menggunakan media sosial pun diperlukan etika berkomunikasi virtual sebab suatu persepsi dapat dibentuk secara bebas oleh orang lain pada diri kita dan kita tidak dapat membendungnya, karena yang hanya dapat kita kendalikan adalah self-control atas diri kita sendiri.
Berkaca dari berbagai impact yang dapat terjadi baik untuk diri sendiri (pelaku) dan orang lain (objek) maka itulah alasan mengapa kontrol diri sangat penting dalam aktivitas komunikasi virtual di media sosial. Berikut adalah beberapa cara yang dapat kita lakukan bersama untuk mencegah terjadinya konflik di komunikasi virtual. Pertama, apakah kalian tahu hubungan kausalitas (sebab-akibat)? Ternyata membentuk suatu komunikasi virtual yang baik juga erat berkaitan dengan hubungan sebab-akibat, maksudnya adalah jika kita menstimulan otak kita untuk memiliki pandangan dan perasaan positif terhadap suatu kejadian di media sosial, maka pola perilaku komunikasi yang akan muncul juga akan ikut positif sehingga tidak ada lagi penggunaan hate speech (ujaran kebencian). Kedua, kemampuan literasi media juga tidak kalah penting, karena munculnya konflik juga dapat diawali oleh adanya berita atau informasi hoax yang tersebar di media sosial. Dengan memiliki tingkat kewaspadaan literasi media yang baik dan kritis sudah dapat menjadi salah satu tindakan preventif untuk meminimalisir terjadinya konflik di media sosial. Ketiga, memaksimalkan peran orang terdekat (significant others) untuk memberikan semacam boundaries terhadap hal-hal yang seharusnya tidak dilontarkan dimana bisa memicu konflik. Oleh karena itu, apabila ditinjau dari psikologi komunikasinya dimana generasi Z merupakan generasi yang lebih menyukai komunikasi terbuka sehingga pendekatannya seharusnya dilakukan dengan melibatkan mereka dalam diskusi yang sifatnya terbuka dan membangun. Lalu, komunikasi terbuka juga akan meningkatkan self-esteem dan self-efficacy-nya menjadi positif, karena mereka akan merasa keberadaan dirinya dihargai apabila suara mereka didengarkan.
 |
| Sumber: lifestyle.okezone.com |
Dapatkan reward khusus dengan mendukung The Writers.
List Reward dapat dilihat di: https://trakteer.id/the-writers/showcase.
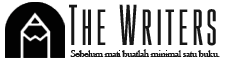
 Gabriel Bias Christiadi Limantara
Gabriel Bias Christiadi Limantara