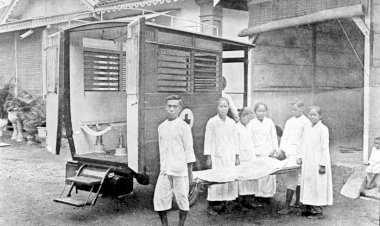Another Day with A New Start

“Lu tahu, gue juga pernah depresi waktu dulu kuliah di Kanada,” ungkap Ivan saat mengantarku kembali ke kosan.
“Gimana ceritanya?” Tanyaku.
“Ya ga tahu, dari SMA kita yang terbaik se Indonesia, pasti songong begitu masuk kuliah kan? Fisika, Matematika, semua berasa bisa. Lu juga pasti berasa gitu dulu,” lanjutnya.
“Ya ya.. Terus kok bisa depresi?” Aku terus berusaha mendengarkan sambil GoCar itu terus melaju di tengah pekatnya malam Jakarta.
“Nah, ada beberapa bulan setelahnya, tiba-tiba saja semua kuliah itu jadi tidak bisa. Tambah lagi kampus mensyaratkan nilai harus di atas D. Jika ada lima saja yang D atau E, maka langsung diwajibkan mengambil cuti kuliah dan terapi. Bodohnya, malah gue abaikan.” Ivan terus bercerita tentang masa lalunya dengan mata terus menerawang ke arah langit-langit mobil.
“Mirip ya, pengalaman kita. Terus lu ngapain?” Aku semakin memburu jawabannya.
“Gue malah pindah jurusan, menyangka kuliah di sana lebih mudah. Tapi ya sama saja. Namanya depresi, sudah pelajaran yang paling gampang pun ga bisa. Sampai akhirnya, orangtua dipanggil, diminta konseling.”
“Apa kata orangtua lu saat konseling?”
“Nah itu dia, sialnya bokap malah cerita kekhawatirannya bahwa depresi gue akan berlanjut ke niat bunuh diri. Sudah, selesai semua. Secara halus kampus mengeluarkan gue karena ga mungkin menerima resiko ada kejadian bunuh diri. Drop out lah sudah,” sambungnya lagi.
Itulah yang mendasari keputusan Ivan meninggalkan masa depannya yang cemerlang di Kanada. Padahal ia sebelumnya menolak masuk ke Matematika ITB yang waktu itu juga jadi incaran banyak siswa di sekolah kami.
“Tapi gue masih bersyukur ya. Ngeliat nasib elo, kayanya masih mendingan gue masih sempat masuk lagi ke kampus swasta sini dan masih bisa melanjutkan impian jadi engineer kelistrikan. Walaupun swasta sih, dan itu pun sampai bolak-balik ke psikiater termahal se Indonesia. Sekali berobat habis Rp 800 ribu, belum terapi lain-lainnya,” Ivan mengenang kembali pengalamannya dua puluhan tahun lalu.
“Bangsat, hahaha. Temen macam apa lo malah bersyukur liat nasib temannya sendiri jelek.” Aku setengah mengumpat. Tentu saja dengan niat bercanda dan menertawakan diri sendiri.
“Tapi serius, gue paling ga tahan lihat orang-orang seperti elu. Yang sudah berjuang melawan dirinya sendiri, berusaha bantu orang-orang yang senasib, tapi malah ga dapat dukungan dari orang sekitar. Adanya direndahkan dan kondisi lu malah dimanfaatkan habis-habisan. Itu kenapa gue berdiri paling depan untuk nyelamatin. Gue sedikit banyak bisa tahu rasanya, bro,” katanya dengan muka miris.
“Ya baguslah, berarti gue masih punya sahabat, walaupun sama-sama ngaconya kan? Hahaha.”
Kami terdiam lama.
“Sekarang ini gue khawatir nasib lu mirip Minke. Tahu kan?”
“Minke di Trilogi Pulau Burunya Pram?” Tanyaku balik.
Minke adalah orang yang juga berjuang untuk dirinya sendiri, orang-orang yang dia cintai., bahkan untuk seisi Indonesia, saat bangsa ini masih terpecah-pecah menjadi berbagai suku. Ialah yang mendorong perjuangan atas nama satu bangsa saja. Namun perjuangannya yang gigih berujung kehilangan cinta sejatinya, dimurkai bapaknya, disisihkan dalam pertemanan, dikhianati, dimusuhi, dan akhirnya meninggal dalam keadaan kesepian, sakit-sakitan.
“Bagusnya gue ga baca semua serinya sampai tamat, jadi ga perlu khawatir sejauh itu. Cukup sampai ‘Anak Semua Bangsa’ aja.” Lanjutku lagi memecah keheningan.
“Kenapa begitu?” Cecar Ivan.
“Entah ya, cerita Trilogi itu terlalu mendayu-dayu dan cengeng. Gue ga suka. Lebih bagus baca kumpulan cerpennya Pram. Andai pun gue jadi sosok Minke, cukup sampai perjuangan gagahnya melawan diskriminasi terhadap pribumi saja. Ujungnya nasib gue jadi Minke atau siapapun, ga ada yang tahu, kan?””
“Tapi sedih kan, dia tidak jadi siapa-siapa? Banyak tokoh dan pahlawan kemerdekaan lainnya yang lebih dikenal. Itu pun kita kenal sosoknya setelah ditulis Pram kan?”
“Maksudnya sosok aslinya, Raden Tirto? Kan ujungnya diakui juga jadi Bapak Pers Nasional. Not bad lah,” sanggahku.
“Tapi ingat itu karena ada Pram. Siapa yang bisa jamin setelah lu mati nanti akan ada yang menjalankan peran Pram buat lu?” Ivan setengah mengejek, setengah miris.
“Ya ga apa apa. Itulah purpose dalam hidup. Kita kejar apapun risikonya. Hidup kita toh cuma sekali, sudah itu mati. Buat gue perjuangan terbaik ada di jalan sunyi,” jawabku dengan tegas.
“Sumpah, gue ga pernah nemu orang setambeng lu,” Ivan tertawa-tawa. Tanpa sadar mobil itu sudah sampai di depan kosan.
“Tapi lu jangan kaget liat isi kamar gue ya,” Aku memperingatkan saat membuka pintu. Ivan langsung beristighfar. Kamar itu sudah berjamur, berantakan, dan berbau tak enak.
“Baunya ngingetin masa-masa gue di Kanada dulu. Persis begini, khas penghuni yang sedang depresi,” komentarnya saat pintu itu terbuka lebar.
“Waktu itu siapa yang bantu jagain lu?”
“Ya kita sistemnya kan ada roommate, bukan kos sendirian. Dia yang bantu ngasih gue caregiving, bersih-bersih, ngingetin makan, mandi, sampai akhirnya orangtua gue datang. Di sana awareness mengenai depresi lebih baik, ga kaya di sini udah tahu orang depresi malah tambah diisolasi dan diinjek,” jawabnya.
Malam makin larut saat kami terus berbincang-bincang di teras sebelah kosan hingga berjam-jam lamanya. Ivan menolak dengan halus minum kopi yang kusodorkan. Maag, katanya.
“Ude lu beresin dulu aja itu kamar,” sarannya. Aku mengiyakan.
“Biasanya ada pembantu juga. Tapi berhubung gue udah ga nempatin kamar ini beberapa bulan, jadinya ga pernah dibuka, apalagi dibersihin. Besok minta si Ibu bantu lagi,” kataku menerangkan. .
Ivan kemudian pamit untuk pulang. Ia berpesan untuk tetap menjaga kondisi diri dan terus bertemu banyak orang agar tidak lagi dikuasai depresi yang membuat keinginanku mengakhiri hidup muncul lagi.
“Kalau ga memungkinkan untuk pindah ke kosan yang lebih ramai, minimal lu ajak ketemuan teman-teman ke sini. Makan bareng.”
“Beres, lu juga datang aja, nanti gw masakin. Gue hobi masak kok,” janjiku.
“Anjrit, cewe gue dulu aja seumur-umur ga pernah masakin gue. Ini dimasakin cowo. Ogah!” jawabnya sambil tertawa-tawa.
“Eh jangan salah. Emang sekarang udah ga zamannya kali cewe masakin cowo. Cowo justru kelihatan lebih keren di mata cewe kalau bisa masak. Hahaha!” Sanggahku setengah bercanda.
“Ya baguslah, ada masanya lu akhiri kesendirian ini. Cari pasangan lagi. Ga baik terus-terusan kaya gini,”sarannya lagi.
“Entahlah, sekarang sih ga merasa ada minat apapun sama cewe. Gue susah jatuh cinta, dan cewe pun ga bakalan mau kan hidup sama cowo yang belum beres dengan dirinya sendiri? Mending gue cari duit yang banyak dulu. Jadi high quality jomblo hahaha.”
“Caranya?” Tanya Ivan tak yakin.
“Ya ini ada kopi luwak. Gue yakin ini blessing dari Tuhan. Caranya menjawab permintaan gue untuk bisa menyembuhkan diri sendiri sambil bantu orang-orang yang juga kesusahan saat pandemi ini. Angka bunuh diri saat pandemi kan naik tajam. Gue rasa gue bisa berbuat sesuatu,” jawabku berusaha optimis.
“Lu yakin itu bisa laku? Mahal gitu, emang ada yang mau beli?”
“Baru cerita-cerita doang di medsos aja udah berebut pesan kok. Dan karena sudah nanganin tiga tahun, pembeli loyalnya sebenarnya sudah ada. Tinggal dikemas dengan bagus aja. Dulu tanpa label pun banyak yang setia mesan. Apalagi udah gw kemas dengan edukasi soal depresi kan? Jadi banyak manfaatnya ketimbang sekedar ngejar profit.” Aku berusaha meyakinkannya.
“Terserah lu dah, Pak. Ya udah hati-hati ya. Take care,” katanya sambil melambaikan tangan, membuka pintu GoCar yang sudah menjemput.
Aku kembali ke kamar, membersihkan apapun yang masih bisa dibersihkan dengan tenaga yang masih tersisa. Debu di lantai sudah menumpuk terlalu banyak dan jamur tumbuh di mana-mana. Pandanganku kemudian tertumbuk ke sebuah lukisan yang kubuat tiga bulan lalu. Masa-masa depresi sudah menguasai seluruh kehidupanku sehingga panik mencari pertolongan ke sana ke mari.
Kufoto lukisan itu dan menulis captionnya di Facebook, “Another day with a new start... New battle.”
=====
Cerita ini bagian dari Ebook #CoffeeDepresso: The Stories yang merupakan lanjutan dari Ebook #CoffeeDepresso seri pertama. Tulisan-tulisan saya bisa jadi menjadi trigger dan stressor bagi penderita depresi. Bagi yang merasa dirinya depresi atau sudah terdiagnosa depresi, harap tidak membaca tulisan-tulisan ini sendirian.
Buku #CoffeeDepresso edisi pertama bisa didownload di http://bit.ly/ebookdepresso.
Cerita ini adalah fiksi yang berdasarkan pengalaman saya di kehidupan nyata. Tidak ada kesamaan dengan nama orang, tempat, dan peristiwa yang ada di dalamnya dengan kejadian di dunia nyata.
Dapatkan reward khusus dengan mendukung The Writers.
List Reward dapat dilihat di: https://trakteer.id/the-writers/showcase.