Rangkui

Sore itu, dari jendela kamar hotelku di lantai 5, Sungai Rangkui kami terlihat seperti comberan. Airnya keruh, berwarna entah coklat entah hitam. Dilatarbelakangi langit merah senja dan bayangan samar bukit Mangkol di ujung barat sana, Rangkui semakin terlihat kumuh, suram, dan merana.
Mesjid Jami' dengan 4 menaranya yang menjulang gagah, sepertinya sudah tak hirau lagi dengan sungai yang setia menemaninya sejak lebih dari 87 tahun silam. Mesjid Jami' tetap terawat dan terus bersolek. Sementara Rangkui dibiarkan merenta. Tak terbayang kalau dulu sungai ini pernah begitu bersih dan jernih, menjadi sumber air minum dan tempat masyarakat kota kami mandi dan mencuci pakaian sehari-hari.
Kutelpon Afendi, Pendi panggilannya, kawan sepermainan masa kecilku. “Pen, aku ada di sini.” Ia terkejut dan sedikit protes, karena sebelumnya aku tak mengabarkan kepulanganku. Tapi segera kupotong omelannya. “Besok temani aku Subuh di Mesjid Jami' ya. Setelah itu kita jalan kaki menyusuri sungai Rangkui lalu cari sarapan di Pasar Pagi.”
Pendi tertawa. “Mau nanggok apa di Rangkui? Sampah plastik? Ikan udang lah mati mabok racun. Tapi dak masalah, kalau orang Jakarta nak bernostalgia mengenang masa kecil. Besok aku jemput jam 4.15 ya.”
Ucapan Pendi membuatku semakin terkenang dengan berbagai kisah yang mengikatkan kami pada Rangkui. Masa-masa yang hanya dipenuhi suka cita. Tak ada yang kami risaukan. Setiap memulai hari, yang kami pikirkan hanyalah permainan apa lagi yang akan kami lakukan sepulang sekolah siang nanti.
Musim penghujan tak menyurutkan hasrat kami untuk bermain. Walaupun untuk kesenangan itu terpaksa kami harus meloloskan diri dari rumah secara sembunyi-sembunyi. Terkadang sampai harus jatuh terjerembab di tanah pasir di bawah rumah panggung kami karena melompat dari jendela. Tapi siapalah yang kuat hati tinggal di rumah hanya memandang hujan. Sementara suara celoteh dan tawa riang kawan-kawan sepermainan sayup-sayup terdengar nun di ujung sana.
Hujan akan membuat air sungai Rangkui yang jernih meninggi karena kiriman air dari tebat, danau buatan sejak jaman Belanda untuk retensi limpahan air di sebelah barat kampung Kacang Pedang sana. Menghilir hingga bermuara di Sungai Baturusa yang lalu akan memuntahkannya ke laut.
Itulah saat yang tepat untuk unjuk keberanian. Melompat sambil salto dari tepi jembatan, lalu berenang mengikuti arus sebentar hingga mencapai undak-undakan tempat para ibu mencuci pakaian, naik kembali ke pagar jembatan, lalu melompat lagi berulang-ulang. Hanya sesederhana itu. Tapi bagi kami sungguh kegembiraan tak terkira. Walaupun terkadang bila salah mendarat, punggung atau dada terasa pedas tertampar air. Tapi sesakit apapun, kami gengsi mengakuinya. Karena cuma akan jadi bahan tertawaan dan olok-olok kawan-kawan.
 Sumber foto: https://m[dot]tribunnews[dot]com/images/regional/view/303951/mandi-di-sungai-rangkui-pangkalpinang
Sumber foto: https://m[dot]tribunnews[dot]com/images/regional/view/303951/mandi-di-sungai-rangkui-pangkalpinang
Hanya di musim air pasang laut kami tak berani main di sungai. Tok Harun (atok: kakek) selalu mengingatkan kami. “Ikak jangan pernah mandi di sungai saat aik laut pasang. Banyak baye (buaya) dari muara masuk sampai sini.”
Lalu akan diulang-ulangnya lagi kisah yang selalu membuat kami bergidik itu.
“Jaman Atok agik kecit, ada kawan Atok disambar baye. Namanya Hasan, budak kampung Melintas. Kuteng (putus) sebelah kakinya sampai mata kaki. Tapi die selamat karena atok cepet narik die ke tangga. Baye tu agik neg ngejar Hasan. Ku trajang (tendang) ku, pecah matanya. Bedepeng (bergegas) baye tu lari masuk ke dalam aik!”
Kami saling melirik. Sedikitpun kami tak pernah percaya kisah Tok Harun menendang buaya sampai matanya pecah. Karena menurut analisa Pendi, saat Tok Harun mengatakan hal itu, cuping hidungnya kembang kempis. "Itu tanda-tanda orang sedang membual," kata Pendi dengan yakin.
“Orang kampung ramai-ramai ngejar baye tu. Due hari baru ketangkep di bawah jerambah (jembatan) jalan Pelipur. Di belah perutnya, agik ade kaki si Hasan.” Sambil bercerita, mata Tok Harun kadang menyipit, lalu tiba-tiba membelalak. Menakutkan! Membuat kami semakin ngeri membayangkan kaki Tok Hasan menyembul dari perut buaya.
“Ngape dak disambung agik kaki Tok Hasan?” Selalu ada yang biang kerok yang menyeletuk jahil di antara kami yang membuat kami terkikik-kikik. Tapi Tok Harun selalu menanggapinya serius.
“Aok mane pacak agiiik la. Ikak ni betanyak macem budak dak suah sekulah!” (yah mana bisa lagi. Kalian ini pertanyaannya seperti anak tak pernah bersekolah) seru Tok Harun kesal. Matanya semakin melotot. Kami sibuk menahan tawa.
“Kaki tu lah bindem (biru pucat) macam daging busuk. Kami bersihkan dan kafani baik-baik, lalu dikubur di belakang Mesjid Jami'. Waktu Hasan meninggal berpuluh tahun kemudian, kaki yang tinggal tulang tu diambik dijadikan satu dengan jenazah Hasan saat dimakamkan di pemakaman Kacang Pedang. Tu mimang pesan Hasan sejak dulu.”
“Lama Hasan dak nak sekolah dan main agik kek kami. Padahal Hasan anak pandai. Sering jadi juara kelas. Dia hanya mau ikut mamaknya yang setiap hari bejual pempek di Pasar Pagi. Cita-citanya untuk jadi pemain PSSI pun kandas. Padahal lah ade panggilan seleksi ke Palembang,” cerita Tok Harun sambil menghisap rokoknya, lalu melanjutkan memperbaiki tebik (jaring panjang seperti net bulutangkis untuk menghadang ikan) yang koyak tersangkut batu sungai.
Tok Harun memang sehari-hari mencari ikan di sungai Rangkui. Bila sore ia hanya menggunakan tanggok (serokan) untuk menjebak ikan betutu yang menempel di dinding sungai. Tapi bila malam, dipasangnya tebik melintang sungai. Besok pagi-pagi, sudah banyak ikan yang terjerat. Ada ikan palem, nila, lundu, gabus, baung, seluang, sepat siam dan juga udang lobster biru sebesar-besar ibu jari. Ikan-ikan yang masih kecil dilepasnya lagi. "Kelak men lah besak ka kutangkep agik ok," bisiknya kepada si ikan.
Kalau dapat udang lobster memang harganya lumayan. Orang membelinya untuk pengisi akuarium. Tetapi Tok Harun mencari ikan bukan untuk mata pencaharian. Pekerjaan utamanya menjual parang dan sering diminta orang untuk memperbaiki atau mengasah pisau, parang atau gunting.
Terkadang Tok Harun berbaik hati meminjamkan tanggoknya. Tapi menanggok udang tak mudah. Gerakan udang sangat cepat. Bahkan bisa melompat begitu kami baru saja mendekatkan tanggok. Maka kami lebih suka bermain air. Lagipula waktu main kami tak banyak. Sebelum azan Ashar terdengar dari menara Mesjid Jami', kami sudah harus bergegas ke mesjid karena pak Hamdi guru mengaji sudah menunggu. Kalau kami lalai terlambat mengaji dan orang tua kami tahu, minimal sebatan sapu lidi kabung (aren) tanpa ampun akan mendarat di betis hitam kami.
********

Pagi-pagi, sehabis solat Subuh di Mesjid Jami', kami berjalan di sepanjang Rangkui. Mulai dari jembatan jalan Kenangan, terus ke arah barat. Benar kata Pendi. Sepanjang yang kami lalui, Sungai Rangkui begitu kotor, banyak sampah dan berbau tak sedap. Tak ada lagi batang-batang kersen yang rimbun dan perdu serundung bulu yang memenuhi setiap jengkal tanah bantaran sungai yang kini sudah tertutup aspal dan konblok. Tak ada lagi sumber makanan yang mengundang burung serindit, pergam dan punai singgah sejenak melepas lelah.
“Macam mana nak bersih, tambang-tambang timah inkonvensional pakai rajuk (menghisap tanah dengan mesin pompa) sudah merambah sampai di tebat sana memuntahkan lumpur sepanjang hari. Tengoklah airnya. Pasti tercemar berat.” Kata Pendi bersungut-sungut. Aku tak menanggapi karena asyik menikmati setapak demi setapak jalan kembali ke masa silam.
Tak terasa, kami sudah sampai di Pasar Pagi. Ko Athet menyambut dengan wajah sumringah seperti biasa. Aku sudah mengenal Ko Athet sebagai pedagang kue sejak lama. Walaupun anak-anaknya sudah berhasil, di antaranya ada yang menjadi dokter di Jakarta, Ko Athet tetap setia berjualan kue.
Segelas taefusui (susu kedelai) panas sudah terhidang. Kami asyik menikmati kue-kue kampung yang tersedia. Sementara Ko Athet menyiapkan telur setengah matang pesanan kami sambil berceloteh akrab. Pasar Pagi semakin ramai dan penuh sesak. Teringat dulu di tahun 80an, tak ada pedagang yang mau berdagang di sini. Tempatnya terpencil, sunyi, dan berlokasi di hadapan pekuburan. 40 tahun sudah berlalu. Kota kami yang tua terasa semakin berbeda dan asing. Perubahan telah begitu cepat menghilangkan jejak-jejak masa lampau yang penuh kenangan manis bagi kami anak-anak kampung.
Dapatkan reward khusus dengan mendukung The Writers.
List Reward dapat dilihat di: https://trakteer.id/the-writers/showcase.












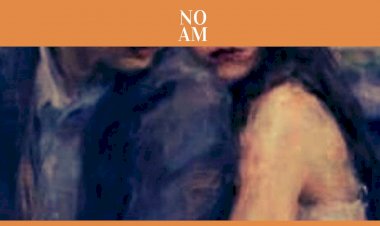























![[Cerbung] Perawan Sunti dari Bawono Kinayung #1-3](https://thewriters.id/uploads/images/image_380x226_5e6db0a9bea1f.jpg)




